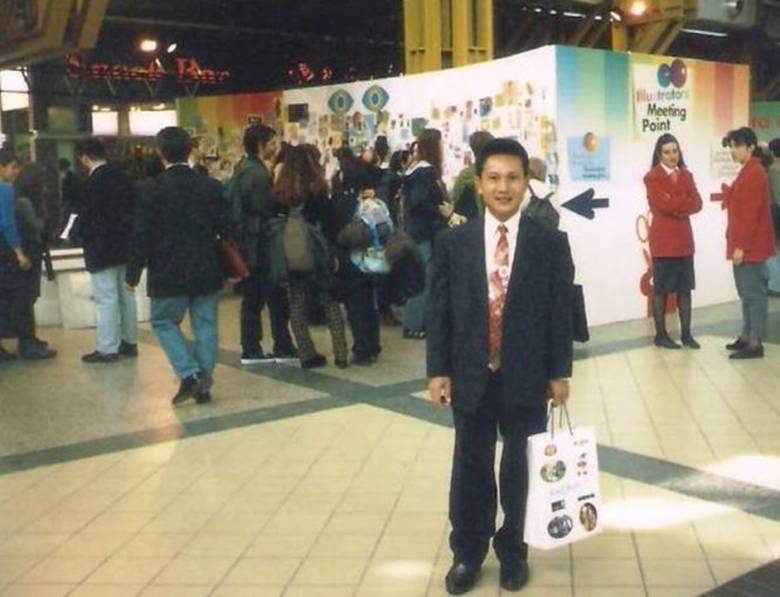Olimpiade Paris dan Kesetaraan

Umat Kristiani dunia seharusnya misuh-misuh dan murka atas pertunjukan parodi "The Last Super" pada upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 bernuansa pengkhinaan yang dilakukan kaum TBGL+ (Transgender, Bisexual, Gay, Lesbian) di sana. Nyatanya, mereka anteng-anteng saja dan tidak menganggap kreasi itu sebagai penghinaan, meski ada sedikit riak kecil saja, tidak sampai gerakan perlawanan atau ajakan boikot nonton olimpiade.
Apapun prinsip yang dianut oleh sebuah bangsa dan negara bernama Perancis dengan semboyan "Liberte, Egalite, Fraternite" atau Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan, tetaplah mereka harus memiliki kepekaan dan kecerdasan relativisme budaya. "Tepa slira" terhadap perasaan orang lain.
Euphoria kemenangan kaum kiri di Perancis yang keras memperjuangkan kaum miskin dan terpinggirkan itu menjadi semacam "pesta kemenangan" bagi kaum TBGL+ yang selama ini sangat gigih memperjuangkan persamaan hak di antara sesama ummat Gusti Allah, termasuk hak perkawinan sesama jenis yang sudah berpayungkan hukum positif di sejumlah negara. Bukankah ini buah dari kegigihan mereka selama ini dengan sponsor para konglomerat dunia termasuk Facebook ini?
Sebaliknya, di negara tertentu TBGL+ menjadi isu seksi untuk menarik minat dan perhatian pemilih. Karenanya, perjuangan TBGL+ masuk ke ranah politik, ujung-ujungnya ke undang-undang untuk melegitimasi keberadaan dan hak mereka.
Tetapi ketika "pesta kemenangan" ini mereka rayakan dengan menyisipkan pertunjukkan plesetan "The Last Super" yang dilakukan oleh kaum TBGL+ dengan kostum, aksesoris dan gaya penampilan yang khas, rasanya kebablasan juga. Olahraga sudah dicemari kepentingan politik mereka. Padahal, kebebasan tidak selayaknya berbuat sebebas-bebasnya, sebab kebebasan juga harus memperhatikan perasaan liyan, di luar apakah perasaan liyan itu tersakiti atau tidak.
Ingat kasus Salman Rushdie dengan novel "Ayat-ayat Setan"-nya yang jelas-jelas menghina umat Islam, kebebasan harus dibayar mahal dengan ketidakbenaran dirinya, di samping memicu kemarahan ummat Islam sampai kini. Nyawa Rushdie terancam kemanapun dia pergi. Buah kebebasan semacam inikah yang dikehendaki kaum TBGL+ dengan parodi "The Last Super"-nya itu?
Tetapi penghormatan terhadap orang dan lembaga, dalam hal ini lembaga keagamaan, tetap harus diperhatikan. Bukankah permintaan TBGL+ agar negara mengakui pernikahan sejenis juga setelah ada "kerelaan" lembaga agama tertentu. Dalam hal ini sebut saja Kristen Katolik. Mengapa rasa terima kasih TBGL+ malah ditunjukkan dengan cara penghinaan semacam itu? Apakah kreasi kaum TBGL+ di acara pembukaan Olimpiade Paris ini justru kontraproduktif bagi mereka di saat sejumlah negara sudah memberi mereka karpet merah?
Semangat Olimpiade yang seharusnya mengedepankan persamaan (equality), kejujuran dan keadilan (fair play), menjauhkan diri dari isu agama dan politik, malah dicemari kebebasan seturut persepsi kaum TBGL+ itu sendiri. Memang ada irisin di "persamaan", tetapi harus diingat prinsip ini tidak disandingkan dengan kebebasan berbuat sebebas-bebasnya.
Alih-alih Perancis yang selama ini menyanjung dan mengedepankan apa yang disebut "haut culture", dengan pertunjukan kaum TBGL+ yang difasilitasi di ajang pembukaan Olimpiade Paris itu mereka menampilkan prinsip kebalikannya, "budaya rendahan".
Tentu saja ada pihak yang sepakat dengan kreasi TBGL+ dengan argumen sebagai promosi nilai-nilai keterbukaan dan kesetaraan yang menjadi landasan Perancis, kemudian Negara melalui panitia Olimpiade Paris memberi wadah berekspresi tanpa mendiskriminasi identitas, termasuk identitas gender dan orientasi seksual di negara itu. Juga menolak anggapan bahwa itu bukan gambaran "The Last Super".
Dengan catatan yang saya buat sambil ngopi pagi ini, saya paham akan banyak kaum TBGL+ serta simpatisannya yang misuh-misuh, bahkan mungkin akun cadangan ini akan dilaporkan ramai-ramai ke Facebook dan datanglah vonis "menyalahi komunitas" itu yang memungkinkan sebuah akun ditutup untuk selamanya.
Tidak menjadi persoalan, tulisan ini lahir bukan atas dasar kebencian terhadap kaum tertentu, dalam hal ini TBGL+. Tetapi tersemat juga kebebasan mengeluarkan pendapat, jangan sampai mengkritik TBGL+ dianggap sebagai penghinaan. Kalau TBGL+ tidak boleh dikritik dan setiap kritikan dianggap penghinaan, apa bedanya dengan para diktator dan pemimpin zalim dunia yang pernah ada? Kecuali kalau tujuan mereka ingin dimasukkan sebagai golongan "orang suci" yang tak tersentuh.
Pepih Nugraha