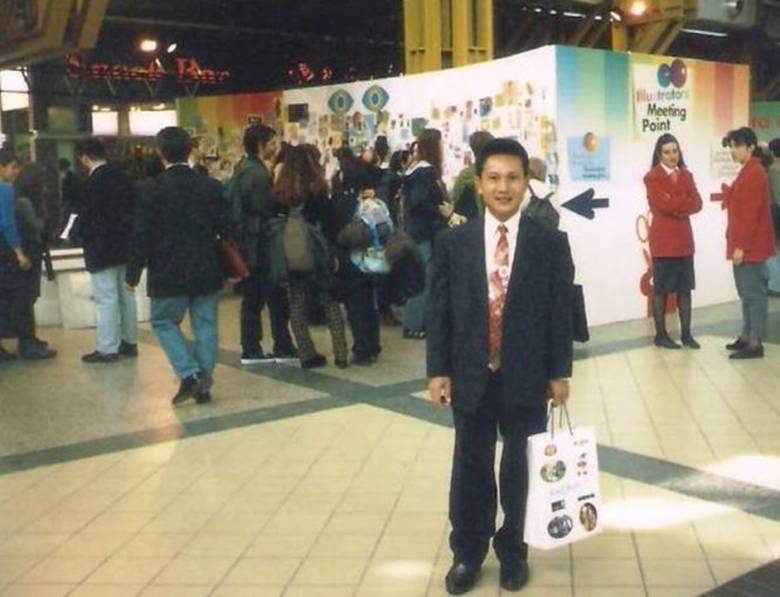Pendidikan Kita Cetak Anak-anak jadi Egois

Kata nenek moyang kita, masyarakat Indonesia adalah manusia-manusia yang gemar bergotong royong. Presiden pertama Indonesia Soekarno begitu bangga dengan karakter tersebut. Dalam banyak kesempatan, gotong royong menjadi salah satu karakter yang selalu didengung-dengungkan oleh Bung Karno. Apakah benar bangsa kita masyarakatnya berkarakter gotong royong?
Hasil observasi saya malah menampakkan fakta sebaliknya. Karakter gotong royong bangsa kita – saat ini – sudah terkikis dan berubah menjadi bangsa yang egois. Bahkan saya berani mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan masyarakat paling egois di dunia. Silakan menolak. Saya akan beberkan beberapa fakta dengan perbandingan negara lain.
Saya mulai dengan bidang olahraga. Mohon sebutkan prestasi Indonesia pada cabang olahraga yang membutuhkan kerja sama solid (semacam gotong royong). Adakah juara dunia asal Indonesia dalam cabang bola voli, bola basket, atau cabang olahraga lain semacam itu? Jangan sebut sepakbola.
Cabang olahraga terpopuler itu yang perlu kerja sama 11 orang di lapangan, tak pernah mencapai prestasi dunia. Asia pun tak. Kedodoran. Kita mengalami kesulitan dalam bekerja sama, bergotong royong, dan saling mempercayai. Negara lain yang konon disebut sebagai masyarakat individualistis, malah luar biasa hebat dalam kerja sama di lapangan bola.
Indonesia justru memiliki banyak juara dunia individual. Olahraga yang hanya membutuhkan kemampuan sendiri atau maksimal berdua. Atau yang tidak memerlukan terlalu banyak interaksi kerja sama saat bertanding. Kita pernah punya juara dunia tinju, juara dunia panahan, juara dunia paralayang, juara dunia panjat tebing, juara dunia jetski, dan yang paling sering juara dunia bulutangkis.
Baca juga: Sekolah Master di Inggris Modal 200 Foundsterling
Yang kedua, di bidang politik. Sebutkan jumlah partai politik di negara kita setelah Era Reformasi. Banyak ya! Pernah mencapai 48 parpol. Setiap pemilu silih berganti hadir parpol baru. Setiap ada yang mati, hadir lagi yang lainnya. Ketika seorang tokoh gagal di partai lama, dia keluar lalu bikin parpolnya sendiri. Manakala seorang presiden berasal dari suatu kekuatan, maka kekuatan lain akan berusaha sekuat tenaga menjelekkan presiden tersebut selama berkuasa. Demokrasi Indonesia saat ini malah menciptakan manusia-manusia egois untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Hal yang tidak terjadi di beberapa negara maju. Jumlah parpol mereka terbatas. Padalah orang-orang hebat di negara maju itu sudah pasti dalam banyak hal lebih hebat dibanding tokoh Indonesia. Minimal dalam hal sumber daya keuangan yang menjadi salah satu faktor penting suatu partai politik. Kalau menengok Amerika Serikat, dari dulu sampai sekarang parpol di negeri itu hanya dua: Demokrat dan Republik. Tak ada satu orang pun yang berniat membuat parpol baru. Konsensus nasional mereka memagari hal itu.
Kenapa kita menjadi begitu egois ya?
Pendidikan Dasar jadi Penyebabnya
Setelah saya obesrvasi dan pelajari lebih dalam, termasuk kepada diri sendiri, ternyata salah satu penyebabnya adalah pendidikan dasar kita. Sejak kecil saya sudah diajari bagaimana meraih peringkat di kelas. “Anak pintar!” begitu kata guru dan juga orangtua. Untuk meraih peringkat satu atau minimal 10 besar di kelas, tentu saja saya belajar keras. Pun ketika ujian berlangsung, saya menjadi manusia paling pelit sedunia. Ada teman yang mau melihat jawaban saya (nyontek), pasti saya pelototi dengan sangat. Saya menjadi manusia kompetitif. Jiwa dengan semangat mengalahkan orang lain. Setiap ujian adalah ajang pembuktian diri.
Namun di balik itu, karena terus menerus berlangsung sejak SD sampai SMA bahkan sampai kuliah, jiwa kompetisi dan “kepelitan” itu mendarah daging. Saya harus mengalakan seluruh teman di kelas. Saya harus menjadi juara kelas. Apalagi di keluarga juga kerapkali dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara. Baik saudara sekandung maupun para sepupu.
Pada saat yang sama, sekolah relatif jarang memberikan pelajaran dalam bentuk praktik bagaimana bekerja sama dengan baik. Kebanyakan teori. Kalau pun ada praktik bekerja sama dalam bentuk kerja kelompok, hanya sesekali saja. Tidak membekas. Mungkin hanya pelajaran ekstrakurikuler pramuka yang membentuk kita bagaimana cara bekerja sama dengan kawan, bergotong royong, dan membangun jiwa solidaritas. Tapi tak semua anak masuk ekskul pramuka bukan? Di keluarga juga sama. Kerja sama dan kolaborasi menjadi barang langka dalam pertumbuhan anak-anak Indonesia. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tercerabut dari akar budaya sukunya masing-masing. Tenggelam dalam ‘keluarga besar’ perkotaan yang kehilangan identitas.
Baca juga: Karakter para Penggila Kho Ping Hoo
Jiwa kompetitif itu bagus, pada suatu sisi. Namun menjadi negatif pada sisi yang lain. Jiwa kompettif harus juga dibarengi dengan beberapa hal:
· Peningkatan kualitas dan kapasitas diri. Bukan bagaimana mengalahkan orang lain, melainkan bagaimana mencapai potensi terbaik diri. Bukan bagaimana menjadi yang terbaik, melainkan bagaimana melakukan yang terbaik.
· Semangat berjuang. Semangat berjuang (fighting spirit) yang harus terjaga secara sehat. Lagi-lagi bukan bagaimana mengalahkan orang lain, tapi bagaimana mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Sampai optimal.
· Kolaboratif. Harus ditanamkan sejak belia bahwa manusia adalah makhluk sosial (homo socius). Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Penting bahkan sangat penting bagi seorang anak untuk memiliki jiwa kolaboratif. Dalam bidang pekerjaan apapun, selain kualitas dan kapasitas diri, diperlukan kerja sama tim (kolaborasi). Apalagi dalam membangun bangsa ini. Seperti kata Bung Karno, kita harus menggelorakan semangat gotong royong.
Kalimat di bawah ini begitu bagus menggambarkan bagaimana suatu kerja sama tim akan menghasilkan sesuatu yang lebih dahsyat. Konon, kalimat ini adalah kalimat mutiara dari Afrika.
“If you want to go faster, go alone. But if you want to go far, go together.” Silakan pilih mau cepat, tapi kemudian berakhir, atau mau melangkah lebih jauh. Suatu organisasi, suatu perusahan, suatu bangsa, pasti ingin melangkah jauh. Bukan sekadar cepat. Kita memang wajib piawai berkolaborasi.
Ubah Ruh Pendidikan
Beruntung sudah semakin banyak orang yang menyadari hal tersebut. Sudah muncul sekolah-sekolah yang memanusiakan manusia. Bukan hanya dicekoki dengan teori dan hafalan melainkan juga dengan lebih banyak praktik laiknya kehidupan nyata (real life education). Sejak belia anak-anak sudah mendapatkan pelajaran bagaimana seharusnya menjalani kehidupan nyata. Hal apa yang disebut sebagai pendidikan karakter.
Saya kadang malu berkaca pada negara lain yang seringkali kita sebut negara egois, tidak bermoral, dan sejenisnya. Akan tetapi mereka justru menerapkan pendidikan karakter terhadap anak sejak usia dini sampai 15 tahun kemudian. Di Jepang misalnya. Sejak pendidikan usia dini (PAUD), mereka sudah dilatih bagaimana bersikap. Ya, bersikap. Sikap yang menjadi dasar dari setiap tindakan. Sikap dan tindakan di toilet, sikap dan tindakan antri, sikap dan tindakan mengelola sampah, dan sebagainya.
Hal semacam itu juga terjadi di negara maju seperti Australia dan Finlandia. Di Australia, saya terpana melihat bagaimana sekolah dan keluarga mendidik mereka cara menghormati orang lain. Ketika orang lain bicara, diamlah. Baru bicara setelah orang lain diam. Di Finlandia, saya salut dengan sistem pendidikan problem solving sejak usia dini baik secara individu dan terutama secara bersama-sama. Tak ada ujian buat anak sekolah Finlandia sampai mereka berusia 15 tahun.
Tampaknya, kita tidak perlu memotong satu atau dua generasi untuk mengubah karakter egois masyarakat Indonesia. Tidak perlu. Apa yang kita hadapi dan rasakan sekarang akan berubah, jika sejak saat ini juga, kita mengubah cara mendidik anak menjadi manusia sosial yang sesungguhnya. Manusia sosial yang punya kualitas dan kapabilitas diri dilandasi oleh karakter kompetetif yang kolaboratif. Bukan manusia egois!
Generasi inilah yang akan mewarnai Indonesia. Kelak. Semoga.
***
Penulis adalah Asesor Kompetensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)