Melihat Novel Burung-Burung Manyar Melalui Sudut Historis
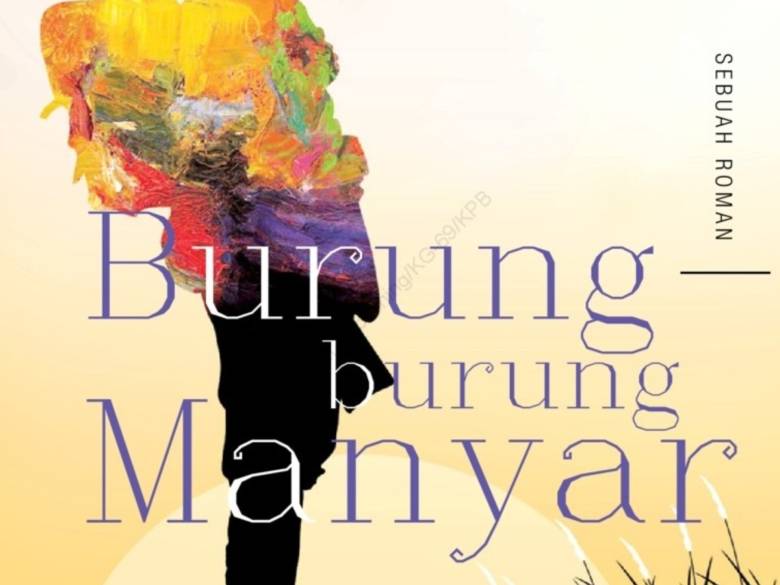
Melihat Novel Burung-Burung Manyar Melalui Sudut Historis
Tidak ada habisnya tema perjuangan menuju kemerdekaan diangkat pada tiap-tiap kisah dalam sebuah novel. Salah satunya pada novel Burung-Burung Manyar karya sastrawan Indonesia, Y.B. Mangunwijaya. Novel ini diterbitkan pada tahun 1976 dan menjadi salah satu karya sastra yang paling terkenal dan diakui di Indonesia. Dalam pendekatan historis, novel Burung-Burung Manyar dapat dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggambarkan keadaan sosial dan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini dianggap sebagai sebuah karya sastra yang memaparkan kritik sosial yang tajam terhadap kebijakan pemerintah Jepang pada masa itu, yang dianggap mengabaikan hak-hak rakyat kecil.
Novel Burung-Burung Manyar ini seperti menggambarkan keadaan Indonesia pada masa-masa sebelum dan setelah kemerdekaan. Rasanya, memperjuangkan kemerdekaan bangsa sebelum menjadi “Indonesia” sangat kental sekali dipaparkan dalam novel ini. Letnan Barjabasuki, ayah dari tokoh utama, Setadewa atau kerap disapa Teto, kepala II KNIL Belanda di Magelang, pergi ke medan perang, merantau, hingga meninggalkan keluarganya untuk ikut berjuang melawan penjajahan Belanda di tanah tumpah darahnya. Acap kali, mereka pun hidup berpindah-pindah untuk berlindung dari ancaman perang yang tiba-tiba datang ke daerah mereka.
Namun, sepertinya Teto tidak mengikuti jejak ayahnya, ia lebih memilih mengabdi kepada bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Bukan karena tak ingin, Teto mengabdi pada Belanda dan menjadi bagian dari KNIL semata-mata karena sangat ingin balas dendam terhadap penjajahan Jepang dan membenci pribumi yang berjongkok-jongkok di hadapan Jepang, pribumi yang mudah terhasut, yang terkadang tak kukuh pendirian ingin mendukung siapa, Jepang? Belanda? Atau sebenarnya ingin berjuang melawan penindasan dan merdeka menjadi Republik Indonesia? Bahkan, tak jarang pribumi yang terlalu tunduk terutama kaum wanita menjadi gundik para Jepang agar dirinya tidak ditindas.
Memilih pergaulan yang positif dan memperbanyak relasi nyatanya telah diajarkan sejak dahulu oleh para sastrawan Indonesia dan diangkat pada alur kisah karya sastra mereka. Sejak dahulu, memang pada awalnya, semua penduduk Indonesia bermatapencarian hanya pada sektor agraris, terlihat juga pada kutipan berikut: “Semua raja Jawa itu aslinya hanyalah petani biasa” (Mangunwijaya, 2014:8).
“...dan kalau tidak salah Papi bilang tentang pengalaman hidup praktis, kelak si anak, kalau jadi komandan atau pegawai tinggi, dapat beruntung berkat pergaulan dengan lapisan bawahan dan sebagainya atau semacam itu” (Mangunwijaya, 2014:8).
Pada masa itu, mereka selalu mempunyai cara agar tidak tertangkap atau bersembunyi dan berdalih supaya dalam masyarakat mereka tidak serta-merta hilang begitu saja. Agaknya, setiap tokoh yang terdapat dalam novel ini acap kali saling berhubungan dan tidak terlepas dari alur kisah masa lalu. Meskipun beberapa tokoh tidak berpegang pada aliran sesat, akan tetapi lebih banyak diceritakan tokoh-tokoh yang memegang teguh kepercayaan dengan hal mistik dan alam gaib pada alur cerita dengan tema sejarah seperti ini. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka pun melalang buana berjuang penuh untuk mencari nafkah, hal ini tampaknya terus berlanjut hingga kisah-kisah historis selanjutnya dan terjadi di kehidupan nyata masyarakat Indonesia.
Ternyata, saya terus menemukan pada setiap judul cerita sejarah yang pernah saya baca, hal-hal antek Jepang yang menjadikan kaum wanita pribumi sebagai gundiknya dengan jaminan mereka dapat hidup aman pada tiap-tiap karya sastra yang mengusung tema historis. Layaknya kisah Siti Nurbaya, perihal perjodohan pun kerap kali terjadi pada setiap cerita yang mengangkat tema sejarah dengan dalih “orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya”, termasuk pada novel Burung-Burung Manyar ini. Keterpaksaan pun mendorong seorang anak yang mau tidak mau harus menerima keinginan orang tuanya supaya tidak terjadi perdebatan panjang, walaupun pada akhirnya mereka saling mencintai dan seolah menemukan cinta sejatinya.
Menurutku, soal politik pun sama bahayanya dengan masalah cinta segitiga, atau bahkan lebih dari itu. Penceritaan sang tokoh yang kurang “terbuka” demi melindungi keluarganya kerap terjadi dalam sudut historis seperti ini. Maka tak jarang, strategi perang dan persembunyian seperti gerakan bawah tanah pun sering dilakukan oleh tokoh pada setiap sudut historis yang berbeda judul cerita.
Mengecam pendidikan juga berperan penting dalam proses pendewasaan diri dan menambah wawasan, sehingga kita bisa mempraktikkan dan berbagi ilmu yang kita dapatkan kepada masyarakat sekitar dan orang yang membutuhkan. Hidup mandiri dengan mencari nafkah sendiri dan meringankan beban orang tua bahkan sudah diajarkan sejak terdahulu oleh sastrawan senior seperti Y.B. Mangunwijaya. Bahkan, sifat dan kepribadian manusia pun nampaknya telah diajarkan sejak lama, seperti sikap jujur dan tidak bermuka dua atau munafik. Terkadang lain dimulut lain dihati, banyak orang yang kerap menjadi penjilat terhadap musuhnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, terlihat pada kutipan berikut:“Aku tipe anak kolong yang sejak kecil punya kode etika berterus terang. Lebih baik berkelahi berbahasa kepal dan tendangan kaki daripada bohong dan pura- pura” (Mangunwijaya, 2014:40).
Perilaku lain dalam mengisi kemerdekaan berupa memerangi masalah kemiskinan, pola hidup rakyat, pejabat, serta penyelewengan yang dilakukan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sepertinya, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) ini pun terus berlanjut terjadi dalam dunia politik Indonesia hingga sekarang. Kemudian, cara berpakaian Noni dan nyonya Belanda yang bebas menurutku sangat menarik karena mereka tidak dituntut untuk menjadi sempurna dan segalanya sudah diatas hukum, terkecuali putri ningrat Jawa.
Hal menarik lain yang saya dapatkan dari novel Burung-Burung Manyar, bahwa kita juga diajarkan untuk tidak menilai sesuatu dari luarnya saja. Agaknya, akan lebih baik jika kita menjadi jiwa-jiwa yang berterus terang dan apa adanya. Ibarat kata, seperti kutipan dalam novel Burung-burung Manyar ini: “Lebih baik berkelahi berbahasa kepal, dan tendangan kaki, daripada bohong dan pura-pura” (Mangunwijaya, 2014:40).
Rasa-rasanya, suatu karya sastra akan sangat menarik dan bermakna jika karya tersebut dapat menyuarakan kenyataan yang terjadi di kehidupan nyata dalam bermasyarakat. Novel Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya ini agaknya layak untuk terus dilestarikan agar kalangan milenial pun masih dapat terus mengulas kembali isi novel ini.
Oleh: Ayda Nur Haliqa



