Mempertanyakan Arah Pendidikan
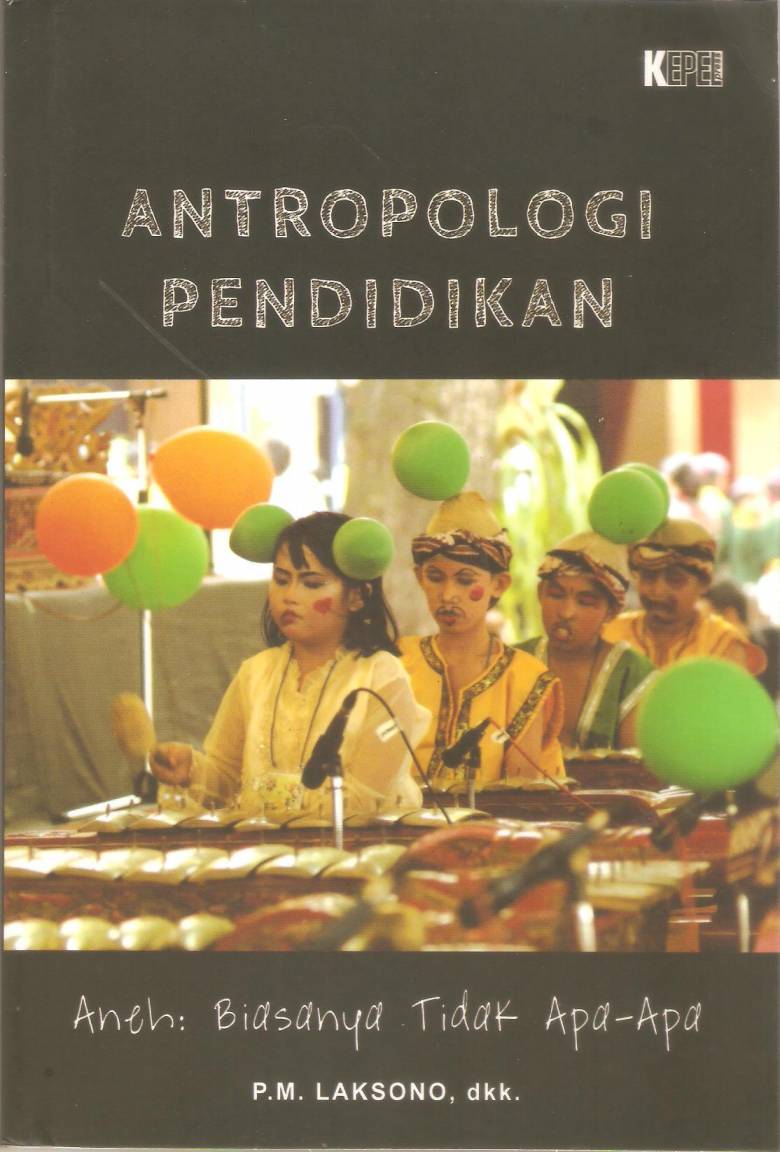
Judul: Antropologi Pendidikan
Penulis: P. M. Laksono, dkk
Tahun Terbit: 2015
Penerbit: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajahmada dan KEPPEL Press
Tebal: xiv + 170
ISBN: 978-602-356-043-1
“…sebenarnya yang dipentingkan dalam pendidikan adalah prosesnya dan bagaimana setiap siswa mampu melalui proses tersebut. Namun yang terjadi saat ini adalah salah kaprah ketika pendidikan hanya dilihat dari hasil akhirnya saja dengan melihat skor atau nilai dalam bentuk angka untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan seseorang. (hal.27)”
Bagaimana hubungan pendidikan dengan kebudayaan sebuah bangsa? Apakah pendidikan seharusnya mengajarkan kebudayaan, atau pendidikan membentuk kebudayaan? Atau pendidikan sekadar bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam kebudayaan? Sebelum kita menjawab hal tersebut, baiklah kita telaah dulu apa arti kebudayaan dan apa konsepnya. Kemudian kita lihat juga apa arti pendidikan dan apa konsepnya. Barulah kita bisa menjawab pertanyaan di atas.
P.M. Laksono mengutip pendapat Ki Hajar Dewantoro sebagai defisini kebudayaan yang sangat tajam. Kebudayaan adalah “pernyataan batin masyarakat yang mencipta melalui perseorangan” (hal. 6). Definisi ini oleh Laksono dianggap sebagai sebuah pernyataan arti kebudayaan yang sangat tajam daripada definisi yang sekarang ini dipakai. Sebab definisi ini mewadahi semua hal yang dipikirkan, dihasilkan dan dilakukan oleh perseorangan dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi sumber dari semua itu. Kebudayaan bukan sekedar sistem gagasan saja. Kebudayan menjadi teladan (momong), prakarsa (among), dan fasilitator (ngemong). Konsep kebudayaan dilihat sebagai usaha untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan, terus-menerus mengaktualkan kehidupan, bukan sekedar melestarikan masa lalu (hal. 99). Sasaran konsep kebudayan adalah agar identitas kita tetap, lestari, ajeg dan asli, namun di saat yang sama berubah, dinamik, plural, dialektik (taktis bersejarah) (hal. 15).
Pendidikan harus dimaknai lebih luas daripada sekedar persekolahan. Sebab seseorang bisa mendapat pengetahuan dan keterampilan baru bukan hanya dari sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, asal ada sistem untuk seseorang bisa belajar, maka mereka akan bisa mendapat pengetahuan dan keterampilan baru tersebut. Bahkan mengembangkannya. Pendidikan yang bagaimana? Meminjam Panca Dharma dari Taman Siswa, Pendidikan haruslah menyadari bahwa manusia adalah bagian dari Kodrat Alam, mengupayakan Kemerdekaan, memelihara Kebudayaan, mempertahankan Kebangsaan dan mengajarkan Kemanusiaan (hal. 30). Seluruh proses pendidikan haruslah mengarah kepada lima hal tersebut.
Oleh sebab itu pendidikan harus menjadi cerminan kebudayaan dan sekaligus cerminan terhadap perubahan kebudayaan (hal. 6).
Terus apa pentingnya Etnografi Pendidikan? Etnografi pendidikan adalah alat untuk melihat keanehan-keanehan yang terjadi dalam pendidikan (hal. 16). Bukan itu saja, etnografi pendidikan bisa menunjukkan arah pendidikan yang diinginkan. Setidaknya dari kacamata para antropolog.
Budi Satriawan mengangkat kasus Tamansiswa, sebuah bentuk pendidikan (persekolahan) yang Indonesia. Tamansiswa didisain oleh Ki Hajar Dewantoro untuk melawan pendidikan barat yang individualis dan kolonialis. Tamansiswa berfokus pada proses belajar dan bukan hasil semata. Namun Tamansiswa kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain, khususnya setelah era reformasi. Budi Satriawan menemukan setidaknya tiga hal yang menyebabkan Tamansiswa mengalami kemunduran, yaitu (1) orientasi orangtua yang telah berubah dalam memilih sekolah. Orangtua sekarang lebih memilih sekolah yang tidak lagi pada sekolah yang nasionalis, tetapi sekolah yang kebarat-baratan dan kemudian sekolah yang pengajaran agamanya kuat (hal. 37); (2) orientasi guru professional yang tidak lagi sesuai dengan prinsip guru (pamong) Tamansiswa.
Guru di Tamansiswa harus tidak berjarak dengan muridnya. Bahkan di luar jam sekolah, guru tetap harus menjadi pamong bagi murid-muridnya. Guru professional saat ini merasa bahwa mereka orang professional yang dibayar sesuai dengan keahliaannya dan sesuai dengan jam kerja (hal. 41); dan (3) adanya intrik-intrik di dalam Tamansiswa sendiri (hal. 43).
Urip Danu Wijoyo memotret perubahan pengasuhan anak dari keluarga ke sekolah melalui percakapan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sibuk mencari PAUD untuk anak-anak mereka. Dalam percakapan-percakapan yang dicatat oleh Urip Danu Wijoyo, terungkap bahwa pemilihan sekolah (PAUD) didasarkan kepada sekolah yang mampu memberikan pengasuhan, menggantikan peran keluarga. Pengasuhan dalam arti pembentukan sikap, urusan makan, pengajaran dan semua hal perkembangan anak. Orangtua hanya melahirkan, memberi makan tapi jiwa dan pikirannya menjadi milik orang lain (hal. 52).
Ami Priwardhani mendiskusikan tabrakan gagasan tentang anak melalui penelitiannya di Ende. Harus diakui bahwa PAUD adalah budaya barat yang dibawa ke Indonesia. PAUD dibangun dengan nilai-nilai barat. Barat menempatkan anak sebagai aset yang berharga bagi masa depan. Anak dibawah umur 7 tahun adalah masa keemasan. Oleh sebab itu anak pada usia dibawah 7 tahun harus mendapat asupan gizi yang baik, pendidikan yang berpusat pada anak. Sementara anak dalam kebudayaan Ende adalah berada di lapisan paling bawah. Anak tidak dilibatkan dalam segala urusan sosial. Pendapat anak tidak dihargai sama sekali. Anak mendapat makanan seadanya, makanan terbaik adalah untuk orang dewasa (laki-laki).
Dua nilai yang berseberangan ini tercermin dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Ende. Guru-guru dilatih dengan standar barat. Guru-guru tersebut rata-rata adalah ibu-ibu lokal yang juga memiliki anak. Akibatnya mereka menerapkan cara barat secara formal dan cara Ende secara informal dalam mengajar (hal. 77). Gagasan tentang masa keemasan, yang seharusnya memfasilitasi anak untuk berkembang imajinasinya, justru dipakai untuk kepentingan lokal tentang apa yang dianggap penting untuk sukses di masa depan. Kedua hal yang dianggap penting di masa depan bagi warga Ende adalah kalau anak bisa berbahasa Indonesia dan bisa mengaji dalam Bahasa Arab. Itulah sebabnya di TK pelajaran difokuskan kepada pengajaran Bahasa Indonesia dan berbagai doa dalam Bahasa Arab. Anak harus belajar dua bahasa asing di masa keemasannya (hal. 78).
Kurikulum yang seragam juga membuat PAUD di Ende menjadi tidak bermakna sama sekali bagi anak. Ami Priwardhani memberi contoh tentang seorang guru yang bertanya apa yang terjadi kalau hujan datang terus-menerus. Anak menjawab akan datang gelombang. Guru menyalahkan anak karena jawaban yang diharapkan (seperti yang ada di dalam buku teks) adalah banjir. Sementara anak menjawab dengan pengalamannya sehari-hari yang hidup di tepi pantai (hal. 83).
Transpiosa Riomandha mendiskusikan krisis akulturasi keluarga Jawa dalam pendidikan. Dia mengangkat kisah Zora, anak pasangan Jawa yang ketakutan ulangan Bahasa Jawa. Di sekolah, pengajaran Bahasa Jawa telah menjadi pelajaran Bahasa Asing bahkan bagi anak-anak pasangan Jawa di Jogjakarta (pusatnya Budaya Jawa). Sebab orang Jawa telah menjadi Indonesia. Bahasa Jawa sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu bagi anak-anak Jawa. Kalaupun masih dipakai, unggah-ungguh berbahasa sudah banyak ditinggalkan. Sementara anak, dalam pelajaran Bahasa Jawa diminta kembali menjadi Jawa di masa lalu (hal. 97).
Apakah tujuan pengajaran Bahasa Jawa kepada anak-anak adalah supaya anak-anak bisa menggunakan Bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari? Jika ya, dimana mereka bisa menggunakannya? Jika tidak untuk apa pelajaran Bahasa Jawa masih diberikan, kalau akhirnya hanya tersisa dalam bentuk angka di rapor anak, dan sesudahnya dilupakan begitu saja?
Kiki Koesuma Kristi membahas ketidak mampuan sekolah dalam menghubungkan apa yang dipelajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Suci hamil karena tidak tahu bahwa berhubungan badan dan mengeluarkan sperma di dalam vagina akan menyebabkan kehamilan. Padahal Suci mendapatkan pendidikan alat-alat reproduksi di pelajaran biologi sejak SMP. Sekolah yang berorientasi kepada hasil akhir, yaitu angka dalam rapor menyebabkan proses pembelajaran yang tergesa-gesa dan bersifat di permukaan saja. Ilmu pengetahuan hanya dihafal untuk ujian, bukan dimaknai sebagai landasan untuk bertindak yang lebih arif (hal. 107).
Sementara pelajaran seks yang sesungguhnya terjadi di antara para remaja itu sendiri. Mereka saling menceritakan pengalamannya dalam berpacaran dengan berbagai istilah yang mereka buat sendiri.
Aant Subhansyah membawa berita bagus dari Gunungkidul. Sekolah Pagesangan adalah sekolah alternative berbasis masyarakat setempat. Konsep belajar yang dipakai adalah belajar untuk komunitas. Konsep ini berbeda dengan sekolah pada umumnya yang bertujuan membentuk individu untuk mampu masuk dalam modernisasi/industrialisasi (hal. 130). Dalam proses belajar, Sekolah Pagesangan menggunakan proses-proses sehari-hari yang terjadi di komunitasnya, seperti menanam pohon, membuat gaplek dan sebagainya. Mereka mempraktikkan dan mempelajari, bagaimana supaya proses-proses tersebut menjadi lebih baik. Namun sayang sekolah semacam ini hanya diminati oleh mereka yang miskin dan terpaksa karena tidak memiliki pilihan ke sekolah umum.
Berbagai potret ‘keanehan’ dunia pendidikan telah berhasil dibuat melalui Antropologi Pendidikan. Dalam catatan akhir, Primanto Nugroho menggaris bawahi lima hal, yaitu: (1) kisah-kisah dari orangtua dan anak sudah diabaikan dan digantikan dengan angka-angka statistik, (2) gagasan-gagasan alternative yang inovatif dari komunitas sering tergerus oleh kekuasaan negara, (3) pendidikan anak terlepas dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya, (4) sekolah dianggap sebagai administrasi negara yang begitu saja dijalankan, (5) pendidikan hendaknya dikembalikan sebagai cerminan budaya dan cerminan perubahan budaya.
Potret buram di atas sangatlah mengkhawatirkan. Namun kita tak harus terlalu khawatir. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang ini, sepertinya sadar akan kesalahan yang telah diungkap di atas. Kementerian berupaya mengembalikan guru sebagai guru yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu insan pembelajar yang mengabdi. Kementerian mencoba memberi kebanggaan kepada guru dengan memberikan penghargaan-penghargaan di luar numerasi. Kementerian juga berupaya membangun ekosistem pendidikan yang memberi peluang kepada semua pihak untuk terlibat dalam menentukan arah pendidikan. Berbagai bentuk diskusi antara masyarakat dengan kementerian dilakukan. Data dan informasi yang dimiliki oleh kementerian dibuka untuk dibaca oleh masyarakat secara online. Kementerian juga membuat Direktorat Jenderal PAUD-Dikmas untuk memberi pengetahuan kepada orangtua dan masyarakat terlibat aktif dalam proses pendidikan anak-anaknya. Namun semua yang dirancang tersebut barulah permulaannya, perubahan masih sangat jauh di depan. Seperti pernah disampaikan oleh Anies Baswedan dalam sebuah pertemuan: “Saya ini menakhodai kapal tanker yang panjangnya 180 meter.
Saat saya sudah memutar kemudi, beloknya baru terjadi 7 km di depan. Jadi kita harus sabar kalau kita belum melihat perubahan. Kalau tidak sabar kita akan memutar kemudi lagi, dan akhirnya malah tidak jadi berbelok.” Jadi kita harus menunggu 7 tahun, sementara masa jabatan menteri hanya 5 tahun. Bagaimana ini?
***



