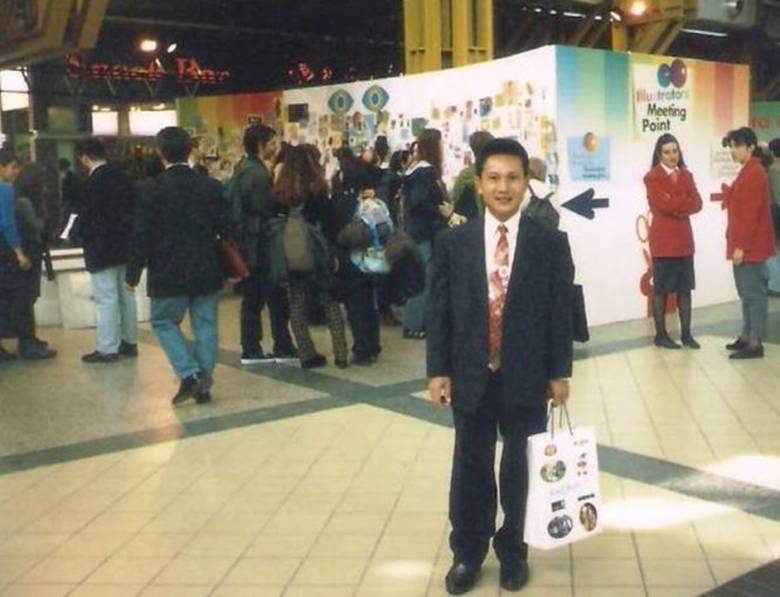Serial Kebangsaan (8) Menakar Fenomena Roy-Jeje dan Simulakra

Tiba-tiba penciuman jurnalisme busana Jepang bekerja, mereka mengendus sesuatu yang menarik di Jakarta. Berita.
Bukan berita tentang peristiwa besar, melainkan sekadar fenomena yang tidak biasa. Karenanya memiliki nilai berita.
Jurnalis negeri matahari terbit itu membaui adanya riak sosial yang tidak biasa, yang diperagakan anak-anak muda luar kota Jakarta lewat CFW, Citayam Fashion Week.
Belum sampai gerakan sih, tetapi riak itu melengkapi dirinya dengan ikon ciptaan yang sengaja dimunculkan lewat pasangan Roy-Jeje.
Roy disosokkan sebagai anak muda ganteng yang digilai-gilai lawan jenis. Tongkrongan Roy tidak sama dengan Roy Marten, pemuda tampan idaman kaum hawa di tahun 1970-an, juga bukan sosok “Si Boy” yang sudah cakep tajir pula, yang disosokkan lewat sebuah film pada masanya.
Roy van Citayam ini sesungguhnya anak tanggung yang tampil malu-malu dengan busana ala kadarnya. Tapi tubuh Roy mengandung perekat, buktinya Jeje sampai lengket begitu.
Diorkestrasi atau tidak, sengaja diskenario atau tidak, fenomena Roy-Jeje dan CFW telah memunculkan ambiguitas baru dalam penamaan SCBD.
Jika sebelumnya orang mengenal singkatan itu sebagai Sudirman Center Business District, akhir-akhir ini barangkali netizen lebih mengenal SCBD sebagai Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Lihat, betapa perkasa pikiran manusia atas teks!
Menurut media busana Jepang yang kemudian menulis fenomena ini, "catwalk" terbuka CFW tak ubahnya Harajuku di jantung kota Tokyo yang juga sering menggelar acara serupa.
Roy-Jeje mewakili anak-anak muda pinggiran yang bukan penduduk asli Jakarta, tetapi memanfaatkan ruang publik Jakarta sebagai arena unjuk eksistensi dirinya.
Roy-Jeje mungkin tidak paham filosofi Jurgen Habermas mengenai "public sphere" sebagai ruang pelarian demokrasi yang sering terkooptasi lembaga formal dalam hal ini negara. Mereka hanya berkreasi begitu saja. Boleh jadi cuma dituntun naluri, tanpa bekal pengetahuan yang memadai.
Benar, Roy-Jeje dan anak-anak muda SCBD lainnya tidak memanfaatkan ruang publik sebagai saluran pemikiran sebagaimana yang dikehendaki aktivis Mazhab Frankfurt tersebut, melainkan sekadar panggung terbuka untuk membuat konten.
Ya, Roy-Jeje dan kawan-kawannya itu adalah apa yang hari-hari belakangan ini disebut “content creator”. Kata “creator” yang disandang istilah yang merebak pasca kelahiran media sosial itulah mau tidak mau memaksa Roy-Jeje kreatif, sekreatif mungkin. Bahkan kreativitas yang tidak biasa, yang ternyata bisa mencuri perhatian publik.
Roy-Jeje juga tidak tidak berpretensi mengejek kelas menengah-atas Jakarta yang seolah-olah sedang memasuki dunia simulakra-nya Jean Baudrillard, dunia simulasi yang menjadi kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Roy-Jeje sedang berjalan di dunia nyata!
Roy-Jeje tidak sedang berpura-pura, juga bukan korban iklan yang dimuntahkan media massa atau media sosial sehingga mereka terjebak dalam “konsumsi simbol”, di mana orientasi konsumsi yang semula ditujukan untuk kebutuhan hidup menjadi sekadar gaya hidup.
Setidak-tidaknya demikianlah Baudrillard menggarisbawahi pendapatnya.
Roy-Jeje juga bukan apa yag disebut T. Veblen sebagai penikmat kelas alias "leisure class" yang gemar mengonsumsi produk-poduk kapitalis di lapangan.
Coba saja tanya Roy tentang "outfit" yang dikenakannya. Busana paling mahal yang ia pakai adalah jaket seharga Rp130.000 yang ia beli di pasar. Bagi anak-anak "borju" Jakarta, jumlah uang sebesar itu tidak cukup untuk menikmati satu "cup" Starbucks dan beef mushroom panini sekali duduk.
Roy-Jeje tampil apa adanya tanpa berpretensi menjadi kelas penikmat atau sedang memasuki dunia simulasi. Mereka juga bukan menjadi masyarakat tontonan (spectacle society) yang gemar bertukar simbol tadi. Simbol apa yang mereka mau pertukarkan, wong mereka tampil apa adanya begitu?
Sebagian orang yang melihatnya justru yang tidak biasa, yang memandang sinis kehadiran anak-anak muda pinggiran yang merangsek Jakarta seperti Roy-Jeje. Sinis karena mereka tidak serta-merta mampu menciptakan tren baru dalam pergaulan sosial maupun dalam berkreasi. Mereka tetap "no one", sementara dalam tataran tertentu Roy-Jeje sudah menjadi "someone".
Buktinya seorang menteri, sebut saja Sandiaga Uno, menawari beasiswa buat Roy. Maksudnya baik, memberi kesempatan Roy berkreasi lebih lanjut.
Tapi, niscaya Roy menolak karena merasa tidak membutuhkannya. Yang ia butuhkan sekadar "ruang publik" di mana ia dan kawan-kawannya bisa mengekspresikan karyanya dalam membuat konten.
Kalau akhir-akhir ini kehadiran anak-anak muda SCBD itu diganggu aparat keamanan sampai harus dibubarkan segala, sesungguhnya aparat seperti sedang mempertontonkan bahwa mereka seperti tidak ada pekerjaan saja.
Roy-Jeje dan anak-anak SCBD sedang melakoni kehidupan nyata, bukan sedang main drama tembak-tembakan sadistis yang mengakibatkan nyawa manusia melayang secara tragis.
Slebeeew....
**"