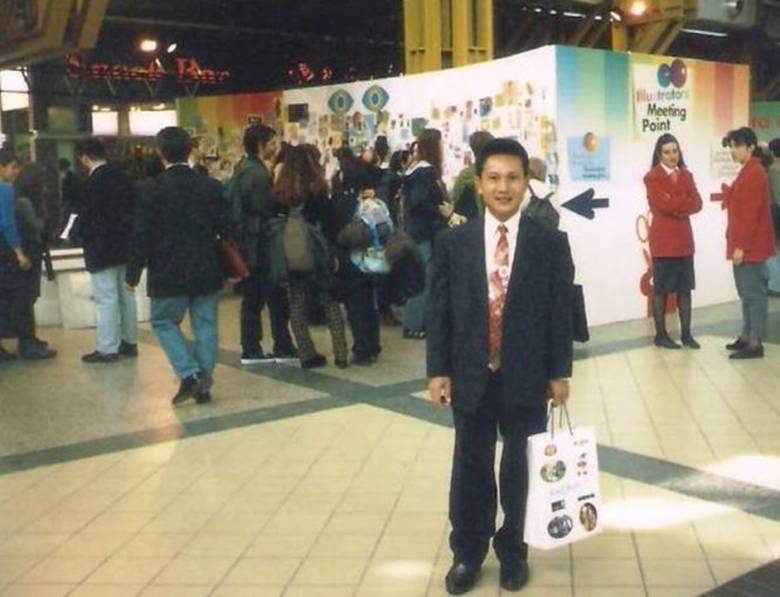Saya dan Agama

Permenungan saya mengenai hal-hal sensitif tentang agama yang selama ini tabu di angkat ke permukaan bukan terjadi kemarin sore, bahkan sejak saya duduk di bangku sekolah menengah pertama.
Tanpa ada yang mengajari, dengan pengetahuan terbatas, dan tanpa buku bacaan berkelas saat itu saya mulai bertanya; mengapa saya harus beragama? Lalu, adakah manusia selain saya di dunia ini yang tidak bergama?
Memang pertanyaan sederhana, tetapi manakala saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya merasa pemikiran saya terlalu jauh melompat ke hal-hal yang belum seharusnya saya pikirkan di saat teman-teman seusia asik bermain dingdong atau mencuri-curi baca buku stensilan Enny Arrow. Pertanyaan ini menggumpal tanpa bisa saya tanyakan kepada orangtua sendiri, pertanyaan yang tak menemukan jawaban.
Sampai kemudian terjadi hal yang menghantam kesadaran saya tentang agama dan beragama saat berkesempatan mengunjungi Eropa untuk pertama kalinya di tahun 1997. Saat itu, petinggi Muhammadiyah Lukman Harun -yang secara politis berseberangan dengan Amien Rais di tubuh organisasi Islam itu- mengajak saya melihat sejumlah gereja yang bangkrut di Amsterdam, Belanda, karena ditinggalkan pemeluknya.
Gereja itu kemudian diakuisisi oleh organisasi Islam dan dijadikan masjid. Wah, ini seperti "Perang Salib" dalam bentuk lain, pikir saya.
Saya ditugaskan oleh Harian Kompas untuk meliput peletakan batu pertama Masjid Soeharto di Bosnia-Herzegovina, sebagaimana tertulis dalam undangan. Sementara kunjungan ke Belanda merupakan “en passant” atau sambil lalu dan tidak ada di agenda liputan. Akan tetapi, saya diajak Lukman Harun justru untuk melihat kenyataan di Eropa di mana banyak gereja bangkrut karena ditinggalkan umatnya!
Sambil berjalan santai di kota Amsterdam yang sebelumnya hanya bisa saya lihat lewat gambar atau tayangan video, saya bertanya mengapa banyak gereja bangkrut di Eropa. Lukman Harun menjawab bahwa mereka, orang-orang yang meninggalkan gereja itu, ada yang sekaligus meninggalkan agamanya juga.
“Ada yang menjadi atheis, ada yang menjadi agnostik, tetapi mungkin ada juga yang menjadi mualaf masuk Islam hahaha…” katanya sambil “ngakak” di akhir kalimatnya.
Lukman memang biasa bicara apa adanya tanpa sungkan. Tetapi ketika saya bertanya apakah hal itu terjadi pada Islam dan masjidnya, ia agak lama berpikir. "Wah, saya kurang paham, tetapi mungkin saja ada tetapi saya tidak tahu di mana," katanya.
Kalau mereka keluar dari agamanya dan tidak lagi meyakini agamanya, tanya saya kemudian, apakah berarti mereka menjadi atheis. Lukman menjawab, “Tidak juga. Ada yang tetap meyakini Tuhannya, tetapi tidak terhadap agamanya.”
Meyakini Tuhannya, tetapi tidak agamanya? Menarik banget, bisik batin saya.
Saya cukup memahami ucapan Lukman Harun di saat saya sudah dibekali bacaan secukupnya, salah satunya “Sejarah Tuhan” (A History of God) karya Karen Armstrong versi Bahasa Inggris yang saya baca di Perpustakaan Harian Kompas.
Di kemudian hari, saya membaca laporan Pew Research yang menunjukkan secara global jumlah orang yang tidak terafiliasi dengan agama apapun, termasuk ateis, agnostik, atau mereka yang menyatakan “nothing in particular”, meningkat dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi sekitar 1,9 miliar pada 2020.
Ini berarti porsi populasi tidak beragama naik dari 23,3% menjadi 24,2% dalam dekade tersebut. Dengan kata lain sekitar 1 dari 10 orang dewasa di bawah 55 yang dibesarkan dalam agama kini tidak lagi berafiliasi dengan agama apapun. Sedikit sih dibanding jumlah penduduk dunia.
Disebutkan, Kristen dan Buddha menjadi dua kelompok yang paling banyak beralih menjadi "unaffiliated" di banyak negara Barat dan Asia Timur. Namun Hindu dan Islam menunjukkan tingkat “switching” jauh lebih rendah, dengan mayoritas tetap mempertahankan agama asalnya.
Ini sekaligus menunjukkan meskipun dunia secara keseluruhan tetap mayoritas beragama, tren ke arah ketidakberagamaan atau non-religius terus tumbuh di banyak negara terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur.
Ketika Mulai Bertanya tentang Agama
Saya lahir di sebuah kampung di Tasikmalaya, Jawa Barat, di sebuah negeri yang ramah pada doa. Di Indonesia, agama bukan sekadar keyakinan. Ia merupakan identitas sosial, tercetak di KTP, hadir di upacara kenegaraan, bahkan ikut menentukan apakah seseorang dianggap “orang baik” atau tidak. Di negeri ini, sulit berkata “saya ragu” tanpa segera dicurigai.
Saya dibesarkan sebagai Muslim. Sejak kecil saya diajari menghafal doa sebelum memahami maknanya, diajari mengaji dan diwajibkan salat. Saya disuruh taat sebelum diajak berpikir dan saya menjalaninya dengan ketaatan.
Tidak ada yang salah dengan itu hingga suatu hari saya mulai bertanya. Bukan bertanya untuk membantah Tuhan. Saya bertanya karena ingin mengerti. Dalam Islam, saya diajari bahwa iqra’ (bacalah) adalah wahyu pertama. Tapi dalam praktik sosial, membaca terlalu jauh sering dianggap berbahaya.
Bertanya tentang tafsir, sejarah, atau konteks ayat bisa cepat diberi label liberal, “nyeleneh”, sesat, bahkan kafir. Ada rasa mulai gelisah. Jika Islam adalah agama akal dan hikmah, mengapa pertanyaan justru ditakuti?
Dari pengalaman saya di Amsterdam, mungkin saja banyak orang tidak benar-benar meninggalkan Tuhan, tetapi menjauh dari agama karena tak diberi ruang untuk berpikir jujur. Keraguan mereka tidak dijawab, hanya dibungkam. Tetapi apa memang demikian alasannya?
Sebagai warga negara Indonesia, saya menyaksikan bagaimana agama sering tampil bukan sebagai suara nurani, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ayat dan hadis dipanggil untuk membela pejabat korup, menekan kelompok lemah, atau membungkam kritik.
Saya bertanya, apakah ini Islam yang saya peluk atau Islam yang telah berubah menjadi institusi politik?
Ketika agama lebih sibuk mengatur panjang celana rakyat kecil, tetapi gagap menghadapi ketimpangan, penggusuran, dan ketidakadilan, sebagian orang boleh jadi kehilangan kepercayaan. Bukan pada Tuhan, tetapi pada mereka yang mengklaim berbicara atas nama Tuhan.
Saya punya beberapa teman atheis, setidak-tidaknya agnostik, dan saya mendengar pengakuan mereka bahwa mereka meninggalkan agama bukan karena membaca buku atheis, tetapi antara lain karena luka hidup; doa yang tak kunjung berjawab, orang saleh yang menderita tanpa penjelasan, keadilan yang dijanjikan, tetapi tak pernah datang. Oalah…
Alih-alih diajak berdialog, mereka justru diminta bersabar tanpa empati, disuruh ikhlas tanpa ditemani. Dalam Islam, kita mengenal kisah Nabi Ayyub yang mengeluh, Nabi Ya’qub yang menangis, bahkan Nabi Muhammad yang pernah bersedih hingga hampir putus asa. Tapi mengapa umatnya sering tak diberi hak untuk rapuh?
Agama yang Diwariskan, Bukan Dipilih
Di Indonesia, hampir tak ada ruang untuk memilih agama secara sadar. Kita lahir, lalu agama melekat seperti nama keluarga. Maka banyak orang “beragama” tanpa pernah benar-benar bertanya apakah mereka memahami dan meyakininya.
Ketika dewasa dan mulai berpikir, sebagian merasa agama itu bukan hasil perjumpaan batin, melainkan warisan sosial. Ada yang kemudian menemukan kembali imannya secara lebih matang. Ada pula yang merasa tak sanggup melanjutkan.
Ironisnya, negara dan masyarakat sering memaksa orang tetap mengaku beragama, meski hatinya telah kosong. Kita lebih takut pada atheisme administratif daripada kemunafikan massal.
Sebagaimana telah saya kemukakan barusan, saya mengenal orang-orang yang tidak lagi percaya pada Tuhan, tetapi sangat manusiawi. Mereka jujur, peduli pada sesama, dan menolak kekerasan.
Ini membuat saya berpikir: mungkin yang mereka tolak bukan nilai Islam, Kristen dan lain-lain, melainkan wajah agama yang mereka temui.
Bukankah dalam Islam, agama yang saya peluk, akhlak lebih utama daripada simbol? Bukankah Nabi lebih sering dikenal karena kejujurannya sebelum kenabiannya?
Jika agama gagal menghadirkan rahmah, jangan heran bila orang mencarinya di luar agama.
Saya tidak menulis ini untuk mengajak orang meninggalkan agama, apalagi meninggalkan Islam yang saya yakini. Tidak. Justru sebaliknya. Saya menulis karena saya percaya bahwa iman yang dewasa lahir dari pertanyaan, bukan dari ketakutan.
Saya membaca banyak buku filsafat yang konon mitosnya sering menjerumuskan orang menjadi atheis. Malah sebaliknya, semakin banyak membaca buku filsafat semakin memantapkan saya beragama dan bertuhan.
Tetapi tidak bisa saya pungkiri, Islam yang saya rindukan adalah Islam yang berani berdialog, yang tidak gemetar menghadapi keraguan, yang tidak buru-buru mengkafirkan. Islam yang percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada tafsir manusia mana pun.
Mungkin, orang-orang yang hari ini menjauh dari agama (Islam, Kristen, Hindu dll.) bukan sedang memusuhi Tuhan. Mereka sedang mencari-Nya dengan cara yang belum kita pahami.
Dan mungkin tugas kita bukan menghakimi mereka, melainkan bertanya pada diri sendiri: apakah agama yang kita tampilkan masih cukup ramah untuk menampung manusia yang berpikir, terluka, dan jujur itu?
***