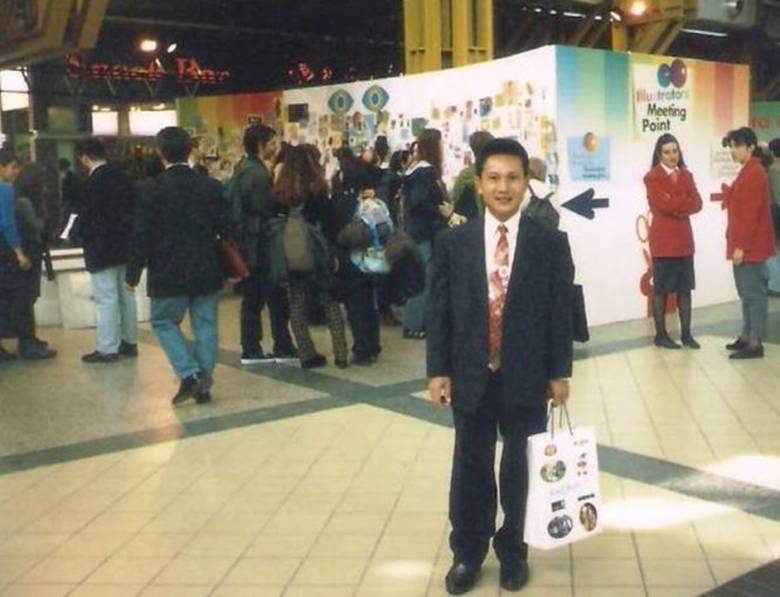Jalan Pulang [2] Bahasa, Kunci Jendela Dunia
![Jalan Pulang [2] Bahasa, Kunci Jendela Dunia](https://assets.ytprayeh.com/img/4r16185e4776261/7a9e4-FC_20210424_0027.JPG)
Waktu sungguh relatif. Durasi penerbangan Jakarta-Yogyakarta yang kurang lebih sekitar 55 menit di udara, akan terasa cepat atau lama bergantung pada situasi kemendesakan kita. Bila dibandingkan dengan perjalanan darat yang menghabiskan waktu tempuh 7-8 jam, tentu durasi penerbangan ini jauh lebih singkat. Namun, bila setiap detik menjadi sangat berharga sebagaimana yang saya rasakan, penerbangan ini terasa lama dan menyiksa.
Saya hanya dapat memejamkan mata, tetapi nyatanya tetap terjaga. Ingatan demi ingatan tentang sosok Ibu dan kesibukannya hilir-mudik di benak saya. Semasa aktifnya, Ibu adalah seorang guru Bahasa Jerman, baik mengajar di SMA maupun di sebuah lembaga kursus. Bahkan, tak jarang di rumah pun Ibu menerima murid les privat, yang rata-rata adalah para siswa SMA yang memang secara serius sedang mempersiapkan diri untuk berkuliah di Jerman, umumnya mereka yang mengincar kuliah di jurusan teknik atau kedokteran. Di masa itu, adalah pemandangan biasa bila sore hingga malam hari Ibu menerima murid les 2-3 orang tiap harinya. Tak heran, banyak teman sekolah saya yang mengira saya pasti juga pintar berbahasa Jerman. Namun, kenyataan berbicara sebaliknya, baik saya maupun adik saya, tak sedikit pun tergerak untuk mendalami bahasa itu, padahal Ibu tak kurang membujuk dan merayu untuk mengajari kami.
Belakangan, setelah saya bekerja, barulah rasa sesal itu mengemuka. Betapa tidak, bila pekerjaan akhirnya melabuhkan saya berkali-kali tugas ke Frankfurt dan beberapa kota lain di Jerman. Malangnya, setiap kali bertugas saya hanya mengandalkan komunikasi dalam bahasa Inggris yang belum tentu semua orang Jerman memahami atau bahkan bersedia menanggapinya. Seandainya, ya seandainya... dulu saya menuruti keinginan Ibu untuk mengajari saya berbahasa Jerman sejak sekolah menengah, tentu situasi dan ceritanya akan lain. Kemampuan berbahasa Jerman saya pasti sudah “tingkat dewa” dan saya akan lebih mudah membaur bergaul dengan masyarakat Jerman dari segala lapisan.
Saya jadi bertanya-tanya, mungkinkah itu bisa dibilang bagian dari naluri seorang ibu? Naluri yang mengatakan bahwa kelak saya pasti memerlukan bahasa Jerman. Hanya, barangkali karena Ibu sangat demokratis maka ia tak sertamerta memaksakan keinginannya itu. Entahlah, penyesalan memang selalu datang terlambat. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali.
Bahasa Jerman bukanlah satu-satunya bahasa asing yang Ibu kuasai. Ia juga fasih berbahasa Inggris dan Belanda, lalu sedikit mengerti bahasa Prancis. Selepas saya pergi merantau, saya dengar Ibu juga sempat mencoba belajar bahasa Latin meski tidak terlalu intens, dan mencicip bahasa Ibrani sekadar untuk keperluan memahami teks-teks gerejawi.
Sungguh, saya sering takjub dan salut pada orang yang memiliki kemampuan berbahasa asing lebih dari dua bahasa.
Tak terbayangkan bagaimana otak mengelola semua bahasa dengan karakteristik tatabahasa yang berlainan. Bila dikaitkan dengan teori 8 kecerdasan manusia yang pada 1983 dikenalkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Ibu tergolong orang yang kuat dalam kecerdasan linguistik dan verbal, yakni kemampuan menggunakan kata-kata dan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, menurut Howard Gardner, biasanya sangat pandai menulis cerita, mengingat informasi, membaca, dan baik saat berbicara atau menjelaskan, dan mereka sangat cocok bila meniti karier sebagai penulis, jurnalis, pengacara, atau guru. Sesuai!
Meski demikian, sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi, memiliki kecerdasan yang sangat kuat di bidang tertentu, bukan lantas menafikan atau meniadakan kecerdasan lainnya. Kedelapan kecerdasan tersebut tetap ada pada tiap manusia, tetapi dengan proporsi yang tidak selalu sama.
Teori ini sangatlah populer dan sering dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kemampuan diri setiap orang, bahkan banyak guru yang menerapkannya untuk mengenal dan memahami kekuatan setiap siswanya. Adapun kecerdasan lainnya, menurut Howard Gardner, adalah kecerdasan logika dan matematis, kecerdasan visual dan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan naturalis.
Mengenal atau setidaknya memahami sedikit teori ini sebenarnya cukup mengasyikkan, paling tidak sekadar memetakan kecerdasan mana yang menonjol pada diri kita. Saya misalnya, mungkin tidak memiliki ketertarikan kuat untuk belajar bahasa asing, tetapi toh pekerjaan yang saya tekuni selama 30 tahun lebih—dan saya senang menjalaninya—erat terkait dengan pergumulan tatakata, kepenulisan, dan kebahasaan. Artinya bahwa, kecerdasan linguistik dan verbal saya cukup berperan, di samping percikan-percikan kecerdasan lain yang juga saya rasakan. Kecerdasan intrapersonal misalnya, mungkin ada pada peringkat kedua.
Kecerdasan linguistik dan verbal Ibu, sepertinya diikuti oleh anak saya. Sejak ia kecil, setiap kali mendapat pelajaran bahasa asing yang baru, ia lahap begitu saja, bahkan tanpa belajar keras sekalipun. Padahal, yang ia terima adalah bahasa-bahasa yang dilengkapi dengan kerumitan huruf-huruf hanzi dan kanji. Nilai rapornya untuk bahasa asing (Inggris, Mandarin, dan Jepang) selalu di atas nilai rata-rata kelas, meski dalam perjalanan studinya ia lebih tertarik memelajari bidang teknologi. Bagi saya ini menjadi contoh kasus menarik, karena kedua kecerdasan ini boleh dibilang mewakili dua kutub yang berbeda, namun toh keduanya akur dan saling melengkapi. Teknologi pesat berkembang di berbagai belahan dunia, dan bahasa akan menjadi kunci untuk membuka jendela dunia.
Lamunan acak saya akhirnya dihentikan oleh suara awak kabin yang mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat, yang artinya akan segera memasuki fase critical eleven. Jujur, meski sudah ratusan kali melakukan perjalanan penerbangan dengan variasi durasi waktu tempuh, saya masih saja selalu waswas setiap kali memasuki fase critical eleven atau waktu-waktu sebelas menit paling kritis di dalam pesawat, yaitu pada tiga menit setelah pesawat take off (lepas landas) dan delapan menit sebelum pesawat landing (mendarat). Konon, data statistik menunjukkan, saat take off dan landing adalah fase paling rawan dalam sebuah penerbangan. Keduanya menjadi waktu yang sangat krusial karena apa saja bisa terjadi di rentang itu. Itulah sebabnya, awak kabin akan memberikan arahan bagi para penumpang seperti mematikan ponsel, menutup meja, menegakkan sandaran kursi, membuka tirai jendela, dan menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Saya sering sangat jengkel setiap kali mendapati perilaku penumpang yang masih saja acuh menghidupkan ponsel di pesawat meski sudah diperingatkan untuk mematikannya. Tidak sadarkah mereka bahwa aturan ini bukan sekadar pelengkap, tetapi dibuat untuk mendukung jalannya evakuasi apabila diperlukan dan demi menunjang keselamatan penerbangan?
Beruntunglah, fase kritis kali ini boleh kembali saya lewati dengan selamat. Pesawat landing sempurna dan tanpa goncangan berarti. Ingin rasanya untuk segera mengaktifkan ponsel dan memeriksa sekiranya ada berita tentang Ibu. Namun, ego itu saya abaikan guna mematuhi peraturan penerbangan.
Pesawat berhenti. Para penumpang tampak bergegas bangkit, tangan mereka meraih-raih tas dan bawaan dari kompartemen kabin, seolah takut barangnya hilang, tertukar, atau tertinggal. Begitu pintu kabin terbuka, penumpang yang sudah berjejal di lorong kabin pun seperti dimuntahkan dari dalam lambung pesawat. Saya aktifkan ponsel yang segera disambut dengan keriuhan suara denting notifikasi pesan masuk. Saya abaikan pesan-pesan yang berasal dari grup-grup WhatsApp, yang kebanyakan hanya berisi kiriman foto, video, atau sekadar stiker yang berulang-ulang. Bukan prioritas. Saya langsung menuju ke nomor anak saya. Ada satu pesan, dan buru-buru saya buka. Lega rasanya, isi pesannya hanya menanyakan jam kedatangan pesawat. Tidak ada berita lain. Terima kasih Tuhan. (bersambung)