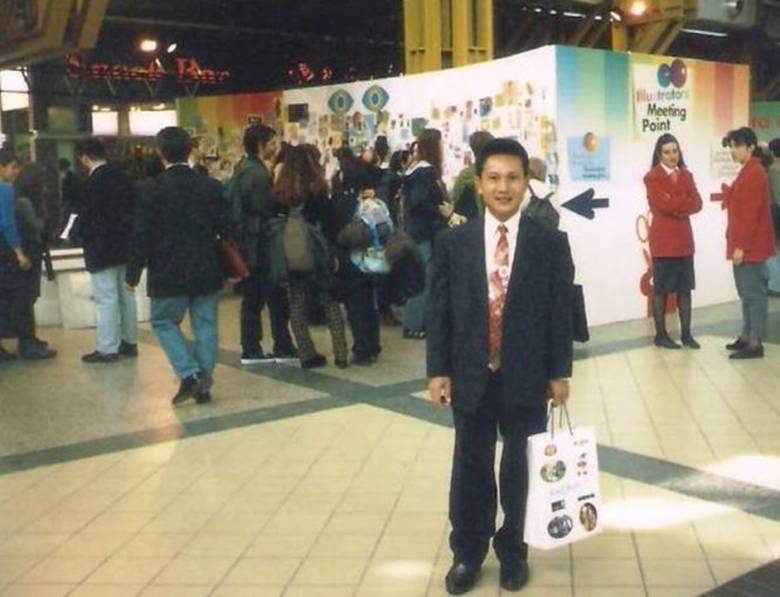Tidak Ada Agama yang Arogan

Ranah media sosial sedang ramai membicarakan berita mengenai dugaan penghinaan terhadap agama (keyakinan) yang dipeluk mayoritas penduduk negeri ini yang dilakukan oleh seorang selebritas medsos ternama, khususnya jagat Twitter.
Dalam cuitan yang kemudian menjadi perkara itu, sang selebritis medsos mengatakan agama Islam sebagai “pendatang dari Arab” yang arogan, sedang agama asli Indonesia itu sunda wiwitan, kaharingan, dan lain-lain. Disebut “arogan” karena mengharamkan tradisi asli, ritual, sampai wayang kulit. Sedang mengenakan busana kebaya disebut murtad.
Saya tidak dalam kapasitas membicarakan sang selebritis medsos, sebab bagaimana pun setiap orang berhak dan boleh bersuara di ranah medsos sebatas tidak melanggar aturan dan ketentuan medsos itu sendiri. Sepanjang kicauan, pikiran dan tayangan tidak melanggar ketentuan tersebut, maka medsos tidak akan memberangusnya, bahkan membiarkannya menjadi polemik, kalau dialektik dianggap terlalu keren. Itu memang yang medsos kehendaki.
Ada pepatah “siapa menabur angin, akan menuai badai”. Tentu sang selebritis medsos sudah paham betul pepatah ini. Maka sepanjang dia punya argumen atas apa yang dikicaukannya di Twitter, ia akan jalan terus kendati harus menghadapi keberatan dari beberapa pihak, yang bisa saja melaporkannya kepada yang berwajib. Berbicara dan berpendapat dilindungi konstitsi, maka ia akan menggunakan undang-undang dasar itu sebagai tameng. Ini sudah benar.
Baca Juga: Agama yang Dibawa-bawa dalam Penunjukan Kapolri
Tetapi persoalannya adalah pada konten kicauannya sendiri. Jika saja yang dimaksud adalah “sebagian kecil pemeluk agama Islam (arogan) karena mengharamkan ini dan itu”, misalnya, mungkin kicauannya akan aman-aman saja. Orang diajak berdialektika tentang kebenaran (atau ketidakbenaran) pernyataan tersebut. Dari sini akan tumbuh diskusi yang sehat, tidak perlu main lapor polisi dan masuk ke ranah hukum.
Ketika kemudian membenturkan “agama pendatang” versus “agama lokal”, cara ini yang kemudian bisa menimbulkan diskusi liar yang mengarah ke caci-maki, argumentum ad hominem, bukan diskusi yang sehat. Sebab, sejatinya masing-masing agama tidak harus diperhadapkan sedemikian frontal.
Percaya saja bahwa setiap agama itu membawa kebaikannya masing-masing. Sejatinya perdebatan “agama pendatang” versus “agama lokal” sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan, sebagaimana kita berbicara dalam konteks ideologi (Pancasila).
Dengan sedikit catatan, ideologi mungkin bisa dinarasikan kembali dan kehendak mengubahnya ada pada Majelis melalui Sidang Istimewa dengan syarat dan ketentuan yang tidak mudah.
Tetapi kalau terkait agama, tidak ada seorang pun yang berhak menggugat keyakinan yang sudah “given” dari “sononya” dan diyakini sebagai kebenaran mutlak oleh para pemeluknya. Agama lebih dari sekadar “selera”, tetapi ia juga menyangkut keimanan seseorang.
Iman itu meyakini kebenaran sebenar-benarnya menurut agama yang dipeluknya. Kalau saja dalam “selera” ada pepatah mengakan De gustibum non est disputandum (selera tidak bisa diperdebatkan), apalagi agama yang menyangkut keimanan.
Baca Juga: Memisahkan Sains dan Agama pada Ruang Berbeda
Orang yang mengimani agama tertentu dan orang lain (liyan) menyebut agama yang dipeluknya itu sebagai “arogan”, tentu ia keberatan menerima pandangan itu, kendati orang itu memeluk keyakinan yang sama. Baginya, ia tetaplah “liyan” apapun dalih yang dikemukakannya, misalnya sekadar “otokritik”.
Tulisan ini sekadar pengingat (reminder), bahwa hati-hatilah bicara tentang agama di ruang publik seperti medsos kalau tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tinggi di bidang agama dan keilmuan agama tersebut. Jangankan bicara agama lain yang bukan keyakinannya, bahkan bicara agama sendiri jika salah narasi, salah-salah menuai persepsi yang keliru.
“Taburlah kesejukan, maka kau akan menuai kedamaian.”
Itu saja.
***