The History of Dayak (3)

Dayak pada sense awal mula adalah askripsi dan labeling, yang mengarah ke makna serba-minor. Seiring waktu, labeling serba-miring itu pun, pupus. Dayak kini puak, satu dari sejuta warna yang menyumbang sebentang pelangi-bangsa bernama: Indonesia.
Orang Dayak sendiri yang menghapus stigma serba-minor yang melekat, sekaligus mencederai tubuhnya. Melalui berbagai upaya, seperti: branding, framing, melalui cara dan gaya hidup, sekolah, dan berliterasi: Dayak menulis dari dalam.
Dayak distigma serba-miring di masa lampau bukan tanpa maksud dan tujuan. Setidaknya, terdapat lima sebab yang menjadi tujuan dari pelabelan tersebut.
1. Komodifikasi budaya. Antropolog dan penulis luar, termasuk orang asing, suka pada apa yang disebut dengan news values. Apa yang bisa “dijual” dari Dayak sebagai penduduk asli Borneo? Mereka coba mengeksplorasinya. Dan menemukan bahwa unsur primitif (meski dalam aslinya, primitif berarti: pertama, awal mula, asli) laku sebagai komoditas, barang jualan.
Salah satu dari ciri primitif suatu suku bangsa adalah: Ciri dari sistem mata pencaharian (modus vivendi) dan cara hidup serta cara beradanya (modus essendi). Cawat, tato, wanita dengan dada terbuka, berburu dengan senantiasa memegang sumpit dan menyandang senapan (lantak) dan meminggang parang adalah salah stau ciri primitif itu.
Objek itu lalu difoto. Ditulislah bahwa mereka suku bangsa pengayau, barbar, kanibal, suka makan orang. Tidak paham bahwa dengan senjata siap di tangan, tidak ubahnya dengan manusia zaman sekarang dengan teknologi komunikasi di tangannya: ke mana pun membawa HP, sehingga sewaktu-waktu diperlukan, siap digunakan. Ketika di hutan, ada hewan buruan lewat, senjata –sebagai teknologi—siap digunakan. Di masa lampau, setidaknya hingga tahun 1990-an, berapa banyak gambar manusia Dayak mengenakan cawat dan menyumpit jadi post-card? Dan itu laris, sebagai komoditas!
Komodifikasi budaya oleh penulis luar ini, kemudian berdampak sangat luar biasa. Konstruksi yang dibangun orang luar, dengan menjual unsur nilai beritanya, terhadap orang Dayak lalu nancap ke otak orang. Padahal, bukan demikian esensi orang Dayak yang sesungguhnya!
2. Vorurteil (miskonsepsi). Orang luar dan penulis asing banyak keliru di dalam memahami orang Dayak. Kebanyakan penulis asing, terutama Barat, keliru dalam hal ini. Sebagai contoh, labeling “wild” yang ditempel oleh Windsor pada etnis Dayak yang berarti: orang Dayak seperti bebek kehidupannya. Apa makna di balik pelabelan itu?
Label wild haruslah ditafsirkan dengan mengacu kepada realitas (sosial) pada waktu itu, tradisi, dan konteks lahirnya. Menurut ensiklopedi Merriam-Webster, terdapat tujuh macam pengertian “wild”. Akan tetapi, yang paling mendekati apa yang dimaksudkan Windsor dua pengertian berikut ini.
Pertama, living in a state of nature and not ordinarily tame or domesticated, misalnya “wild ducks”. Kedua, having no basis in known or surmised fact, misalnya a wild guess.
Dengan demikian, Windsor mencitrakan etnis Dayak sebagai penduduk yang masih perlu untuk dimanusiakan. Dalam kacamatanya, mereka suku bangsa yang jauh dari peradaban. Tinggal di alam bebas, liar, dan tidak mempunyai pemukiman yang tetap. Sebagaimana layaknya bebek liar, begitulah cara hidup orang Dayak, tidak seperti orang Barat yang tinggal di rumah batu. Karena tinggal di betang yang terbuat dari kayu, bambu, dan diikat dengan rotan pada waktu itu sesuai dengan tradisi orang Dayak yang hidup komunal, oleh orang barat bukan dianggap sebagai rumah karena pola permukiman dan bentuknya tidak sama dengan yang ada di negeri mereka.
Rumah yang ditopang tiang tinggi, dari bahan kayu dan bambu, dianggap sebagai "kandang hewan". Windsor dengan vorurteil (alam pikiran dan pengetahuan) barat, tidak tahu bahwa ada maksudnya. Tiang tinggi untuk melindungi dari bahaya binatang buas, seperti: kalajengking, ular, dan macan. Selain untuk menghindari banjir. Di malam hari, tangganya dibalik, atau ditarik ke dalam. Tujuannya untuk menghindari tamu tak diundang masuk yang beritikad tidak baik. Dalam hal ini, Windsor telah gagal paham.
Orang Dayak dianggapnya “manusia liar” karena tinggal di perumahan yang menurut kategori pelancong dan penulis barat tidak layak huni. Tidak ada WC dan kamar mandi di betang. Desain dan bentuk betang berbeda dengan yang ada di barat. Di benak para pelancong dan penuls barat, orang Dayak tidak ubahnya seperti bebek: siang hari keluar rumah mencari makan ke ladang dan berburu. Sore hari pulang masuk betang.
George Windsor memang hebat sebagai pengarung samudera ternama. Namun, bukan seorang penulis yang benar dan jujur. Ia (1837) bahkan secara simbolis menggambarkan orang Dayak pada awal abad 18 sebagai “manusia liar”. Hal ini dengan jelas dapat dilihat bagaimana Windsor ketika mengurutkan prioritas siapa yang harus dikunjunginya setelah berlabuh, dan kemudian mendarat. Setelah mengunjungi residen kompeni Belanda di Sambas dan sekitarnya, ia kemudian sowan ke istana Sultan Sambas, baru “...interview with some wild Dyaks” (Windsor, hlm. 181-199).
Menurut teori simbolik interaksionisme (Blumer, 1969), urutan kunjungan ini menunjukkan bahwa orang Dayak dipandang sebelah mata, bahkan dianggap belum beradab dengan menyebutnya sebagai "manusia liar". Padahal, orang Dayak baik-baik saja, tidak mengancam atau berusaha untuk membunuhnya. Kisah mengenai percobaan pembunuhan dirinya justru dikisahkan Windsor pada bagian sebelumnya, ketika ia menceritakan seorang nelayan di pantai pulau Jawa coba mengakhiri nyawanya di atas kapal.
Meski menyebut penduduk asli Borneo sebagai “wild”, sama sekali tidak ada niat, apalagi upaya, penduduk asli Borneo untuk membunuh Windsor, meski ia dilihat sebagai orang asing yang berani-beraninya masuk tanah Dayak. Padahal, bagi orang Dayak, masuk ke kampung orang tanpa terlebih dahulu mengutarakan maksud atau niatan dapat dianggap sebagai mata-mata, atau bahkan memunyai niat jahat.
Lebih jauh, memasuki kampung orang tanpa jelas tujuan dan maksudnya dianggap sebagai perbuatan menyerang, menantang, dan mengajak berperang. Oleh karena itu, tamu yang tidak diundang tersebut pantas untuk dicurigai, ditanyai maksud kedatangannya, dan jika dirasa perlu patut untuk diadili. Jika terbukti bersalah, tamu yang tidak diundang tersebut dapat dikenai hukum adat, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat bergantung kepada kasusnya.
Baca Juga: Gebrakan Budaya dari Malinau Kaltara
Konsepsi seperti itulah yang ada di kepala pelancong dan penulis barat. Sedemikian rupa, sehingga kendatipun merupakan penduduk asli Borneo, etnis Dayak dianggap bukan sebagai penduduk, bahkan dianggap sebagai orang asing di negerinya sendiri. Pencitraan seperti itu nantinya berimpak pada bagaimana sultan-sultan dan raja lokal yang menguasai Borneo pada waktu itu memperlakukan orang Dayak hingga masa kemerdekaan. Dan setelah merdeka, yang memimpin mereka (gubernur, bupati, camat) adalah orang asing, bukan dari kalangan etnis Dayak sendiri.
Singkat kata, orang luar menulis Dayak dipengaruhi konsep dan pengetahuannya. Miskonsepsi, mispersepsi, selain nantinya banyak salah di dalam akurasi dan terminologi. Contohnya: penjelajah bernama Karl Helbig, peneliti dan etnolog asal Jerman. Ia banyak sekali melakukan kesalahan dalam karyanya.
Pria bernama lengkap Karl Martin Alexander mengisahkan ekspedisinya melintas Borneo dari Songkong (mestinya Sungkung) sebuah tempat tinggal Dayak Sarawak yang letaknya tidak jauh dari Jangkang, kampung halaman saya. Setelah dibaca dengan saksama, banyak kesalahan penulisan dan akurasi di dalam karya tulis itu.
Karya, lebih pada kisah perjalanan dan ekspedisi Helbig diberi judul Eine Durchquerung der Insel Borneo yang dapat diterjemahkan menjadi Perjalanan Melintas Borneo, terbit tahun 1937.
Meski mengadung kekurangan, karya ini "buruk-buruk papan jati". Satu di antara langkanya buku zaman kolonial --selain Mijn Leven met de Daya's 1938-1974 oleh van Hulten yang edisi Indonesianya (PT Grasindo, 1992) saya memberi Kata Pengantarnya --yang secara rinci menjelaskan perjalanan seorang penjelajah barat, melewati dan mengamati kondisi daerah/ wilayah kecamatanku saat ini. Antara lain, disebutkan lokus Padek, Darok, Ginis, Bodok, Balai Sebut (ibukota kecamatan Jangkang).
Dicatat pula oleh Helbig ihwal berladang, padi, dan kegembiraan orang Dayak di masa panen. Hal itu membuktikan bahwa sejak zaman baheula, LADANG merupakan staff of life manusia Dayak. Mereka arif mengelola seluruh rangkaian proses kultivasi padi, tanpa menjadi penyebab gangguan lingkungan. Pada 1982, buku ini diterbitkan ulang oleh Dietrich Reimer Verlang, Berlin.
Pengamatan sekilas dan penilaian atas buku ini:
1) akurasi penulisan nama tempat: kurang (5,6)
2) isi buku secara keseluruhan baik (7,8)
3) kedalaman: cukup (6,5)
Demikianlah penilaian umum atas publikasi buku-buku, hasil survei, riset oleh orang asing atas manusia dan budaya Dayak: kurang akurat dan kurang dalam. Perspektif yang dibawa: Barat dengan akar budayanya. Kacamata ini dipakai untuk memotret orang Dayak dan perikehidupannya.
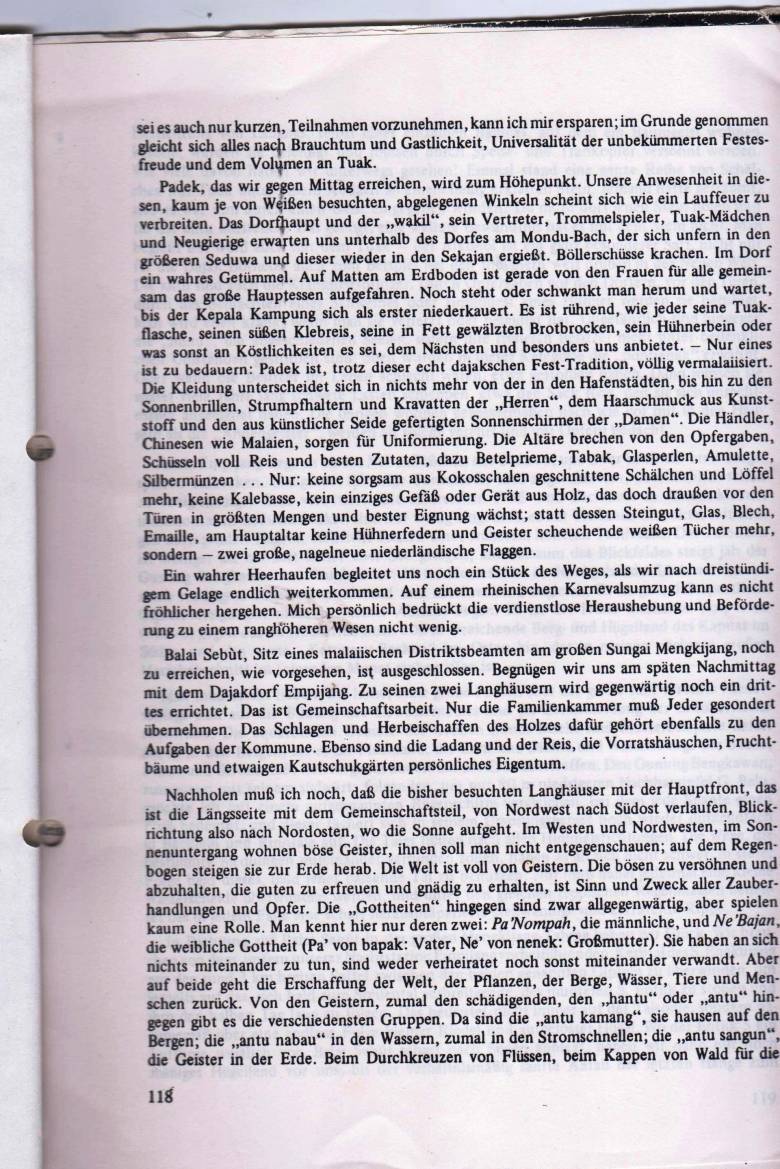
Buruk-buruk papan jati adalah ungkapan yang pas atas publikasi zaman kolonial yang memotret perikehidupan manusia Dayak. Semua wajib "dibaca" dalam konteks 14 bias media (Cirrino, 1971) yang menyatakan bahwa bias suatu teks/ tulisan/ gambar pertama-tama berasal dari penulis dan produsernya.
Toh demikian, yang sangat bernilai, dan tidak tergantikan adalah: buku / karya ini memotret, atau seberkas pantulan cerminan kondisi sosial budaya pada saat itu, di sini, dan di tempat ini. Teori konstruksi realitas sosial dan pendekatan sejarah yang sudah dimulainya, menjadi tonggak bagi penelitian selanjutnya. Namun, serta merta harus diberi catatan: perlu melakukan studi inter-teks agar dapat mengungkap realitas di balik teks-tertulis yang ada. Sayangnya, peneliti dan penulis Dayak --yang memahami akar budayanya sendiri-- masih sangat sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas dan pertanggungjawaban akademik dan metode mendapatkan data/ informasi masih perlu ditingkatkan (lagi).
3. Sensasional. Masih dalam tataran komodifikasi budaya, penulis asing seperti Carl Bock adalah yang pertama membuat label Dayak sukubangsa pengayau (headhunter). Lewat karyanya The Headhunters of Borneo (cetak ulang). Singapore: Oxford University Press (1985), Bock telah menstigma Dayak dengan label tersebut. Dosa asal mispersepsi orang tentang Dayak sebagai suku bangsa pengayau, diawali dari Bock.
Baca Juga: Dayak: Ethnic Identity yang Terbentuk Tidak Sengaja
Bock, meski orang Barat, pandir dan tidak cukup berpengetahuan dalam hal ini. Ia tidak tahu, ngayau tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada tata-laku dan tata caranya. Bock tidak paham, bahwa terdapat 5 alasan ngayau, yakni: 1) melindungi pertanian, 2) mendapatkan tambahan daya (rohaniah), 3 balas dendam, 4) sebagai penambah daya tahan berdirinya bangunan, 5) mempertahankan diri, wilayah/ klan. Jadi, tidak sembarang mengayau –topik ini akan ditulis tersendiri nanti.
4. Dayak dari Yunan. Setelah ditelisik, mazhab atau pihak yang menyatakan asal mula nenek moyang Dayak dari Yunan, sarat dengan muatan politik. Secara epistemologi, asumsi ini musykil dipertanggungjawabkan. Syarat sejarah saja tidak dapat dibuktikan dengan argumen ilmiah (Socratic Inquiry), misalnya jawaban benar dan jujur atas pertanyaan berlapis yang berikut ini: Jika dari Yunan, persisnya Yunan mana? Siapa nama imigran pertama itu? Bagaimana mereka bisa sampai di Borneo? Seperti apa perjalanannya? Mendarat pertama kali di mana? Kampung pecinannya di mana? Tahun berapa? ---Semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara meyakinkan dengan data! Jadi, sangat lemah!
Dengan demikian, mazhab atau pihak yang mengatakan Dayak asalnya dari Yunan bermuatan politis. Muatannya: kalian bukan pewaris sah Borneo. Kalian pendatang, seperti kami! Namun, asumsi ini tidak terbantahkan oleh opini umum: di mana pun, entah di ensiklopedia, entah di penggolongan etnis Dunia oleh Gordon dan The Johua Project oleh –antara lain saya kontribusi proyek itu-- Dayak disebut: indigenous people of Borneo. Saya salah seorang yang membantah mazhab ini. Saya aliran yang menyatakan Dayak tidak dari mana pun asalnya. Mereka dari sini dan tempat ini (Borneo). Ini lebih mudah dipertanggungjawabkan secara akademik!
5. Dayak dinista dan diserang. Mengapa? Saya mengamati hal itu karena ada upaya untuk mengadu domba suku bangsa ini, dan hal itu keliru! Mereka tidak paham bahwa semakin diadu domba, Dayak semakin solid. Kompeni Hindia Belanda yang menginisiasi damai antar-suku Dayak seBorneo Raya pada 1894 di Tumbang Anoi (wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalteng saat ini) tidak menggunakan taktik Divide et Impera –pecah belah dan adu domba pada Dayak, lalu kuasai. Sebab taktik ini hanya berlaku di tanah Jawa, yang sukunya solid. Namun, di kalangan suku bangsa Dayak yang saling kayau dan punya wilayah masing-masing, Hindia Belanda menggunakan taktik lain yang berbeda. Banyak orang, terutama pengamat, keliru dalam hal ini. Nama taktik untuk menguasai Dayak oleh Hindia Belanda: Salt starvation! Suku bangsa yang saling kayau, yang haus darah, dan saling bersaing itu; disatukan, baru dikuasai.
Dayak dinista dan diserang karena jika saling kayau, dikira banyak orang, modus seperti itu agar mereka mudah dikuasai. Namun, sejak Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894, Dayak solid. Mereka sadar. Merekalah pewaris sah bumi Borneo. Kesadaran kolektif itu terus dipertahankan secara gigih, dengan sekuat tenaga, cipta-karsa, dan daya upaya.
Kesadaran kolektif secara naluri, bahwa mereka wajib mempertahankan wilayah dan klan, juga harga diri; mencuat kembali. Itulah spirit, makna terdalam ngayau di masa silam. Jadi, bukan pertama-tama memenggal kepala tanpa-sebab, seperti digambarkan Bock.
Kesadaran akan hal itu --soliditas dan bersatu padu-- kemudian terbukti dari adanya perhimpunan Pakat Dayak di Kalimantan Tengah (1929) dan kemudian Partai Persatuan Daya (PPD) di Kalimantan Barat (1945). Hingga nanti berdiri Dewan Adat Dayak (DAD), yang mencapai puncaknya pada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).
Topik yang akan ditulis kemudian, pada bagian tersendiri.
***
Tulisan sebelumnya: The History of Dayak (2)


.png)
