Pengakuan di Ruang Sidang | My Cerpen (4)
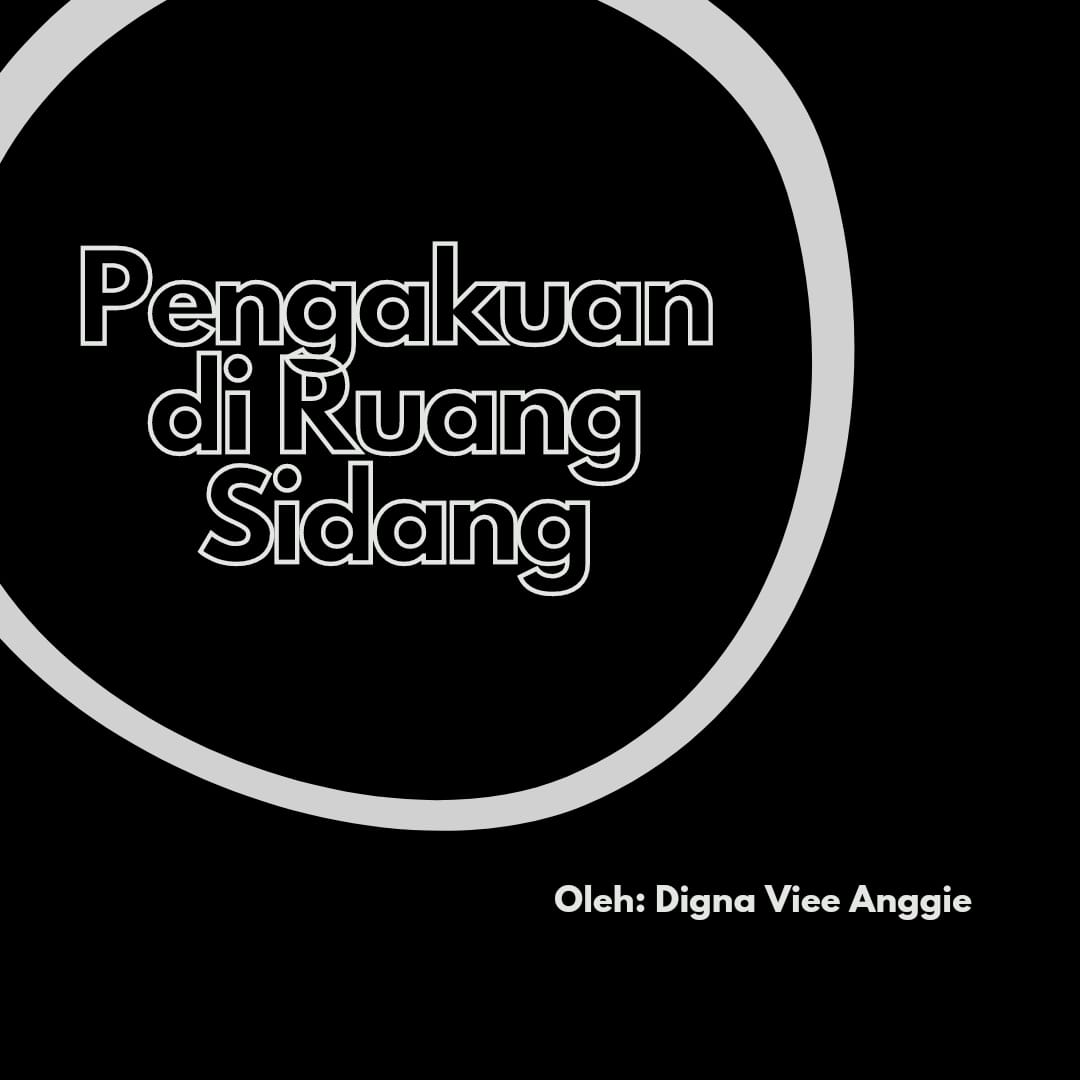
Bertahanlah demi Elora. Berulang kali kukatakan padamu, bertahanlah demi Elora. Gadis lucu yang menggemaskan. Melihat bibir mungilnya, dengan cuap-cuap kecil menanti ASI, aku seperti melihat seorang malaikat mungil yang mengintari hidupmu dengan doa. Jangan kau patah semangat hanya karena suami yang tidak bertanggung jawab.
Terngiang dalam benakku. Nasehat ibu mertua yang amat sangat menyayangiku sebagai menantu. Ia tahu, betapa pilunya aku menanggung kecewa. Setelah berulang kali, Sam mengkhianatiku. Ibu selalu memelukku dengan hangat, ketika Sam memukul wajahku hanya karena selera makannya terganggu oleh tangisan bayi mungil kami, Elora.
Belakangan, Sam berubah bringas. Sejak Elora hadir dalam kehidupan kami. Semuanya berubah. Sam tak betah lagi diam di rumah. Ia beralasan kerja, kerja dan kerja. Ketika tengah malam tiba, ia pulang sempoyongan. Mengibas dengan brutal semua tanaman Ibu di pekarangan. Bahkan, tiang parabola pun hampir dibabat. Ibu tak punya pilihan, selain menyembunyikan aku dan Elora di kamarnya. Sam mabuk lagi.
“Aku tak punya pilihan, Bu. Semua harus berakhir.”
“Kalau kau pergi. Jangan pernah membawa Elora. Biarkan Elora tinggal bersamaku.”
Ibu selalu berupaya mencegah kepergianku. Memang perlu diakui, hanya ibu mertua sebagai alasanku untuk bertahan. Ibu selalu memberi kehangatan ketika hatiku membeku karena ulah Sam. Entah, sudah berapa kali tangan Sam melayang di wajahku. Begitu hebat juga aku bertahan dalam diam.
Seringkali aku menahan diri untuk belanja menggunakan uang Sam. Padahal, ketika tengah hari tiba, aku sangat ingin mengikuti saudari iparku jajan di kantin yang letaknya ada di kaki bukit. Aku sangat ingin makan semangkuk sup segar di sana. Lagi pula, siapa sih yang tidak tahu, jika seorang ibu dengan masa nifas sangat kuat mengisi perut.
Hatiku kerap meringis, mana kala menilik isi dompet hanya terisi dengan beberapa uang goceng. Jika hati Sam baik, ia menitipkan sedikit uang. Itu pun harus cukup untuk membeli susu untuk Elora.
Kuusap jemari tangan. Tampak mengering. Aku seperti kurang gizi. Belum lagi harus berbagi ASI dengan Elora. Kepalaku terasa mau pecah. Ketika mendengar Sam berulang kali mengucapkan kata tak sedap.
Aku seperti menemukan jalan buntu. Ketika tak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Sam. Laki-laki itu berubah sejak kutemukan nama Amanda di layar handphone-nya. Sam pernah cerita padaku, bahwa Amanda adalah mantan kekasihnya. Berulang kali juga kutanya pada Sam. Jika ia masih memilih untuk berkomunikasi dengan Amanda, lebih baik ia tak menikahiku dulu.
“Amanda itu perempuan baik, bersahaja dan tidak egois seperti kamu!”
“Kamu kenapa membanding-bandingkan aku dengan Amanda sih, Mas? Kalau Amanda perempuan baik, kenapa Mas tidak me…”
Prak!
Kulit pipiku terasa perih. Untuk kesekian kalinya KDRT kuterima dari Sam. Kalau tidak karena tangisan kecil Elora, pertengkaran kami pasti berlanjut. Kasar. Sikap Sam semakin membuat ibu mertuaku naik pitam.
“Kalau kau sudah tak mau lagi mengurus anak istrimu, kembalikan saja pada orangtuanya!”
Sam tak bergeming. Mengepul asap rokok yang tampak menebal di udara. Aku menelan saliva. Menahan segukan yang hampir tumpah ruah. Ibu selalu membelaku, meski Sam adalah anak kandungnya.
“Kalau kau pergi…. jangan pernah membawa Elora.”
Aku duduk membisu, setelah mendengar ucapan Sam. Di atas meja makan, saat kami dalam keadaan baik-baik saja. Bicara dari hati ke hati setelah mengisi perut. Elora masih bayi. Sangat membutuhkan ASI. Itu juga alasan untukku tetap bertahan.
“Mas, jika saja kau bisa melupakan Amanda. Aku akan memaafkanmu.”
“Apa-apaan kamu? Kamu kira Amanda itu sama sepertimu? Tidak! Aku tidak akan pernah melupakan Amanda.”
“Terserah kamu, Mas. Jika nanti aku terpaksa pergi dari rumah ini jangan pernah mencariku lagi.”
Aku bergegas mendapati Elora yang menggeliat dalam ayunan. Bayi mungil itu tak pernah mengetahui perkara kedua orang tuanya. Kala menantap wajah Elora, aku rasa menjadi ibu yang paling berdosa. Tuhan menitipkan Elora padaku dengan kondisi rumah tangga yang berantakan.
Perjuanganku mendapatkan Elora tidak mudah. Setelah empat tahun menikah dengan Sam, aku baru hamil. Meski kehadiran Elora sudah melengkapi hidupku, rasa cintaku pada Sam tidak memudar. Sangat jauh berbeda dari perlakuan Sam padaku. Bahkan jauh sebelum Elora lahir, Sam telah berubah. Kudengar, besok Amanda akan ke rumah untuk menyambangi bayi kami, Elora.
“Untuk apa kau membawa wanita itu ke sini, Mas?”
“Amanda hanya ingin melihat Elora.”
“Menurutku sama sekali tidak penting!”
Darahku berdesir sampai ke ubun-ubun. Entah terbuat dari apa hati Sam. Beraninya dia membawa Amanda ke rumah. Aku berpikir bahwa Sam sama sekali tidak menghargai perasaanku sebagai seorang istri.
“Hana! Aku ingatkan sama kamu, ya. Jika besok Amanda datang, jangan pernah menunjukkan rasa tidak sukamu pada dia!”
“Apa, Mas?! Jadi, aku yang harus mengalah? Begitu?!”
Gila. Sedalam itu kah Sam menghargai wanita bernama Amanda. Sementara aku? Aku sebagai seorang istri diminta untuk mengalah. Aku sengaja tak memberitahu Ibu, soal kunjungan Amanda. Pun, aku sudah mengatur strategi, jika Amanda benar datang, lebih baik aku ngumpat di rumah Theresa, saudari iparku.
Elora tak bisa tidur malam itu. Aku meraba kedua kupingnya. Terasa dingin. Dengan ujung jari, aku mengetuk perut Elora. Terdengar kembung. Waktu sudah menunjukkan pukul dua dini hari. Sam belum pulang ke rumah. Aku memberanikan diri untuk meneleponnya. Meminta ia segera pulang. Ibu mertuaku sudah panik ketika menggendong Elora yang tak berhenti menangis.
“Kamu sudah menelepon Sam?”
“Tak diangkat.”
Aku bergegas ke dapur, memilah bawang merah tunggal. Menggeprek bawang itu lalu mengolesnya di pusat Elora. Elora menolak ASI. Aku hanya bisa mendekapnya dengan erat. Ibu mengambil minyak kayu putih, lalu membubuhkan minyak itu di sekujur tubuh Elora. Perlahan, tangis Elora mereda.
Menjelang pagi, Sam pulang ke rumah. Ibu menyemprotnya dengan omelan. Aku sama sekali tak ingin bicara. Batinku terlalu lelah untuk menumpahkan isi jiwa. Bagiku, omelan Ibu cukup mewakili perasanku.
“Elora sudah bangun, Han?”
“Belum.”
“Maaf, tadi malam aku tidak pulang dan tidak mengangkat teleponmu.”
“Tidak apa, sudah biasa,” aku berlagak cuek.
“Kita perlu ke dokter?”
“Nggak perlu. Elora pasti sembuh.”
Sam mengecup lembut kening Elora. Yang kulihat Sam begitu sayang dengan putrinya. Tidak berselang lama, kulihat Sam tertidur nyenyak di samping Elora. Wajahnya terlihat capai. Mungkin karena lelah bergadang semalaman.
“Hana…. Ibu mau bicara sama kamu.”
Aku terdiam. Ibu pasti ingin menasehatiku lagi. seharusnya Ibu tidak hanya melakukan hal itu padaku. Sam juga layak mendapatkannya. Ibu hanya menasehati Sam saat emosi. Itu akan mental di pikiran Sam. Sementara aku? Ibu selalu menasehatiku dengan santai.
“Ibu ingin mengikuti keyakinanmu.”
Aku terhenyak. Ini tidak mungkin. Yang kutahu, Ibu sangat religius dalam imannya.
“Ibu...?!”
Ibu dengan lugas menjelaskan kepadaku alasan ia berpindah keyakinan. Aku tak ingin memberitahunya pada Sam. Lagi pula, Sam bukan seorang kepala keluarga yang baik. Sam berpindah keyakinan saat akan menikah denganku. Tapi, itu hanya demi menikah denganku. Tak ada paksaan, semua itu atas keinginannya sendiri.
Menjelang malam, sepulangnya aku dari rumah Theresa, aku melihat seorang wanita muda. Ia, tengah duduk manis di sofa. Segelas teh hangat dengan ubi rebus buatan Ibu tadi sore tersaji di hadapannya. Aku tak mengenalnya. Rona merah lipstik dibibirnya turut menghiasi senyumnya padaku. Siapakah gerangan? Setumpuk tanya terbesit dalam hatiku.
“Hana!” suara Sam memanggilku dari bilik kamar. Aku bergegas menjumpainya tanpa membalas senyum wanita itu.
“Dimana kau simpan celana jeans yang biasa aku pakai?”
Aku tak menjawab. Setelah Sam meraih Elora dari gendonganku, aku langsung mengobrak abrik lemari pakaian, mencari celana jeans yang Sam maksud. Dasar laki-laki, ya begitu. Padahal celana jeans favoritnya itu terselip diantara beberapa pakaian yang lain.
“Mas…. Ini celananya udah ketemu!” aku sedikit mengencangkan suara. Agar terdengar oleh Sam dari luar.
“Mas….” aku menyusul ke luar, karena tidak ada jawaban.
Ketika muncul di muka pintu, tiba-tiba saja, darahku mendesir. Manakala kulihat wanita muda tadi asyik bercengkrama dengan Elora. Yang membuat kedongkolanku tumbuh, Sam duduk tepat di samping wanita itu. Ia tampak sibuk mengusap layar handphone-nya.
Aku segera meraih Elora dari pelukan wanita itu. Tak sudi jika ia mendekap erat anakku. Karena sikapku, Sam jadi marah. Ia menudingku tidak tahu bersikap sopan terhadap tamu. Aku tak peduli. Wanita itu hanya tersenyum kecil. Barangkali ia juga tersinggung karena ulahku.
“Hana!”
“Kenapa lagi sih, Mas?”
Aku berjalan lurus ke dapur. Melihat Ibu yang tengah asyik menyiapkan makan malam untuk kami. Aku mendekat pada Ibu. Di atas meja, masih tergeletak sisa ubi rebus tadi sore. Aku mengambil sejumput lalu menyuapnya ke dalam mulut.
“Bu, siapa wanita di depan sana?” aku sedikit berbisik di samping Ibu.
“Itu, Amanda.”
Aku terdiam. Tepat dugaanku. Jadi, seperti itu sosok Amanda yang selalu dipuja-puja oleh suamiku. Aku masih tak bergeming. Hanya satu jawaban dari Ibu, cukup. Aku tak memerlukannya lagi.
“Kamu mau makan, Han?” Ibu meletakkan piring di hadapanku.
“Nggak, Bu. Nanti aja.”
“Amanda sudah pulang?”
“Belum,” aku menjawab singkat.
Sengaja kutinggalkan keduanya di ruang tamu. Entah apa yang mereka lakukan di sana, aku tak peduli. Bagiku, yang penting Elora tidak bersama mereka. Aku tak akan membiarkan bayi mungil ini menyaksikan perselingkuhan ayahnya.
Atas perintah Ibu, aku terpaksa makan sambil menggendong Elora. Bayi itu sudah terbiasa melekat ditubuhku. Sulit untuk menelan sesuap makanan di kerongkongan. Aku hampir saja menumpahkan air mata. Jika tak mengingat pesan Bapak, tangis ini akan tercurah di meja makan. Aku berusaha menahannya. Bapak selalu bilang, separah apa pun kamu berduka, jangan pernah menumpahkan tangis di meja makan.
“Hana, aku mau ngantar Amanda pulang.” Sam meminta izin juga denganku.
Aku hanya mengangguk. Memberikan kesempatan kepada laki-laki itu untuk melakukan apa pun yang dia mau. Sam berjalan mendekati kami. Mencium kening Elora tanpa memandangku. Ibu mertuaku dengan santai melahap sisa makanan di piringnya. Ia tak bicara apa pun.
Satu bulan kemudian, aku terpaksa mengakhiri pergulatan batin. Memutuskan untuk melangkahkan kaki dari rumah besar Nyonya Hensi, ibu mertuaku. Aku tak kuat lagi menahan beban yang selama ini terkurung dalam jiwa dan ragaku.
Sepanjang malam aku tak bisa tidur nyenyak. Memikirkan cara termudah untuk kabur dari rumah ini. Aku bimbang untuk menentukan tujuan. Sangat tidak mungkin jika aku pulang ke rumah Bapak. Meski pun Bapak pernah bilang, apa pun yang terjadi, pulanglah ke rumah Bapak.
Elora tidur dengan nyenyak. Aku memandang wajah gadis kecil itu dengan seksama. Merasakan kehangatan napas yang terhembus dari kerongkongannya. Elora bayi pintar. Ia tidak rewel, kecuali jika sedang tidak sehat. Ia sama sekali tidak pernah merepotkan aku sebagai ibu yang mengasuhnya seorang diri.
Pukul 04.30 pagi,
Kulihat keadaan rumah sepi. Ibu sudah tiga hari ke luar kota. Katanya mau pulang ke rumah keluarga. Aku mengambil kesempatan itu untuk pergi. Sam juga sudah lima hari tidak di rumah. Katanya ada kegiatan di perusahaan tempatnya bekerja.
Berat, ketika seorang wanita memutuskan angkat kaki dari rumah. Aku pun demikian. Beberapa tahun menjadi istri Sam, aku seperti sebuah bola yang tersudut ke berbagai arah. Bukan karena mengingkari janji suci di hadapan Tuhan dan sesama, tapi lebih kepada kekuatan hati yang semakin menipis.
Dalam bus yang sedang kami berdua Elora tumpangi, aku menatap setiap sudut kota yang kini kami tinggalkan. Aku menetapkan hati untuk menjauh. Sesekali, aku menatap wajah Elora yang tertidur pulas dalam pangkuanku. Entah dengan cara apa aku membesarkan bayi perempuan ini nanti. Sam, maaf. Semua ini harus berakhir.
Aku menunggu ketukan palu di ruang sidang. Hari ini, aku datang bersama pengacara yang dibayar oleh Bapak. Ia bersedia menolongku untuk melepas ikatan pernikahan dengan Sam. Aku, tampil dengan mengenakan baju putih dipadu rok span yang menggantung selutut. Didampingi oleh Harun, pengacara muda yang siap membelaku dalam persidangan nanti.
Aku tak melihat sosok Sam berada di sana. Padahal, hari ini adalah persidangan terakhir. seharusnya Sam datang untuk mendengarkan keputusan sidang perceraian kami. Harun menatap lekat padaku, untuk kesekian kalinya ia bertanya apakah yang kulakukan sudah tepat. Aku mengangguk. Percuma untuk memberi penjelasan. Aku hanya ingin perceraian ini resmi.
Menjalani proses sidang perceraian bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Ada banyak tahapan yang harus dilalui. Meski pada akhirnya, akta cerai yang menjadi saksi berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Cerai. Bukanlah satu hal yang disukai. Namun, suatu perceraian bisa saja terjadi jika kedua belah pihak sudah merasa tidak lagi ada kecocokan dan kesepakatan untuk hidup bersama.
Aku menatap langit-langit di ruang sidang. Seakan memberiku harapan bahwa dunia ini luas. Perceraianku dengan Sam, bukanlah perkara mudah. Kasihan, Elora harus menjadi korban dari keegoisan kami. Ketukan palu menggema di gendang telingaku. Menandakan bahwa aku dan Sam, resmi bercerai hari ini. Dengan langkah gontai, aku keluar ruang persidangan. Menghirup napas bebas, sebebas-bebasnya.
“Hana….”
Aku menoleh ke belakang. Menatap wajah seseorang yang setia mendampingiku di ruang sidang. Hampir saja aku melupakan laki-laki itu. Harun. Ya, pengacara muda yang mendampingi sidang perceraianku. Ia menyungging senyum, manis sekali. Aku berterima kasih padanya. Tanpa bantuan Harun, aku tidak akan cepat merasakan sebuah kebebasan seperti ini.
Harun membawaku kembali ke ruang sidang. Kami membereskan berkas yang masih tergeletak di atas meja. Ia ingin bicara padaku, sebentar. Hanya sebentar. Karena ruang sidang akan ditutup. Kami tak punya banyak waktu. Ketika semuanya sudah selesai, ia langsung bicara padaku.
“Hana, aku menyukaimu.”
Duaaarrrr….!!!
Aku seperti tertembak oleh sebuah peluru nyasar. Bukankah tadi bunyi ketukan palu sebagai tanda kebebasan? Lantas, mengapa setelahnya ada sebuah pengakuan yang harus kudengar? Aku tak bergeming. Demikian pula Harun. Kami pun berlalu, menyimpan sebuah pengakuan yang masih menumpuk tanya dalam hati. Kami berjanji untuk tidak akan pernah datang lagi ke sini.
*dari ruang persidangan, Maret 2012.



