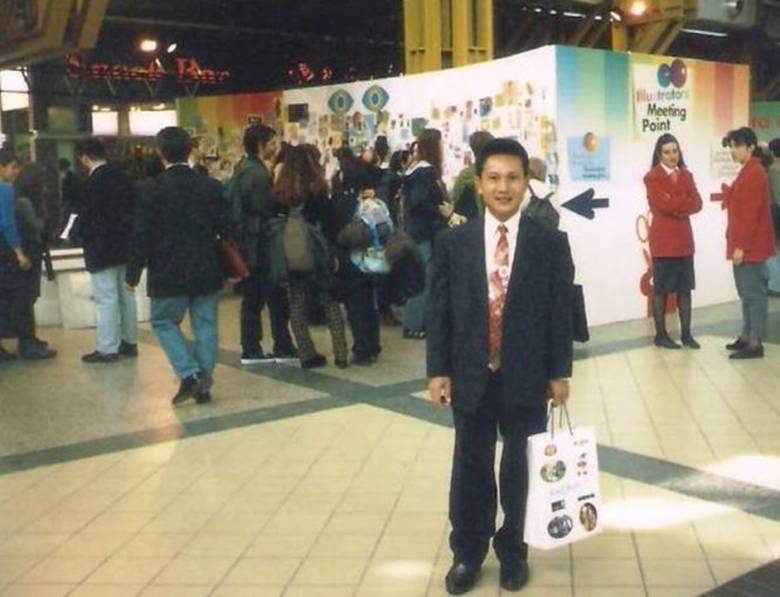Mulailah dengan Bertanya kepada Diri Sendiri

Tak usahlah terlalu menyalahkan kegagalan sitem pengajaran kebangsaan seperti Kewiraan, Wawasan Nusantara, Pendidikan Moral Pancasila atau apapun istilahnya sekarang, hanya untuk sekadar mengukur kualitas kebangsaan. Banggakah kita sebagai bangsa? Apa yang sudah kita perbuat sebagai elemen bangsa untuk negara?
Ini pertanyaan terlalu bombastis, tetapi juga pertanyaan lumrah yang seharusnya kita jawab sendiri, tanpa perlu minta dukungan orang lain.
Konon cara paling mudah mengukur dan menakar rasa bangga kita sebagai bangsa: bertanya kepada para atlet yang menyabet medali emas dalam even-even internasional seperti olimpiade atau kejuaraan dunia suatu cabang olahraga. Masih ingat bagaimana pebulutangkis putri Susi Susanti menjadi sorotan dunia saat mengusap airmatanya di kala Merah Putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya di arena Olimpiade?
Sedikitnya bulu kuduk merinding, jantung berdegup kencang, tubuh bergetar dengan perasaan haru dan bangga bercampur jadi satu.
Pada saat itulah boleh jadi kita merasa, “Yesss... aku 100 persen orang Indonesia! Aku cinta mati Indonesia! Aku bangga menjadi warga Negara Indonesia! Aku bangga menjadi bagian dari Ibu Pertiwi!”
Anda juga bisa merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia dengan cara berempati: katakanlah kalian, para siswa-siswi, yang berhasil meraih medali olimpiade matematika atau fisika, pastilah bangga sebagai bangsa Indonesia, bukan?
Berpikir dan merasa diri sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara yang cinta dan bangga tanah airnya, sudah lebih dari cukup di tengah erosi rasa berkebangsaan yang rendah di antara kita. Tidak perlu saling tuding, cukup bertanya pada diri sendiri saja!
Sekali lagi, jangan terlalu menyalahkan pola pengajaran kebangsaan yang seperti tanpa arah dan tujuan. Suatu pelajaran yang bukan menanamkan rasa cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia, tetapi hanya sekadar membenamkan hapalan demi hapalan di kepala, yang sangat sulit untuk mencapai hati sanubari sendiri.
Tanyakan kepada pakar cinta semacam Erich Fromm; mencintai itu dengan hati, bukan dengan pikiran, termasuk juga mencintai Tanah Air, Ibu Pertiwi ini.
Rasa kebanggaan anak-anak muda sekarang --maafkan jika saya keliru-- hanya sebatas menghapal butir-butir Pancasila yang tanpa peduli bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, juga mukadimah UUD 1945 yang terpaksa “harus” dihapalkan untuk memperoleh nilai baik, atau sekedar untuk mendapat pujian pacar. Bahwa untuk apa saya berada, untuk apa saya ada di Tanah Air ini dan menjadi warga negaranya, rupanya kurang disadari betul.
Masih untung menghapal butir-butir Pancasila, sekarang yang lebih parah malah ada upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi impor. Khilafah , misalnya. Ini ideologi yang diusung organisasi tertentu (alhamdulillah organisasi ini sudah menjadi organisasi terlarang), yang digadang-gadang sebagai solusi cespleng.
Para pengasong ideologi khilafah tidak henti-hentinya menjajakan dagangannya kepada warga negara Indonesia yang labil, yang ketahanan ideologi berbangsa dan bernegaranya rapuh.
Kembali ke soal rasa bangga sebagai bangsa, tentu tidak harus naïf dengan mendorong semua warga negara menjadi atlet peraih medali dan mendengar lagu “Indonesia Raya” berkumandang sambil menghormat Merah Putih untuk sekadar menakar rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Cukup bertindak kebangsaan dalam skala kecil dalam kehidupan sehari-hari , itu saja sudah lebih dari cukup.
Apa dan bagaimana bertindak kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu?
Saya ambil contoh yang umum terjadi saja, yang mungkin juga bisa kita rasakan dan alami. Untuk mempertebal rasa kebangsaan saya sendiri yang barangkali sudah nyaris terkikis, saya akan mengurai satu demi satu seperti ekses otonomi daerah yang merugikan dalam konteks kebangsaan, membanggakan ego sektoral dan ego profesional yang berlebih-lebihan, hasrat berkuasa yang hanya sekadar menggapai kursi kekuasaan.
Juga sikap mendahulukan materi dan pengaruh dan bukan menjalankan amanah, pejabat yang tidak amanah yang hanya mementingkan diri dan golongannya, politisi dan pejabat negara korup jika ada kesempatan, sikap tak acuh dengan keadaan sekeliling, terkikisnya sikap toleran, nilai dan budaya gotong royong yang disepelekan dan hanya dijadikan ejekan “prilaku masa silam”, sampai diambilalihnya pelajaran budi pekerti dari orangtua dan lingkungan oleh media elektronik.
Masih banyak hal lainnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Anggap saja tulisan bagian pertama ini sebagai mukadimah, preambule, repertoire, atau apalah namanya. Semua bahasan semata-mata berdasar apa yang saya rasakan, saya alami dan hasil interaksi saya dengan berbagai kalangan, khususnya yang menyerempet-nyerempet sikap berbangsa dan bernegara.
Tulisan juga menyasar tatanan moral yang mulai goyah akibat penetrasi budaya lewat media baru. Bahkan permenungan ringan mengenai peristiwa sosial-politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, setidak-tidaknya yang pernah saya rasakan dan alami dari hasil bertanya pada diri sendiri, tidak luput dari pengamatan dan menjadi amunisi tersendiri untuk hadirnya sebuah tulisan.
Sama sekali tidak bermaksud menggurui siapapun.
***
Catatan: Artikel merupakan pengembangan lebih lanjut buku "Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang", Bentang Pustaka.