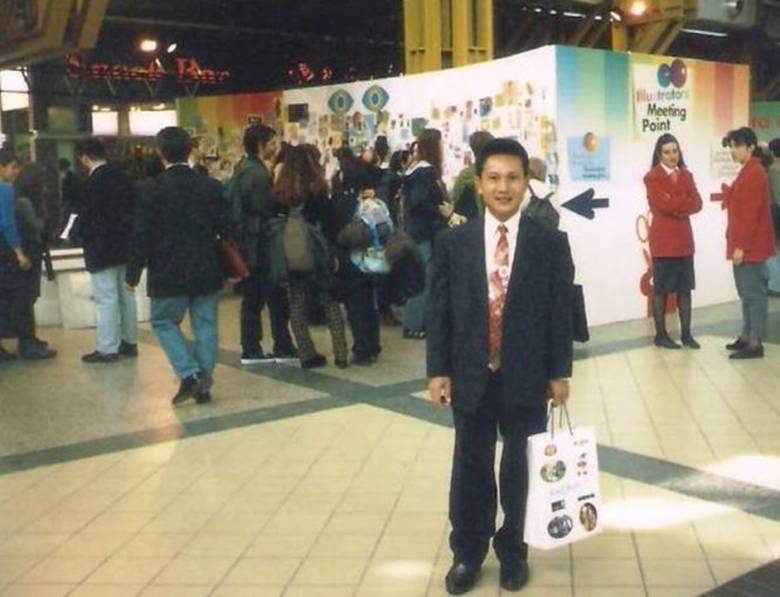MENCURI TUHAN

Entah berapa banyak cerita yang pernah saya baca, dari kecil sudah. Sebab di rumah, ibu kami melanggan majalah, koran, dan membelikan saya buku-buku cerita. Saya melahap dan meneguk semua itu karena saat kecil-remaja-dewasa awal khususnya, saya lapar dan haus sekali apa saja. Lebih tepatnya: lapar-haus kehidupan, penasaran, dan ingin tahu dunia.
Ada karya-karya fiksi itu yang membuat saya mencandu, pingin baca lagi, dan selalu berharap bisa temukan karya pengarang yang sama lagi. Ada juga yang saya suka tapi tidak terlalu mengharapkan bisa membaca lagi yang seperti itu karena sudah banyak dibuat pengarang lainnya.
Saya tidak tahu sejak kapan persisnya saya mahir membaca dan bahkan tidak ingat di umur berapa ibu saya mengajarkan saya huruf-huruf. Sepertinya saya langsung bisa saja. Tapi kalau dikenang ke bacaan-bacaan awal, pertama kali saya mencandu sebuah rubrik di bagian belakang majalah Sunda Manglé. Itu rubrik yang memuat anekdot dan beberapa kartun lucu. Dan karena menunggu terbitan baru lebih dari satu minggu, saya suka membaca bundelan-bundelan Manglé tua di sebuah perpustakaan kecil punya seseorang yang entah siapa. Entah orang itu sudah meninggal pada saat itu, atau masih ada dan terkurung di rumahnya karena sakit parah sejenis lumpuh.
Perpustakaan ini dibuat segi enam, dengan lantai plesteran semen yang licin dan selalu bersih, dan kaca-kacanya menciptakan ruangan ini stabil terangnya sepanjang siang. Di malam hari, lampunya sangat muram kalau saya kebetulan melihatnya dari jalan utama desa. Saya tidak pernah datang sendirian ke perpustakaan ini, tetapi menemani kakak saya yang paling besar, seorang perempuan, ke temannya, seorang laki-laki, anak pemilik rumah dan perpustakaan ini. Mereka bisa mengobrol berjam-jam di teras rumah mereka yang amat besar dan saya kira mereka tidak berpacaran, tapi ada kecocokkan dunia saja.
Antara perpustakaan dan teras itu masih ada jarak jalan setapak di tengah taman, dan tamannya sendiri agak bercampur kebun. Maksudnya, ada pohon-pohon bebungaan, tapi juga ada beberapa pohon buah: mangga beberapa jenis, petai tua dan muda, alpukat, nangka, belimbing, pisang, dan ada juga pohon dengan buah yang asam sekali. Saya lupa nama pohon yang satu itu. Saya suka membayangkan di surga nanti ada taman, kebun, perpustakaan, dan buah-buahan yang saya tidak tahu namanya kecuali buah khuldi yang masih terlarang untuk dimakan.
Teman kakak saya itu selalu bercelana setinggi lutut yang sejak dibelinya memang sudah setinggi lutut, berbeda dari para pemuda kampung lainnya yang celana-celana pendeknya memang hasil modifikasi dari celana panjang tua. Dan dalam keadaan diam wajahnya itu selalu tampak tersenyum seakan-akan saya ada di depannya dan dia sedang mendengarkan saya dan menghargai seorang anak kecil berbicara. Baik kakak saya maupun temannya itu tidak pernah masuk ke perpustakaan, tapi biasanya menyempatkan duduk di teras luar sebentar saja untuk memastikan saya sudah masuk dan mengambil buku tanpa meminta bantuan mereka.
Kini saya sering berpikir bersih dan rapinya perpustakaan itu mungkin memang selalu disapu dan dilap teman kakak saya itu karena saya sangat sering melihatnya merawat tanaman dan menjaga kebersihan taman-kebun itu.
Mereka berdua tidak terlalu nyaman mengobrol di teras perpustakaan karena mungkin malas menyapa atau disapa orang lewat. Kira-kira lima meter jarak dari teras perpustakaan ke jalan. Jadi, kalau saya sudah mereka pastikan duduk tenang di perpustakaan, mereka akan pindah ke teras rumah.
Kembali ke majalah Manglé, di perpustakaan tersebut begitu banyak bundelannya. Ada yang berderet di bawah, di tengah, ada juga di deretan rak paling atas. Saya biasa mengambil yang di atas terlebih dahulu. Meski dengan susah payah, saya tahu bahwa saya senang memanjat raknya yang tebal dan kuat itu, dan seakan sengaja dibuat untuk dinaiki. Bundelan-bundelan itu lebih tebal dari Al-Quran yang ada di rumah kami. Dan saya akan menurunkan beberapa karena saya hanya membaca bagian belakangnya saja. Saya akan tertawa-tawa sendirian di dalam perpustakaan itu seperti iblis bersuka-ria melihat manusia berdosa.
Tidak dapat saya pastikan apakah saya juga membaca rubrik-rubrik lainnya di saat masih bocah itu, tapi sepertinya pernah juga saya mengintip rubrik lainnya termasuk carpon (cerpen). Waktu itu saya baru kelas tiga SD dan melakukan hal serupa sampai kelas enam. Empat tahunan di perpustakaan itu tidak jarang saya membaca anekdot yang sama lagi tanpa sengaja dan menatap kartun yang sama lagi karena semua bundelannya tidak berjilid khusus, hanya bersampul-sampul karton keras dengan pelapis akhir kertas kopi. Beberapa buku lain saya baca-baca juga, tapi kini tidak dapat mengingat satu pun bacaan-bacaan lain itu. Hanya terbayang beberapa secara samar. Beberapa malah saya penasarani terus bukan karena menarik dan menghibur, tetapi karena justru tidak mengerti. Ada sebuah buku berbahasa Sunda karya Haji Hasan Mustapa yang saya suka saja bahasanya tapi saya tidak mengerti. Saya hanya menebak dia itu banyak bicara tentang hubungan kita dan Tuhan.
Kadang-kadang kakak saya tidak mengobrol berdua, ada satu lagi teman mereka yang lebih ganteng dari pemilik rumah dan perpustakaan itu. Orang ketiga itu lebih putih, lebih banyak bicara, dan mungkin karena kulitnya putih maka rambutnya terlihat jauh lebih hitam dari rambut dua yang lainnya. Namun saya sejak kecil sudah tahu bahwa tiga orang sahabatan ini kelihatannya agak susah mendapatkan teman lainnya. Mereka terlalu menikmati semacam ekslusivitas mereka mengingat hampir tak ada lagi pemuda-pemudi sekelas mereka saat itu, yakni kelas yang kalau berjalan di kampung membuat orang mengangguk sementara mereka sendiri hanya melambai kecil disertai senyuman kecil. Orang bisa berhenti dari jalan kaki, sedangkan mereka bertiga itu akan berjalan saja jika berpapasan dengan orang lain, baik itu sebaya ataupun orang tua.
Yang saya tahu, sikap orang-orang semacam itu kepada kakak saya karena kakak saya anak seorang guru. Kepada dua temannya itu saya tidak tahu karena alasan apa, mungkin keduanya anak guru juga, karena sampai sekarang saya tidak pernah tertarik mencari tahu kedua teman kakak saya itu anak siapa. Kalau tidak salah saya pernah mendengar salah satunya—si Rambut Hitam—adalah cucu mantan lurah ternama dulu, seorang yang sering disebut kaum ménak.
Si Rambut Hitam itu pun sama, tidak pernah tertarik masuk ke perpustakaan. Mereka tidak satu pun pernah mengambil salah satu buku atau bundelan majalah untuk menemani mereka mengobrol di teras, meski kadang mengintip melalui jendela perpustakaan untuk memastikan saya ada. Kadang-kadang mereka menggoda saya dengan suara-suara meniru hantu. Saat itulah saya mengenal pertama kali istilah “kutu buku”, panggilan kesayangan si Rambut Hitam buat saya.
Kehausan saya tidak pernah terpuaskan oleh kehadiran perpustakaan terbaik masa kecil saya itu, saya juga terpaksa “harus” mencuri buku-buku lain dari perpustakaan sekolah saya sendiri seakan tidak cukup dengan bacaan-bacaan yang disediakan ibu saya. Itu gara-gara perpustakaan SD kami jarang dibuka dan setengah gudang. Ada rak buku-buku tapi juga ada gulungan-gulungan atlas, karpet, karung-karung tenda, tumpukan kursi rusak, dan benda-benda lainnya, termasuk alat-alat memasak. Tidak ada guru yang betah mengurus ruangan kotor seperti itu. Dan karena lembap dan pengap, ruangan paling belakang ini selalu dibuka sedikit jendelanya dengan ganjalan kayu dan ikatan kawat yang membuat orang di luar tidak dapat menariknya. Tapi kedua tangan kecil saya dapat masuk ke celah jendela itu, dan jika kesempatan ada saya akan mengambil beberapa buku dari rak yang bisa saya jangkau. Saya membuat galah bambu juga untuk menjepit yang tidak terjangkau tangan. Pertama kali saya tahu galah semacam itu di taman-kebun teman kakak saya itu yang biasa mereka gunakan untuk menjepit tangkai kecil (di kampung kami disebut cupat) tempat mangga-mangga muda menggelantung. Ya, mereka senang sekali makan rujak pedas di musim mangga.
Buku-buku apa saja yang saya baca dari mencuri itu, saya sudah tidak dapat mengingat lagi. Beberapa berbahasa Sunda, beberapa berbahasa Indonesia. Beberapa saya kembalikan melewati jendela yang sama, beberapa entahlah. Yang jelas saya tidak pernah membuang satu pun buku.
Kini saya berpikir, jika semua itu dosa, mungkin saya dapat menggantinya dengan buku lagi atau dengan uang. Tetapi bagaimana dengan pengetahuan yang saya miliki? Saya tidak dapat mengembalikan pengetahuan ke tempatnya lagi. Pertanyaan serupa ini pernah didalami Edogawa Ranpo dalam cerpen “Kamar Merah”. Tokoh Tanaka dalam cerpen tersebut adalah seorang yang mengarang cerita tentang dirinya yang pembunuh. Setelah ia mengarahkan seorang penabrak korban kecelakaan ke dokter yang salah, korban kecelakaan itu pun mati, dan ia tahu bahwa kematian itu bukan karena penabraknya, juga bukan oleh dokternya yang gagal memberikan pertolongan, tetapi karena ia yang menunjukkan jalan ke dokter yang salah. Karena itu, ia sadar ia sendirilah pembunuh korban sebenarnya. Jika pencurian buku yang saya lakukan itu pun dosa, tentu yang berdosa pertama kali adalah guru-guru saya yang tidak membukakan perpustakaan dan membiarkan jendelanya dapat dimasuki tangan saya. Jadi, saya tidak usah memikirkan cara mengembalikan pengetahuan ke perpustakaan, tetapi menyiapkan tuntutan untuk siapa saja yang membuat saya berdosa jika kelak Tuhan mengadili saya di Hari Keputusan.
Tuhan semoga membela saya nanti, “Dia hanya anak kecil saat itu dan dia kelaparan-kehausan, dan orang lapar-haus hanya harus makan-minum! Kalianlah, guru-gurunya, yang membuat ia berkali-kali makan-minum pengetahuan dengan cara yang salah! Sungguh, Aku tak pernah menyukai siapa pun yang menghalang-halangi pengetahuan! Masuklah ke neraka kalian, dan ke surgalah wahai anak kelaparan-kehausan! Minum dan makanlah pengetahuan sesuka-sukamu dari buah-buahan dan sungai-sungai dan telaga-telaganya!”
Dan mungkin saya akan memohon, “Tuhan, tapi pengetahuan lain yang saya miliki adalah dari guru-guru saya yang itu juga. Dapatkah mereka diselamatkan karena telah memberi saya pengetahuan? Saya kira Engkau Mahaadil dan akan menyelamatkan siapa pun yang pernah memberikan pengetahuan, meski itu hanya setetes. Saya tahu Engkau, yakin adanya Engkau, karena mereka memberi tahu tentang Engkau. Lagi pula bukan karena mereka malas ke perpustakaan, tetapi sekolah kami tidak punya gudang. Sekolahlah yang harus masuk neraka dan bukan mereka.”
Itu mungkin bedanya cara berpikir saya dengan Edogawa Ranpo, bahwa manusia tidak dapat memikirkan siapa salah siapa benar. Sampai Hari Keputusan nanti manusia masih dapat berdebat soal itu dan keputusan terakhir hanya ada di dalam timbangan keadilan Tuhan semata.
Dan bukan maksud saya menginspirasi siapa pun yang membaca cerita ini untuk menghalalkan pencurian, buku-buku sekalipun. Saya hanya ingin bilang saya adalah pembaca yang kelaparan dan kehausan sejak kecil dan tidak ada satu pun buku menghentikan lapar-haus itu. Makin dibaca satu demi satu, makin lapar makin haus saja. Jadi, “lapar-haus”lah yang harus masuk neraka karena keduanya itu sifat iblis. Sedangkan pengetahuan adalah sifat para nabi dan malaikat pembawa ilmu. Dan karena iblis yang membuat rakus bacaan itu membuat manusia tahu, maka iblis yang mendorong anak-anak membaca harus dipertimbangkan Tuhan juga. Jadi, mungkin saja ada iblis yang masuk surga karena kejahatannya telah menyelamatkan manusia dari lapar dan haus pengetahuan.
Kadang-kadang malah saya berpikir Tuhan sendiri adalah Pengetahuan yang kita curi dari berbagai sumber. Mencuri Tuhan sepertinya perbuatan yang paling Tuhan sukai. []