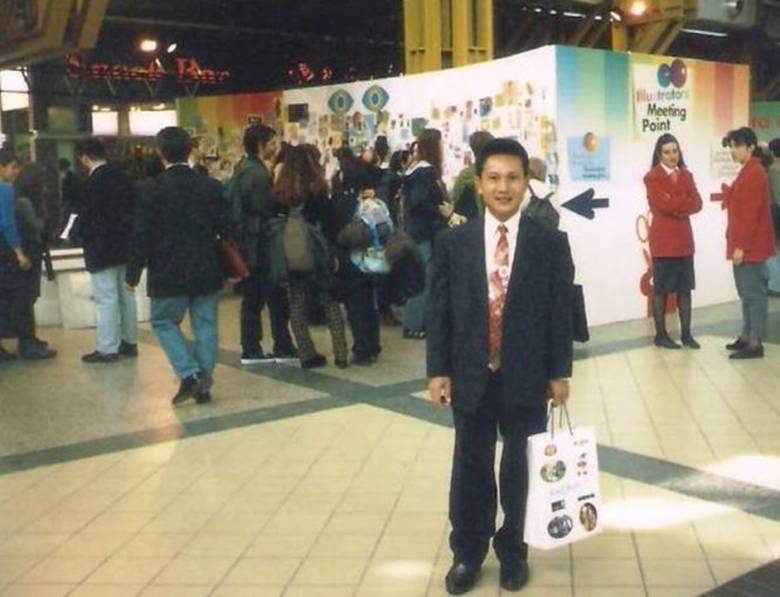Pers Melawan Netizen, Perang antar-Imperium Pengaruh

Tantangan terberat bagi pers dan jurnalisme dalam sepuluh tahun terakhir adalah warganet. Biasa disebut netizen. Pers, media dan jurnalisme di dalamnya adalah awak media, wartawan. Intinya, lawan terberat wartawan adalah netizen.
Lawan? Kok kesannya konfrontatif, mau berantem, mau menang-menangan?
Belum ada teori yang mengatakan bahwa wartawan harus berseteru dengan pembacanya sendiri, dalam hal ini netizen. Kenyataannya, secara tidak langsung -diakui atau tidak- tugas berat wartawan adalah menaklukkan netizen itu sendiri.
Ini zaman penaklukkan, siapa menaklukkan siapa, seolah-olah kita memasuki lorong waktu kembali ke masa kegelapan, ke masa pengukuhan siapa bangsa paling kuat dengan cara menaklukkan lawan-lawannya.
Persoalannya sederhana, sebelum lahirnya imperium baru bernama Internet, di mana imperium itu menciptakan rakyat mandiri yang tangguh, media massa dengan jurnalismenya adalah imperium itu sendiri, setidak-tidaknya jika diperhadapkan dengan rakyat (baca: pembaca) di dalamnya.
Telah banyak disinggung dalam teori komunikasi tentang jarum hipodermik, di mana pembaca pasif begitu saja saat media massa menyuntikkan informasi. Persis seperti saat ini soal kewajiban vaksinasi yang tidak boleh ditolak, jarum hipodermik pada masa lalu yang berisi cairan informasi disuntikkan begitu saja kepada pembaca tanpa bisa bereaksi, apalagi menolak. Pembaca tidak lebih dari berhala yang pasif, tidak berdaya.
Persoalannya jarum hipodermik berisi cairan informasi sekarang ini ada gejala sudah tumpul, tidak bisa lagi menembus kulit pembacanya. Beberapa jarum itu bahkan patah sebelum menembus kulit. Cairan informasi pun tumpah, tidak mengenai sasaran lagi.
Apa pasal? Pembaca sudah punya imunitasnya sendiri. Cairan tubuh mereka sudah penuh berisi informasi macam-macam, yang tidak sekadar mereka peroleh dari media arus utama, melainkan dari media sosial, salah satu bagian dari imperium modern di jagat maya.
Sekarang tugas berat wartawan atau newsroom sebuah media adalah bagaimana meyakinkan pembaca untuk mempercayai apa yang mereka tulis, bukan sekadar pekerjaan menulis informasi atau berita. Bukankah setelah merebaknya blog gratisan di awal tahun 2000an atau dua dekade lalu semua orang bisa menjadi wartawan?
Lihat, betapa adagium klasik "kita semua bisa jadi wartawan" dengan mudah mengkudeta Raja berkuasa bernama "wartawan". Makna wartawan atau jurnalis -yang sejatinya profesi itu diperoleh dengan pengakuan dan diraih dengan susah payah- telah direduksi sedemikian sadis hanya dengan jargon "kita semua wartawan".
Ada puluhan aplikasi kedokteran dan "self healing" yang bisa dilakukan siapapun, tetapi tidak ada jargon "kita semua dokter". Ada banyak pelatihan ketentaraan partikelir oleh organisasi atau ormas tertentu, baik untuk melahirkan satuan pengamanan (legal) maupun teroris (ilegal), tetapi tidak ada jargon "kita semua tentara".
Tetapi, mengapa profesi "wartawan" dengan mudah dikudeta oleh para blogger, netizen, buzzer, influencer atau pegiat medsos lainnya dengan mengatakan "kita semua wartawan".
Ini adalah tantangan sesungguhnya wartawan dan media massa saat ini, yaitu menghadapi para netizen yang cerewet, netizen yang sok tahu dan keras kepala, yang tidak percaya begitu saja atas kabar yang disampaikan para wartawan dari media arus utama, padahal peristiwanya ada.
Terus, bagaimana solusinya? Tentu yang optimistis memberi saran; tulislah berita yang sesuai fakta, yang tidak beropini, yang tidak menggurui, yang sesuai etika dan seterusnya.
Baiklah, kalau sudah menulis berita yang sesuai pakem kebaikan di atas tetapi netizen tetap keras kepala dan tetap tidak mau menerima begitu saja informasi yang disuntikkan, apa lagi yang harus dilakukan?
Berat memang. Anda, wartawan yang bekerja di media arus utama saat ini menghadapi gejala serangan jantung mematikan bagi media yang baru berdiri dan gejala mati suri bagi media massa yang telah lama berdiri. Kue iklan disikat habis salah satunya oleh para pemilik media sosial di mana para netizen, buzzer dan influencer berkumpul di dalamnya.
Baca Juga: "Coma", Media Analog (Cetak) Indonesia?
Kini produsen atau pemasang iklan lebih suka beriklan di media dengan impresi yang transparan, yang terlihat dan terasakan, berapa yang melihat atau mengklik iklan, berapa banyak transaksi yang dilakukan dari klik itu? Kemewahan sederhana yang ternyata tidak dimiliki koran kertas atau bahkan iklan di televisi.
Semakin netizen ramai di sebuah platform media sosial, semakin banyaklah kesempatan uang yang bisa ditimba dari sumur rezeki media baru. Key Opinion Leader (KOL) atau influencer mendapat tempat dan pemasang iklan lebih suka memilih mereka daripada beriklan pasif di media massa. Kenyataan pahit.
Bahkan yang paling ironis, lambat laun netizen, KOL, buzzer dan influencer dengan media sosial di dalamnya diam-diam punya jarum hipodermik sendiri yang berisi cairan informasi "suka-suka" atau "semau gue" yang lambat lain mulai disuntikkan kepada wartawan dan media arus utama di kerajaan newsroom mereka.
Mau bukti? Betapa banyaknya sekarang media massa arus utama dengan wartawan profesional di dalamnya tak berdaya menghadapi suntikan jarum hipodermik dengan mengambil berita yang diproduksi netizen di sejumlah platform media sosial, baik itu dari Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok.
Bukan saatnya bicara apakah dengan cara kerja seperti ini wartawan masih menyisakan mahkota marwah di kepala mereka. Berusaha untuk tetap bisa hidup saja sudah lebih dari cukup.
Selamat Hari Pers Nasional...
***