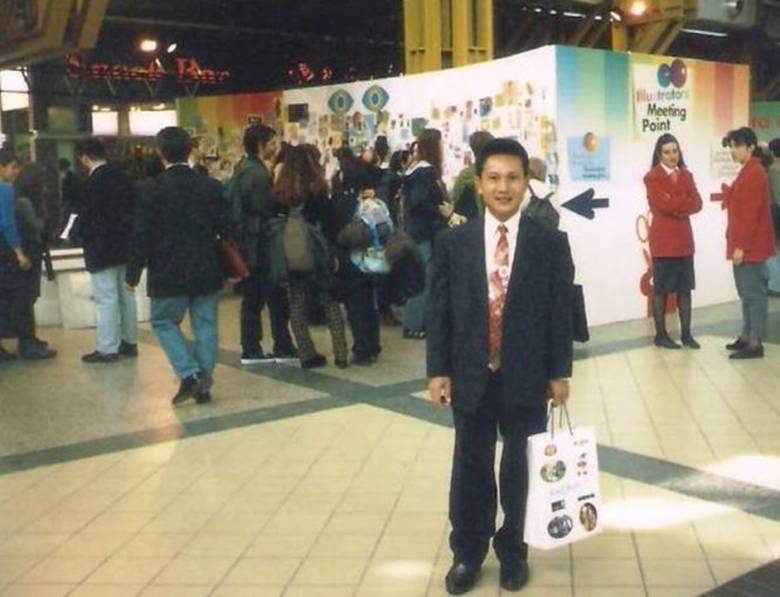Jalan Pulang [3] Memaknai Mitos Pulang Hari Sabtu
![Jalan Pulang [3] Memaknai Mitos Pulang Hari Sabtu](https://assets.ytprayeh.com/img/4r16185e4776261/1d2c3-bed.png)
Rumah sakit besar itu kini terlihat lebih luas dan cantik setelah melakukan renovasi dan pembangunan besar-besaran. Sejumlah ruang rawat lawas masih dipertahankan dengan arsitektur aslinya, sejumlah lain ruang rawat menunjukkan modernitas dan fasilitas mutakhir yang dimilikinya. Tetapi, sebaik-baiknya rumah sakit, tak satu pun manusia sehat bermimpi untuk mencicip menginap di situ.
Tanpa berlama-lama mengagumi kemegahan rumah sakit ini, saya segera menuju ke ruang isolasi, tempat Ibu dirawat. Ya, semenjak pandemi Covid-19, semua pasien yang hendak rawat inap, tetapi terdeteksi masalah pada paru-parunya, harus melewati prosedur isolasi terlebih dulu guna observasi lebih lanjut. Sekian tahun lalu, Ibu memang pernah dirawat di rumah sakit ini untuk penyakit paru-parunya.
Perlahan saya buka pintu lapis pertama ruang isolasi, yang langsung disambut oleh anak saya dan segera mengantar saya memasuki ruang rawat. Tampak Ibu tergolek lemas di ranjang ditemani satu selang infus di tangan. Tak ada sapaan apa pun, selayaknya Ibu sampaikan setiap kali saya pulang ke Jogja. Tak ada pertanyaan kapan datang, naik apa, atau sampai kapan. Tatapannya tanpa ekspresi, seolah kehadiran saya adalah hal biasa, bukan sebuah kejutan sebagaimana biasa.
“Ibu, apa kabar?” sapaku. Tidak ada jawaban selain matanya menatap saya lalu tersenyum kecil. “Ibu tahu, saya siapa?” lanjut saya. Ibu hanya mengangguk tapi tetap tidak memberi jawaban apa pun. Dalam salah satu pembicaraan sebelumnya, anak saya sempat bercerita bahwa kata-kata yang sering diucapkan Ibu sejak di IGD hanyalah “makan” atau “makanan”. Dengan sok pintar, waktu itu saya katakan bahwa itu artinya lapar, minta makan. Tetapi, apa pun makanan yang ditawarkan oleh anak saya ditolaknya semua, sementara kata “makan” sesekali kembali terdengar diucapkan. Jelas hal ini membuat bingung anak usia 20 tahun yang belum punya pengalaman apa pun dalam urusan merawat orang sakit.
Hari ini saya mengalaminya sendiri. Beberapa kali Ibu mengucapkan kata “makan” atau “makanan”, tetapi bukan berarti lapar atau minta makan. Kata itu seolah keluar sendiri dari bawah sadarnya saat ingin mengatakan sesuatu. Ada juga kata “pakaian” yang suka muncul tiba-tiba, lalu disusul dengan sebuah pertanyaan, “aku kenapa?”.
Hari pertama bertemu Ibu, saya sudah disuguhi sejumlah ketidakbiasaan. Ibu tak lagi menjadi pencerita yang antusias terhadap lawan bicaranya. Ia lebih banyak diam. Kekayaan bahasa, cerita, dan kosakata yang saya banggakan selama dalam penerbangan seolah luruh begitu saja. Ke mana perginya ratusan ribu kosakata itu? Ke mana sembunyinya kemahiran aneka tatabasa dari berbagai bahasa? Kenapa hanya tersisa “makanan” dan “pakaian” ditambah kekacauan tatabahasa? Sejenak saya menggugat keadaan itu, namun masih tersembul secercah harapan, barangkali ini hanya sementara karena sedang sakit. Perlahan dan dengan pilihan kata sederhana saya menceritakan kronologi kejadian hingga Ibu harus dirujuk ke rumah sakit, meski tampaknya Ibu tetap tidak sanggup menangkap dengan jernih apa yang saya sampaikan, bahkan kembali bertanya “aku kenapa?”. Hening.
Setelah masa observasi dilalui dan aman dari kemungkinan tertular virus Covid-19, Ibu dipindahkan ke ruang rawat untuk beberapa hari ke depan. Tiga dokter yang menangani, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung, dan dokter spesialis saraf. Dua dokter yang pertama saya mengenal baik karena memang Ibu rutin kontrol kepada mereka. Kehadiran dokter saraf seolah menambah “koleksi” dokter yang menangani kesehatan Ibu di masa senjanya ini. Ada yang berbeda dari cara dokter spesialis saraf ini berkomunikasi—ia mengajak pasien mengenali hal-hal sederhana seperti menanyakan nama pasien, nama anak, atau alamat rumah, lalu mengajak pasien menirukan beberapa gerakan, dan terus diulang. Namun, saya lihat Ibu cukup kesulitan untuk meladeninya, selain hanya mengatakan, “saya tahu, tapi saya tidak bisa....” (belakangan saya baru paham maksud Ibu, yaitu tahu jawabannya tetapi tidak bisa mengucapkannya). Ini bukan lagi perkara yang akan purna dalam 3-4 hari, bisa lebih dari itu, begitu bisik hati kecil saya.
Tepat lima hari dirawat, persisnya di hari Sabtu, Ibu diperkenankan pulang. Sejak Jumat malam dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis jantung sudah membolehkan pulang, tetapi tetap menunggu izin dari dokter spesialis saraf yang baru akan melakukan visit pasien pada Sabtu pagi. Mendengar kata “pulang” sontak raut wajah Ibu menunjukkan kegairahan. Sejak Sabtu pagi ia sudah bersiap. Sarapan yang biasanya memakan waktu cukup panjang, tiba-tiba saja berlangsung kilat. Kata “pulang” terus diulangnya bahkan hendak segera bangkit dari tempat tidur.
Saya coba jelaskan bahwa kita masih harus menunggu keputusan dari dokter spesialis saraf. Namun, penjelasan itu tak lantas menyurutkan niat Ibu untuk cepat pulang. Oleh karena itu, begitu dokter spesialis saraf datang, Ibu berusaha menunjukkan bahwa dirinya sudah lebih baik—meski kenyataannya belum banyak perubahan—toh akhirnya pasien diperkenankan melanjutkan perawatan di rumah. Untuk penanganan lebih lanjut, secara khusus saya mengatur waktu untuk bertemu dengan dokter spesialis saraf.
Atas izin ini, tiba-tiba saja alam bawah sadar saya “menyalakan alarm” mengingatkan adanya sebuah mitos bahwa tak elok pasien pulang dari rumah sakit pada hari Sabtu. Konon, pasien yang melanggar mitos itu dalam waktu dekat akan kembali masuk ke rumah sakit. Meski ini sekadar mitos, nyatanya masih saja banyak percaya dan tentu akan menyebabkan BOR (Bed Occupation Rate) rumah sakit meningkat setiap hari Sabtu. Bila hal ini terjadi, akan menyulitkan calon pasien yang memerlukan ruang rawat segera. Itulah yang terjadi pada saya, mencari celah agar tidak perlu cepat-cepat pulang. Berbagai upaya penguluran waktu saya lakukan, mulai dari berlama-lama mengurus administrasi hingga menjanjikan pulang setelah jam makan siang bahkan seusai mandi sore.
Sebenarnya, saya tak terlalu ambil pusing pada mitos yang sering saya dengar itu. Pun saya juga tak hendak meremehkan mitos karena saya percaya mitos hidup dalam denyut nadi masyarakat, menjadi bagian dari kearifan lokal, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta diyakini kebenarannya oleh para penganutnya. Roland Barthes, seorang filsuf sekaligus kritikus sastra dan semiolog Prancis dalam bukunya Mythologies, kurang lebih juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, mitos (mite) merupakan cara suatu budaya menandai dan memberi makna pada alam sekitarnya. Apa pun bisa menjadi mitos, karena setiap produk budaya memiliki makna.
Jadi, entah kenapa, meski sudah puluhan tahun meninggalkan kota kelahiran dan tinggal di kota metropolitan, hari itu saya mengalami dilema atas mitos tentang pulang hari Sabtu yang terus berseliweran dalam pikiran, tanpa saya pahami bagaimana ia tetiba muncul. Maka, saya putuskan ambil jalan tengah, putar akal untuk mengulur waktu, kalaupun tidak bisa mengulur hari, setidaknya pulang selepas pukul 15.00 WIB atau malam sekalian. Sayangnya, segala upaya perpanjangan waktu itu hanya bertahan hingga pukul 14.00 WIB. Semua urusan justru berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Alasan apa lagi yang harus disampaikan? Tidak ada. Ini benar-benar waktunya pulang.
Sepanjang perjalanan pulang, tidak banyak yang kami lakukan selain memandang sibuknya jalanan menuju ke rumah, barangkali orang sudah mulai bersiap untuk menikmati weekend. Ibu memandang ke luar jendela mobil, tidak banyak berkata-kata karena memang masih sangat sulit untuk berkomunikasi. Namun, dari wajahnya terpancar rasa lega karena boleh pulang ke rumah. Semuanya tampak baik-baik saja dan saya pun telah melupakan mitos yang sedari siang bermain di pikiran. Mungkin memang saya yang terlalu berlebihan menghadapi situasi ini, begitu saya mencoba menenangkan kegalauan, mitos itu hanya berlaku pada zamannya, yang berjarak sangat jauh dari zaman digital ini. Kami pun akhirnya melewati malam itu dengan makan malam bersama dan tidur nyenyak—terlebih saya yang sejak mendarat dari Jakarta hanya tidur di atas sofa bagi penunggu pasien di ruang rawat inap rumah sakit. (bersambung)