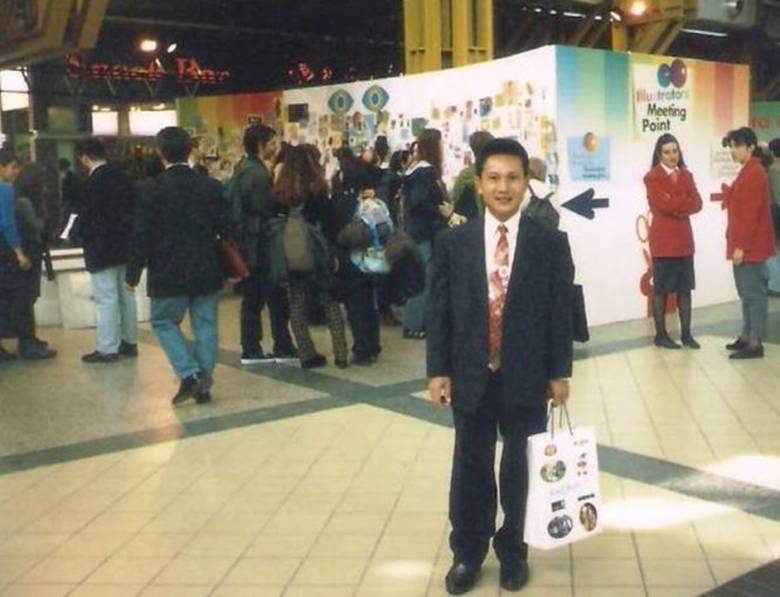Salah Kaprah Budaya "Toleransi"

“Apakah tidak ada toleransi buat saya mas?” tulis seorang mahasiswa, dalam sms-nya. Dia meminta kebijakan berbeda terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Menurutnya, dia layak mendapatkan toleransi dari aturan tersebut. Tapi saya menjawab, “Maaf tidak ada toleransi.”
Saya tidak begitu peduli apakah kata toleransi tepat untuk meminta keringanan dari sebuah aturan. Yang terpenting bukan tepat atau tidaknya kata itu, melainkan makna dari tujuan si peminta toleransi. Sudah sering kuping ini mendengar bagaimana seseorang meminta atau memelas mengharapkan toleransi dari sebuah aturan.
“Saya mohon toleransi mas,” ucap mahasiswa lain yang datang terlambat. Padahal, saya sudah memberikan toleransi (terlambat) sampai 30 menit dari jadwal seharusnya. Dia masih telat juga. Jawaban saya tetap sama, “Maaf tidak ada toleransi.”
Tampaknya, melanggar aturan dengan cara halus atau kasar sudah menjadi semacam budaya di negeri kita. Jangan heran jika ada pameo yang menyebutkan, “Aturan dibuat untuk dilanggar.” Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Buat apa kita capek-capek bekerja, membuang waktu, tenaga dan pikiran untuk membuat aturan, jika setelahnya justru dilanggar dengan mudah, memanfaatkan cara halus semacam toleransi tadi atau cara terang-terangan. Herannya lagi, kita tampaknya senang-senang saja dengan budaya semacam itu. Seperti tak ada apa-apa. Hidup berjalan normal apa adanya. Sungguh menyedihkan.
Budaya toleransi busuk itu ternyata tidak hanya mewabah di masyarakat, mulai kelompok masyarakat bawah sampai kelas atas, tapi juga mewarnai kehidupan birokrasi kita. Saya duga, inilah salah satu penyebab kenapa begitu sulitnya memberantas budaya brengsek seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, sogok, suap dan sejenisnya. Setiap kali sebuah aturan ditetapkan bahwa pejabat dilarang menerima gratifikasi (suap) dalam bentuk apapun, setiap kali itu pula kita bertanya, “Toleransinya sampai sejauh mana?”
Ketika saya berjumpa dengan seorang mantan pejabat tinggi negara dalam sebuah diskusi, hal tersebut juga mengemuka dengan sangat jelas. Sang pejabat, seolah tidak merasakan, ada kesalahan sedikit pun dalam sikapnya. Menurutnya, kita tidak mungkin menerapkan suatu sikap terlalu keras dan kaku. “Idealisme memang penting, tapi perlu toleransi di sana sini,” ucapnya sangat bijak. Dia menyebutkan, bahwa setiap pejabat negara termasuk menteri tidak bisa bersikap terlalu galak atau tegas, apalagi kepada anak buahnya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. “Bagaimana pun kita tetap harus toleransi, karena adanya faktor pertemanan, kerabat, suku, kelompok atau agama,” tambahnya.
Pejabat tersebut kemudian menjelaskan panjang lebar tentang perilaku korupsi di departemennya. Dia menegaskan tidak melakukan korupsi. Tapi anak buahnya iya. Dia tidak bisa melarang secara saklek tindakan korupsi anak buahnya, karena sikap toleransi tadi.
“Ya kalau mencari untungnya 60 persen sampai 90 persen, itu namanya kebangetan. Saya minta kepada mereka untuk hanya 10 persen saja. Itu batas toleransinya,” paparnya. Kesimpulan sang pejabat ini juga luar biasa terkait budaya toleransi ini, “Korupsi sulit diberantas, tapi bisa dikurangi.”
Akibat budaya toleransi tersebut, semua aturan, batasan dan segala macamnya, bisa melar seperti karet. Fleksibel. Tapi sayang, melarnya lebih banyak keluar (negatif), dan tidak pernah melar ke dalam (positif). Bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang sangat toleran, terkait dengan kehidupan beragama. Sayang toleransinya kebablasan di segala bidang, sehingga bau busuk menyebar ke mana-mana.