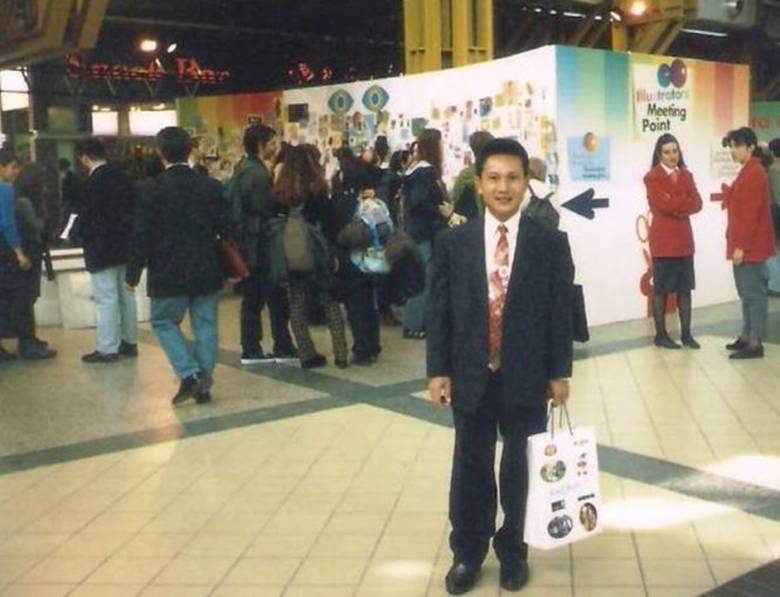Ngayau [1] Ragam, Motivasi dan Komodifikasi Budaya
![Ngayau [1] Ragam, Motivasi dan Komodifikasi Budaya](https://assets.ytprayeh.com/img/8y15974866298fb/2b2d0-gambar.jpg)
Ngayau. Sesungguhnya, ia beragam. Dan tidak sembarangan. Ada aturan hukum adatnya. Hanya boleh dipekikkan jika benar-benar mengancam eksistensi klan/ suatu kaum dan menyangkut kehormatan dan martabat suku bangsa Dayak secara keseluruhan.
Ngayau sesungguhnya banyak ragamnya. Di kalangan suku Ibanic, dikenal dua macam ngayau, yakni: kayau anak dan kayau besai. Dalam pengayauan, terjadi fairness. Prajurit lawan prajurit. Kopral lawan kopral. Jenderal lawan jenderal head to head. Tidak boleh curang.
Kayau anak jika perang / balas dendam antarsesama keluarga saja, tidak melibatkan banyak orang, atau warga kampung. Sedangkan kayau besai baru melibatkan warga seluruh kampung, bahkan sebuah klan berhadapan dengan klan, atau satu wilayah berhadapan dengan wilayah lain.
Bela rasa adalah alasan utama mengapa ngayau selalu melibatkan seluruh warga Dayak, bukan karena takut head to head. Kehormatan klan/ suku dan mempertahankan wilayah adalah dua casus belli (tindakan memicu) ngayau dari masa ke masa.
Hal yang hampir sama dalam setiap subsuku Dayak ialah bahwa: harus ada alasan kuat, yang masuk akal, untuk ngayau. Jika tidak, bahkan orang yang memprovokasi atau menyebarluaskan isu untuk ngayau dapat dikenakan sanksi/hukum adat.
Mangkok Merah
Adalah sarana komunikasi untuk mengajak warga ngayau apa yang disebut dengan “Mangkok Merah”. Mangkok Merah pada hakikatnya adalah sarana komunikasi antarkampung untuk menyampaikan berita adanya bahaya/ancaman melanda sebuah kampung/komunitas tertentu. Mangkok merah terdiri atas beberapa unsur, seperti:
- Mangkok
- Darah ayam
- Abu
- Daun kajakng
- Batang korek api dan
- Bulu ayam
Mangkok Merah disampaikan berantai dari satu kampung ke kampung lain, tidak boleh menginap. Pembawa mangkok merah yang menyampaikannya wajib menerangkan maksud mangkok merah itu kepada penerima, sehingga warga kampung dapat segera menanggapinya.
Dalam hukum adat Dayak Jangkang tegas disebutkan bahwa...” Mengedarkan Mangkok Merah tidak boleh sembarangan, harus dipertimbangkan alasan-alasan yang masuk akal, dan untuk itu, perlu meminta pertimbangan tokoh/tetua adat.Mengedarkan Mangkok Merah haruslah dilandasi alasan yang kuat, yakni alasan yang menyangkut kepentingan umum serta berdampak luas pada tatanan sosial yang hakiki. Seseorang/kelompok yang mengedarkan Mangkok Merah tanpa alasan yang masuk akal, dapat dikenakan pasal hukum adat tentang Pomomar Darah karena berbohong kepada publik.
Motivasi Ngayau
Sesungguhnya, banyak orang luar salah di dalam memahami ngayau. Adalah Carl Bock (1881) yang membuat bias pemahaman khalayah ihwal motivasi-motivasi ngayau. Sebagai orang luar, ia tidak memahami esensi dan latar belakang ngayau dan hanya mereduksinya hanya dengan padanan “headhunter”.
Selama ini, otak kita dikonstruk, kesadaran manusia dibentuk oleh media sebagai symbolicreality.Orang Dayak tidak satu pun menulis di masa lalu, sehingga orang menganggap apa yang ditulis antropolog dan penulis asing sebagai benar. Citra orang Dayak di masa lalu dibentuk orang (luar) tanpa bisa, atau tepatnya tanpa daya, untuk diluruskan. Dikatikan dengan motivasi ngayau yang lain, maka bias oleh Bock ini sebuah mislead yang perlu diberikan pemahaman lebih dalam soal ngayau. Bock memandang ngayau dari kacamata kuda, kacamata barat. Tidak menelisik hingga sensus plenior, kedalaman esensinya.
Ngayau berarti : pergi berperang (Fridolin Ukur dalam buku Tantang Jawab Suku Daya (1971). Ngayau berasal dari kata kayau yang berarti “musuh” (Lontaan, hal. 532). Ngayau antar puak Dayak sepakat diakhiri Dayak Borneo Raya untuk mengakhirinya. Ini terjadi pada pada 22 Mei - 24 Juli 1894, ketika diadakan Musyawarah Besar Tumbang Anoi di Desa Huron Anoi Kahayan Ulu, Kalimantan Tengah.
Kita mengenal 5 motivasi ngayau sebagai berikut.
1. Melindungi pertanian dan keperluan upacara. Misalnya, untuk ditarikan dalam upacara Gawai Notokng (di kalangan Dayak Bidayuh), sehingga ngayau dilakukan ketika padi sedang menguning.
2. Mendapatkan tambahan daya (rohaniah). Dikaitkan dengan "tumbal" ketika membangun rumah, jembatan, atau bangunan lainnya.
3. Balas dendam (revenge).
4. Kepala musuh diyakini sebagai penambah daya tahan berdirinya bangunan (J.U. Lontaan (1975: 533-537) .
5. Saya menambahkan satu ini: Survive (mempertahankan diri). Ini sesuai dengan ungkapan, "Si vis pacem, para bellum" -jika menghendaki damai, bersiaplah untuk berperang.
Ngayau tidak terlepas dari keyakinan suku bangsa Dayak sebagai sebuah entitas. Hal ini dapat ditelusuri dari cerita lisan dan tradisi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Menurut keyakinan yang dipegang teguh, orang Dayak yakin mereka adalah keturunan makhluk langit. Ketika turun ke dunia ini, menjadi makhluk yang paling mulia dan, karena itu, menjadi penguasa bumi.
Keyakinan ini pada gilirannya membawa konsekuensi, orang Dayak merasa diri super, invictus, tuan di tanah miliknya. Jika mengganggu dan mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup mereka, etnis lain dapat disingkirkan. Namun, harus ada alasan yang kuat untuk itu. Darah hewan tertentu, apalagi manusia, tabu untuk ditumpahkan. Jika sampai terjadi, mereka akan menuntut balas.
Ngayau di era modern adalah : Sigap, cekatan, awas dan waspada, terampil, selalu membawa alat untuk hidup, presisi, bijaksana, pandai memilah dan memilih sasaran.
Prinsip bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi benar-benar diterapkan. Meski mengalami penyempurnaan dan penyesuaian, sisa-sisa praktik “mata ganti mata, gigi ganti gigi” ini masih diteruskan di Jangkang hingga hari ini.
Pasal-pasal hukum adat Kecamatan Jangkang masih terasa kental nuansa penuntutan atas pertumpahan darah ini. Terbukti dari diaturnya secara detail pasal-pasal yang menetapkan pengadilan atas perkara dari mulai yang terkecil kasus pertumpahan darah hingga mengakibatkan kematian, yang dalam bahasa Dayak Jangkang disebut dengan “Adat Pati Nyawa”.
Satuan untuk menghitung ganti atas pertumpahan darah unik, disebut dengan tael. Di masa lampau, menghilangkan nyawa manusia walaupun tidak sengaja (misalnya tertembak waktu berburu) maupun secara sengaja maka si pelaku akan mengalami kesulitan membayarnya. Seisi keluarga dan sanak saudara akan turut terlibat membantu. Bahkan, bukan tidak mungkin sampai seumur hidup pelaku menunaikan kewajibannya membayar Adat Pati Nyawa.
Pada masa dahulu kala, pengayauan bisa terjadi antara kampung walaupun masih dalam kelompok suku (besar), atau antarsub-etnik dalam kelompok yang sama, atau antara satu suku dengan suku lain. Pengayauan tidak dilakukan dengan suku di luar orang Dayak.
Ukur mengemukakan bahwa pengayauan mempunyai akar dalam struktur kepercayaan orang Dayak itu sendiri. Ia menyebut ada berbagai tujuan dalam melakukan pengayauan ini, yaitu:
Pertama, untuk melindungi suku dan kampung.
Dalam hal ini dikemukakan bahwa kesalahan bagi orang Dayak tidak lain adalah pelanggaran terhadap adat dan tradisi. Pelanggaran adat dan tradisi senantiasa mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan keserasian alam semesta. Hal ini dapat diperbaiki dan diperdamaikan dengan diadakan upacara kurban tertentu. Tari Totong misalnya merupakan upacara tarian yang menunjukkan keberhasilan “mengayau” kepala musuh. Para pengunjung atau peninjau rumah panjang (betang) pada masa lalu, tidak sulit menemukan deretan tengkorak manusia diikat dan digantung dibumbungi (bagian atas di bawah atap) rumah panjang tersebut.
Kedua, untuk mendapat tambahan daya rohaniah.
Seorang Dayak yang akan berangkat “mengayau”, tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada keampuhan senjatanya (mandau, perisai, sumpit), tetapi pada kekuatan jiwa (daya rohaniah) untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa (gana) menurut Ukur terdapat di kepala manusia hasil kayauan.
Ketiga, balas dendam.
Apabila ada seorang anggota masyarakat Dayak dari suku atau sub-suku atau kampung tertentu yang mati terbunuh akibat pengayauan atau sebab lain, maka seluruh anggota suku, sub-suku atau kampung akan mengambil tindakan pembalasan (mengayau). Setiap keberangkatan pagi untuk mengayau, seluruh anggota masyarakat mengadakan upacara untuk memberi restu dan dukungan.
Sejak 1894, pada Pertemuan Tumbang Anoi, praktik pengayauan di kalangan suku bangsa Dayak sepakat untuk dihentikan.
Masih ada satu alasan lagi mengayau yang sangat esensial. Menurut Masri (2012: 138) pengayauan yang lebih pokok adalah upaya pertahan diri untuk menjaga klan atau kelompok sebagaimana pada zaman baheula dipraktikkan suku-suku. Entah dengan alasan menjaga keberlangsungan keturunan, entah dengan alasan menjaga wilayah dan hak-hak ulayat.
Kadang pengayauan bersifat defensif, namun juga bisa ofensif jika situasi kondisi menuntutnya demikian. Dengan demikian, pengayauan tidaklah dapat dipandang hitam putih begitu saja. Pengayauan, dengan demikian, haruslah dipandang dalam konteks sejarah dan tradisi etnis Dayak pada waktu itu.
Toh demikian, tidak semua suku atau sub-suku Dayak memberlakukan tradisi pengayauan. Seorang misionaris, Herman Josef van Hulten, menulis dalam bukunya Hidupku di Antara Suku Daya (1992) bahwa “Waktu itu (1956) Daya Iban masih terpencar-pencar dan dikenal sebagai pengayau yang ulung. Mereka tinggal di rumah panjang dan hingga sekarang masih bisa terlihat di atas serambinya bergantungan tengkorak manusia hasil mengayau”.
Berkaitan dengan tengkorak itu, Nieuwenhuis menulis bahwa Dayak Iban mencampuri “kebiadaban” dengan “keramahan” manusia yang berlebihan. Karena Dayak Iban adalah insan periang sekaligus acuh tak acuh (Hulten, 1992).
Berbeda dengan Ukur, Petebang menyatakan bahwa mengayau adalah adat dan orang Dayak sangat taat pada adat. Dalam konteks adat inilah, hendaknya kegiatan pengayauan dimaknai. Salah satu adat dimaksud, sebagai contoh, adalah apabila seorang melakukan tindakan sampai orang lain terluka dan mengeluarkan darah, hukumannya sangat berat. Demikian Petebang menggarisbawahi (1998).
Di kalangan masyarakat Dayak, suku-suku yang cukup terkenal dengan gaya mengayaunya adalah suku Iban, Punan, Kayaan, Bukat, dan Taman Ambaloh di Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Lamandau dan Delang di Kalimantan Tengah. Sub-sub suku di sepanjang sungai Sekayam, Jangkang di Kabupaten Sanggau. Sungkung, Banyuke dan Kandayatn di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang (Petebang, 1998).
Keputusan Pertemuan Tumbang Anoi mempertahankan adat dan kebudayaan Dayak merupakan kewajaran, karena dari tujuh suku Dayak (kelompok besar) masing-masing mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda. Adat dan budaya masing-masing kelompok besar itu merupakan identitas dari masing-masing suku. Sejak 1894, praktik pengayauan di kalangan suku bangsa Dayak sepakat untuk dihentikan.
Perjanjian Tumbang Anoi (PTA), yang dilaksanakan dari tanggal 22 Mei – 21 Juli 1894 di kampung Tumbang Anoi, sekarang propinsi Kalimantan Tengah, sungguh mengubah arah dan –meski tidak sengaja— telah menumbuhkan kesadaran orang-orang Dayak sebagai sebuah entitas yang esa di kepulauan Borneo. Hadir dalam pertemuan itu seluruh kepala suku Dayak, panglima perang Dayak dan kepala-kepala adat.
Menjadi pertanyaan bagi banyak orang Indonesia di manakah letak kampung Tumbang Anoi itu? Pada saat PTA dilaksanakan tahun 1894, kampung tersebut berada dalam wilayah perhuluan/hulu sungai Kahayan, sekarang di Propinsi Kalimantan Tengah.
Di perhuluan sungai-sungai Katingan, sungai Kahayan, dan sungai Kapuas (Kalteng), banyak terdapat kota kecil yang bernama Tumbang ini atau Tumbang itu. Tetapi tidak ada nama “Tumbang Anoi”. Mungkin kampung tersebut sekarang sudah “tidak ada lagi”. Dari tahun 1894 sampai sekarang (2013), cukup panjang waktunya, sehingga segala kemungkinan dapat saja terjadi.
Menurut catatan Drs Johnly Friady, cucu Damang Batu (Damang Batu adalah kepala adat yang berkedudukan di Tumbang Anoi), tahun 1893 Damang Batu diundang untuk menghadiri rapat para tokoh Kalimantan di Kuala Kapuas, atas prakarsa Residen Banjarmasin untuk membahas penghentian permusuhan antarsuku yang sering terjadi masa itu yaitu mengayau, membunuh,saling penggal, dan perbudakan (hakayau, habunu, hatetek) + hajipen. Istilahnya: 4-H.
Dalam pertemuan di Kuala Kapuas (1893) itu, hanya Damang Batu yang berani mengangkat tangan dan menyatakan kesiapan sebagai penyelenggara dan tempat pertemuan yaitu di Tumbang Anoi. Kesediaan Damang Batu itu lalu disetujui dan disahkan oleh Residen Banjarmasin.
Kontrolir Tanah Dayak dan Kontrolir Melawi memberi keterangan, “Sebagai tempat pertemuan ditunjuk Tumbang Anoi, yang terletak di hulu Kahayan, karena kampung itu, tempat tinggal Damang Ribu (orang Dayak menyebut Damang Batu) cukup besar untuk memberi pemondokan kepada sejumlah besar orang dan sedang didirikan suatu pesanggrahan dan karena itu di sekitar perbatasan-perbatasan tidak terdapat kampung sebesar itu.
Sebenarnya, karena untuk mereka dari kedua daerah, kampung tersebut sama mudahnya atau sama sulitnya untuk dicapai. Tumbang Anoi dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih empat jam mudik ke hulu dari Kuala Kurun, ibu kota Kabupaten Gunung Mas.
Untuk mengadakan suatu pertemuan dengan Kepala-Kepala Adat Dayak dan Melayu, bertempat di Tumbang Anoi pada awal 1894, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang belum diselesaikan dan yang berasal dari pembunuhan untuk mengumpulkan kepala manusia (pengayauan).
Agar pertemuan itu berhasil, Pemerintah kolonial Belanda membeli bahan-bahan pangan (beras, garam, tembakau dan sebagainya) di Banjarmasin yang dibawa juru-pikul kaki tangan Hindia Belanda, diangkut dari Kuala Kapuas ke Kuala Kurun, untuk disimpan oleh kepala sub distrik dan selanjutnya dikirim ke Tumbang Anoi.
Atas upaya residen Borneo Barat, di Muntumoi Ambaloh Hulu dekat titik perbatasan dengan aliran sungai Melawi disimpan 40 pikul beras. Dengan demikian, jelas kelihatan bahwa peswakarsa dan pembiayaan Pertemuan Tumbang Anoi adalah pemerintah kolonial Belanda. Pada kesimpulan laporan kontrolir afdeeling Tanah Dayak AC de Heer dan kontrolir Melawi, afdeeling Sintang, JPJ Barth, dikemukakan bahwa, “Kami senantiasa menyadari bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh banyak orang dari pihak-pihak yang saling bermusuhan, tentulah dapat terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Tetapi kami harus mengakui bahwa sidang-sidang berjalan dengan baik sekali dan tata tertib sidang tidak pernah terganggu.”
"Loooooooooooooooooooooooooooooooooooo....." berteriak dengan suara nyaring, sembari membentang kedua tapak tangan ke arah luar bibir yang terbuka mengucapkannya.
Dijawab, "Kyeww!"
Jika benar terdetreksi demikian, maka mereka orang kita. Dan wajib disambut sebagai tetamu agung.
Permasalahan yang banyak dihadapi adalah kesulitan transportasi air atau sungai. Sehingga dengan demikian kepala-kepala adat dari Melawi terlambat hadir. Memperhatikan keadaan transportasi saat sekarang di Kalimantan Tengah, khususnya yang menuju ke perhuluan sungai-sungai Katingan, Kahayan dan Kapuas, masih menghadapi banyak kesulitan. Apalagi tahun 1894 saat PTA dilaksanakan.
Betapa sulitnya komunikasi dan transportasi pada saat itu. Delegasi yang berangkat dari Kalimantan Barat (Borneo Barat), dari Kalimantan Timur (Borneo Timur), dari Borneo Utara (Serawak dan Sabah) menuju kampung Tumbang Anoi sudah pasti mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Komunikasi dan transportasi di dalam wilayah Kalimantan Tengah (waktu itu masih dalam wilayah Kalimantan Selatan) juga sangat sulit. Akodomasi dipusatkan di Banjarmasin sebagai locus di tengah, yang dianggap strategis. baru diangkut dari laut, masuk jauh sungai Kayan sampai Tumbang Anoi.
Dari wilayah Jangkang (kini hanya berbatasan 2 kecamatan dari Sarawak), sejauh informasi yang dapat saya himpun, datang 2 panglima perang (macatn), yakni macatn Talot dan macatn Natos. Mereka ditemani kontrolur Sintang. Malangnya, di perjalanan, sang kontroleur kakinya tertusuk akar kayu yang tajam. Tenanus. lalu wafat di perjalanan.
Suatu kejadian yang menakjubkan bahwa pertemuan yang beracara merukunkan suku-suku, sub suku Dayak yang sebelumnya sering terjadi pengayauan (perang suku), berjalan baik dan lancar. Tidak ada gangguan yang berarti dalam persidangan. Hal ini memperlihatkan bahwa orang Dayak sebenarnya lebih suka damai, tidak ada sifat agresif.
Menurut catatan para penulis dan pengamat Pertemuan Tumbang Anoi, persidangan menyepakati “penghapusan pengayauan” antarsuku dan sub-suku bangsa Dayak dan mempertahankan adat kebudayaan Dayak sebagai ciri penghuni Bumi Kalimantan, yang saat itu disebut Borneo.
Saya mewawancarai tetua adat dan para pendengar-saksi sejarah ihwal komunikasi mereka. Konon katanya, menggunakan tanda dan simbol.
"Loooooooooooooooooooooooooooooooooooo....." berteriak dengan suara nyaring, sembari membentang kedua tapak tangan ke arah luar bibir yang terbuka mengucapkannya.
Dijawab, "Kyeww!"
Jika benar terdetreksi demikian, maka mereka orang kita. Dan wajib disambut sebagai tetamu agung.
Namun, sudah tentu, karena para ketua adat --temenggung datang seantero Borneo, dengan bahasa yang berbeda, apa bahasa mereka selama hampir 3 bulan pertemuan besa?. Sudah tentu, dengan cakap masing-masing. Dan: bahasa Melayu. Tapi juga ada penerjemahnya.
Setelah Pertemuan Tumbang Anoi, relatif tidak sering terjadi pengayauan (perang antarsuku). Dari penelitian dan pengamatan, sampai dengan tahun 1930 masih ditemukan tradisi mengayau yang dilakukan oleh beberapa sub-suku Dayak antara lain Punan, Iban, dan Lamandau.
Bagi masyarakat Dayak, Pertemuan Tumbang Anoi membawa manfaat besar. Walaupun tidak segera setelah selesai pertemuan perang antarsuku tidak terjadi lagi, tetapi frekuensinya sudah menurun.
Salah besar mengatakan taktik penguasaan kompeni Hindia Belanda atas Nusantara semuanya dengan "divide et impera", politik pecah belah. Ini taktik penguasaan di Tanah Jawa dan wilayah yang berbentuk kerajaan/ kesultanan.
Di Borneo, tanah Dayak, taktik itu disebut: salt starvation – haus darah, karena tiap klan/subsuku saling kayau. Disatukan dulu, baru dikuasai.
Pertemuan Tumbang Anoi memang diprakarsai pemerintah kolonial Belanda. Belanda merasa tidak nyaman waktu mulai masuk pulau Borneo, karena berada dalam keadaan yang sangat rawan, terutama di pedalaman. Sering terjadi pengayauan antarsuku Dayak. Dengan Peraturan Pemerintah tanggal 15 September 1893 no. 12, residen-residen afdeeling Selatan, Timur dan Barat, diberi kuasa, melalui kontrolir Tanah Dayak dan kontrolir Melawi, untuk melakukan kontrol atas suku-suku Dayak. Malangnya, strategi politik salt starvation –kebalikan dari divide et impera—yang dijalankan kolonial berantakan semua karena ternyata para tokoh Dayak bersatu-padu yang sebelumnya saling kayau. Kompeni Belanda kecele oleh taktiknya sendiri.
Ngayau & Komodifikasi Budaya
Meski telah diakhiri usai PTA, publikasi-publikasi asing masih gencar dan dengan sangat senang menangkat ngayau sebagai komoditas yang laku untuk dijual. Selain itu, publikasi-publikasi asing juga sangat suka menjual hal-hal unik dari budaya etnis Dayak, seperti: anting yang menggantung di telinga panjang, pria wanita mengenakan cawat, badan penuh tato, rumah betang yang berantakan, hasil kerajinan tangan dan kesenian lainnya. Itulah komodifikasi budaya.
Pada zaman baheula, praktik-praktik seperti itu harus diakui memang ada. Akan tetapi, seiring perubahan dan perkembangan zaman, kebudayaan asli Dayak sebagian besar sudah tergerus. Utamanya orang yang memakai anting berjuntai di telinga, kini sudah sangat langka ditemukan, kecuali di pegunungan dan di kampung terhulu yang sangat sangat terisolasi.
Evolusi Ngayau
Sesungguhnya, ada 4 tahapan evolusi ngayau:
1. Head hunter yang berarti memenggal kepala (musuh), mempertahankan wilayah, suku, klan. Bisa ofensif bisa defensif dalam ujudnya, dan hanya ini yang dipopulerkan Bock.
2. Dalam dunia olah raga (head hunter) mengumpulkan piala sebanyak-banyaknya.
3. Dunia SDM strategik: membajak tenaga kerja terampil di bidang usaha/ organisasi sejenis.
4. Kini: Berperang melawan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, segala bentuk yang menjadi hambatan kemajuan/peradaban Dayak.
Ngayau di era modern adalah : Sigap, cekatan, awas dan waspada, terampil, selalu membawa alat untuk hidup, presisi, bijaksana, pandai memilah dan memilih sasaran. Evolusi yang pertama dan keempat: Alat berubah sesuai perkembangan zaman, sedangkan makna : tidak. Yakni bagaimana orang Dayak survive dan menjadi tuan di negerinya sendiri.
Intisari ngayau adalah adalah tentang modus vivendi (cara hidup) dan modus essendi (cara berada) manusia Dayak. Bagi orang Dayak, orang yang hidup bagi diri sendiri, cara hidup yang seperti itu adalah: buruk (Qui sibi vivit male vivit) maka mereka membangun dan hidup berkomunal di rumah panjang dan saling tolong. Pada zaman dahulu, jika satu keluarga mendapat hewan buruan maka akan dibagi. Jika ada warga susah, mereka membantu dan meninggalkan pekerjaan hari itu.
Bela rasa adalah alasan utama mengapa ngayau selalu melibatkan seluruh warga Dayak, bukan karena takut head to head. Kehormatan klan/ suku dan mempertahankan wilayah adalah dua casus belli (tindakan memicu) ngayau dari masa ke masa.
(Bersambung)
***