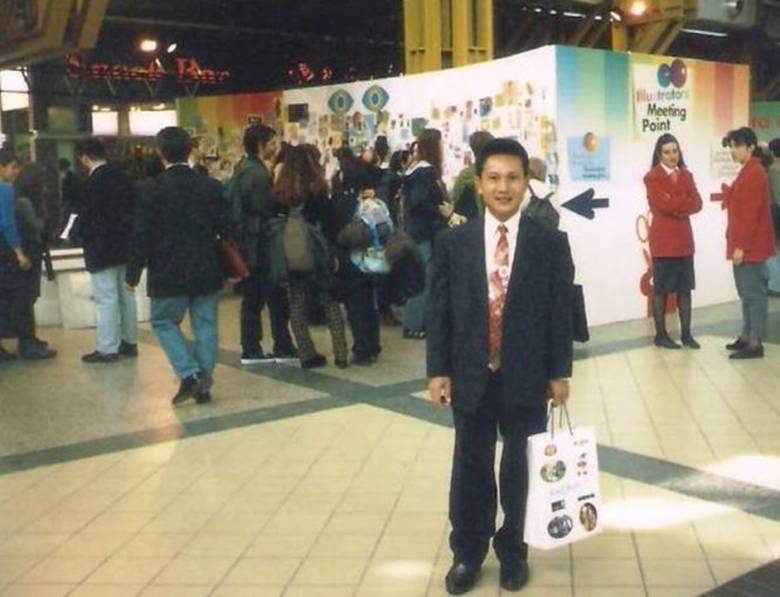Jelajah Kaltara [4] Filsafat Nusantara, Kearifan Budaya Indonesia
![Jelajah Kaltara [4] Filsafat Nusantara, Kearifan Budaya Indonesia](https://assets.ytprayeh.com/img/6e15974a66095ca/25bc7-Screenshot_2021-04-19-07-26-19-62.jpg)
Jika ada yang bertanya siapa yang lebih mendekati “filsuf” alias jago berfilsafat di antara kami bertiga pegiat literasi, yaitu saya, Masri Sarib Putra dan Dodi Mawardi, tentu saja jawabannya Pak Masri, demikian kami memanggilnya.
Selain berlatar belakangnya filsafat, penulis 106 buku dan 4.000 artikel ini fasih saat berbicara filsafat Barat, khususnya filsafat Yunani.
Maka saat Pak Masri bertausiyah tentang Plato, Aristoteles dan Phytagoras, saya seperti terseret ke masa silam, dipaksa duduk di sebuah taman dengan pilar-pilar yang diukir, ke zaman Yunani kuno. Saya melihat gambaran para filsuf Yunani yang sedang berbagi kebijaksanaan.
Filsafat yang dalam khasanah keilmuan disebut Philosophia berasal dari kata philia (cinta) dan sophia (kebijaksanaan). Filsafat berarti cinta kebijaksanaan.
Apa itu kebijaksanaan? Tidak lain segala yang ada dan bisa dipertanyakan. Esensi filsafat memang bertanya dan bertanya dengan jawaban yang tidak pernah terpuaskan.
Kefasihan Pak Masri berfilsafat Yunani mendapat tantangan dari Yansen Tipa Padan, birokrat sekaligus pegiat literasi yang menjadi senior kami bertiga, pada suatu malam yang pekat dan berguntur di Bang Abak, Malinau, sebuah “ranch” terpadu tempat kami biasa berdiskusi.
“Mengapa harus jauh-jauh ke Yunani, mengutip pemikiran mereka, bukankah kita sebagai bangsa Indonesia juga punya kebijaksanaan kalau filsafat bermakna cinta kebijaksanaan? Jangan jauh-jauh, cobalah ungkap Filsafat Nusantara itu,” tantangnya.
Di malam saat tirai gerimis terkembang dan pawana menerpa dengan kencang dari arah lembah bukit, Pak Yansen yang kini menjabat wakil gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) sedikit mengungkapkan alam berpikir bangsa Indonesia pada masa lalu.
Ia berpendapat, sebelum tahun 1908 pun alam berpikir bangsa Indonesia sudah mengerucut pada kemerdekaan, lepas dari belenggu penjajahan, agar bisa bertindak dan berpikir bebas. Berfilsafat memang identik dengan berpikir bebas atau bebas berpikir.
Duapuluh tahun kemudian tercatatlah peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda 1928 di mana para pemuda dari berbagai suku bangsa menyamakan persepsi, meneguhkan sikap berbangsa dan awal mula bernegara dengan menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.
Di mata saya pribadi, Sumpah Pemuda ini merupakan kelanjutan dari Sumpah Palapa yang dikorbarkan Mahapatih Gajahmada yang bertekad menyatukan Nusantara.
Kata “Nusantara” ini tercetus dari Gajahmada untuk memaknai pulau-pulau di luar Pulau Jawa, sebab “nusa” bermakna pulau dan “antara” adalah ruang dan jarak pemisah. Nusantara yang dimaksudkan Mahapatih itu tidak lain penyatuan antara Pulau Jawa di mana kerajaan Majapahit berdiri dengan pulau-pulau di luar Pulau Jawa.
Pun ketika harus menjawab tantangan Pak Yansen tentang Filsafat Nusantara, titik tolak dialektik saya adalah Sumpah Palapa yang menghasilkan kata “Nusantara” itu.
Lalu apa objek formal yang dibicarakan Filsafat Nusantara? Dalam pandangan saya, tidak lain manusia Indonesia dengan kebudayaan yang melekat pada dirinya.
Singkatnya, Filsafat Nusantara berbicara tentang manusia Indonesia dengan kebudayaannya, alam pemikirannya dan kearifannya. Kearifan di sini tidak lain kebijaksanaan yang merupakan makna dari filsafat itu sendiri.
Jika ditanya apa “babon” dari kebijaksanaan bangsa Indonesia, tidak lain adalah Pancasila yang menjadi ideologi bangsa. Di sana terdapat sejumlah kearifan atau kebijaksanaan inti yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia.
Induk kearifan itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Sansekerta yang secara harafiah bermakna “meski terpecah-pecah tetapi tetap satu juga”.
Ah, itu biasa, tidak ada istimewanya, bukankah semboyan serupa dimiliki pula oleh Amerika Serikat dengan “e pluribus unum”-nya?
Benar, tetapi hanya sampai di situ saja, sedangkan falsafah yang terkandung dalam Pancasila jauh lebih holistik lagi. Coba lihat perisai Garuda itu, di sana ada lima gambar yang melambangkan lima sila yang menjadi “way of life” Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Berbicara Indonesia termasuk filsafat, tidak lepas dari beraneka ragam suku bangsa yang hidup di dalamnya. Mereka hidup selain menjadikan Pancasila sebagai cara pandang dan jalan hidup, mereka masih terikat oleh kearifan lokal masing-masing suku.
Jika kita bersepakat tidak kurang dari 700 bahasa yang hidup di Nusantara, maka kurang lebih ada sebanyak 700 suku dengan kearifan lokalnya masing-masing. Jelas kebijaksanaan mereka jika dikumpulkan akan melewati butir-butir filsafat Yunani yang dicetauskan Plato, Aristoteles maupun Phytagoras.
Tidak jauh-jauh, karena kami saat itu sedang berada di Malinau, di Kalimantan yang dikenal sebagai “rumah suku dayak”, ada subsuku dayak seperti Kenyah, Iban dan Lundayeh. Masing-masing subsuku ini memiliki kearifan dan kebijaksaan sendiri dalam bahasa mereka masing-masing.
Sebagian suku dayak misalnya menganut kepercayaan Kaharingan yang menyembah roh para leluhur mereka yang disebut Orai Langit dan Dara Bura Orai Tiana.
Para leluhur inilah yang memandu orang Dayak pada umumnya bagaimana mereka wajib menjaga keanekaragaman hayati, tata cara bercocok tanam, melakukan ladang berpindah, membuka lahan pertanian, mencari jodoh, sampai kepada keharusan berperang jika terpaksa mereka lakukan.
Sebelum Pancasila lahir, sebelum Sumpah Pemuda diucapkan dan Sumpah Palapa dikumandangkan, mungkin saja kearifan lokal suku Dayak ini sudah ada. Dan Dayak hanyalah satu dari 700 suku yang ada. Belum lagi kearifan suku Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Batak, Ambon, Papua dan seterusnya.
Itulah Filsafat Nusantara yang sesungguhnya. Karena berbagai falsafah hidup di dalamnya, maka disadari atau tidak, yang mempersatukan mereka sehingga menjadi bangsa Indonesia adalah memahami "Subjektivitas Budaya" satu dengan yang lainnya.
Apa itu "Subjektivitas Budaya"?
Karena malam telah semakin larut di Bang Abak, jelang tengah malam kami harus beranjak dan berpindah tempat diskusi yang baru berakhir lewat dinihari, jelang makan sahur tiba.
(Bersambung)