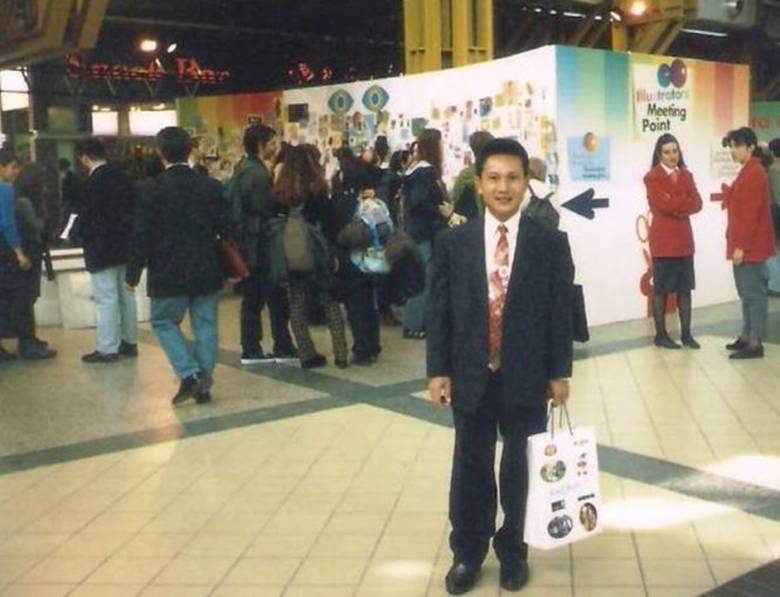Mengurai Jati Diri Manusia dalam Fenomena “Belalak”

Belalak. Bukan Balala. Balala merupakan ritual adat dalam suku Dayak Kanayatn untuk memohon kepada Jubata agar terhindar dari bencana dan malapetaka.
Belalak sendiri adalah bahasa kami suku Dayak Desa. Istilah ini diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang merasa belum terpuaskan baik secara lahiriah/jasmaniah maupun secara batiniah/rohaniah. Setiap sub suku Dayak pasti memiliki istilahnya tersendiri seturut bahasa masing-masing.
Untuk sedikit membantu kita memahaminya, saya akan memberikan sebuah contoh dari pengalaman pribadi saya. Tahun 2014 saya mendapat tugas perutusan ke paroki Ambalau, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Tentu saja saya menyambut dengan gembira hati tugas perutusan tersebut. Namun, ada satu hal lain lagi yang membuat saya begitu gembira, yakni mengetahui kalau untuk sampai ke paroki Ambalau saya harus menggunakan speed boat. Saya sangat gembira karena ini akan menjadi pengalaman pertama dalam hidup saya menempuh perjalanan sekitar 6-7 jam menggunakan speed boat.
Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan tentunya. Namun, karena saya begitu bersemangat untuk menyusuri sungai Melawi menggunakan speed boat, rasa lelah itu pun seakan hilang dengan sendirinya. Ketika sudah sampai di tujuan, saya pun masih merasa belum puas. Karena itu, dalam perayaan misa hari Minggu saya mengatakan kepada umat kalau saya masih belalak naik speed.
Belalak: Bukan tentang Manusia sebagai Makhluk yang Tak Pernah Puas
Dari kehidupan sehari-hari komunitas adat suku Dayak Desa sendiri ada beberapa contoh yang bisa diambil untuk semakin memperjelas pemahaman tentang belalak. Dari dunia kehidupan bayi, misalnya. Saat bayi menangis setelah selesai menyusu atau setelah bangun tidur, oleh masyarakat setempat situasi demikian dinamakan dengan belalak.
Contoh lain lagi ialah dalam hal makan. Ketika seseorang baru selesai makan, lalu masih ada butiran nasi menempel di dagunya, misalnya, oleh mereka yang melihatnya, orang itu akan dikira masih belalak makan.
Dari realitas hidup sehari-hari di mana istilah ini sering digunakan, saya berani menyimpulkan kalau istilah ini mengandung makna yang positif. Dengan kata lain, fenomena belalak tidak hendak menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak pernah puas. Memang, saat seseorang berada pada kondisi belalak ada sesuatu yang belum terpuaskan. Akan tetapi, hal ini kemudian tidak berarti orang tersebut akan melakukan apa saja demi memuaskan hasratnya.
Bayi yang menangis sehabis menyusu tidak kemudian dipaksa untuk menyusu kembali oleh ibunya. ASI memang penting untuk tumbuh kembang si anak. Tapi, ibu yang bijaksana pasti tahu kalau terlalu berlebihan memberi ASI juga tidak baik untuk si buah hati. Demikian juga dengan seseorang yang baru selesai makan. Dia tidak akan kembali untuk makan lagi hanya karena menyadari masih ada butiran nasi yang menempel di dagunya.
Bahwa orang tersebut belum kenyang mungkin ada benarnya. Tetapi, keputusannya untuk tidak kembali makan itu mau menunjukkan sebuah sikap: berani berkata cukup. Dia tentu menyadari kalau terlalu banyak makan, juga tidak baik untuk kesehatan badannya.
Fenomena belalak, dalam hemat saya, dapat menjadi instrumen dalam menguak hakikat manusia sebagai makhluk spiritual. Dan juga pada saat yang sama bisa menjadi alat kritik bagi manusia yang mengaku diri sebagai makhluk spiritual, tapi malah seringkali diliputi oleh keserakahan. Dalam hal ini, saya akan mengaitkan belalak dengan kearifan berladang suku Dayak. Karena, dalam hemat saya, cara berladang yang mereka praktekkan, menampilkan harmoni yang indah dalam upaya menjaga keutuhan ciptaan.
Manusia sebagai Makhluk Spiritual
Izinkan saya menggunakan salah satu kisah dalam Kitab Suci orang Katolik. Dalam hemat saya kisah ini dapat menjadi contoh untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Atau dengan kata lain, untuk menunjukkan bahwa manusia dalam hidupnya tidak cukup hanya mengejar kepuasan lahiriah. Kisah tersebut adalah tentang Yesus yang menyatakan diri-Nya sebagai roti hidup (Yoh. 6:1-59).
Dalam Yoh. 6:1-15 dikisahkan tentang Yesus yang memberikan lima ribu orang. Orang banyak ini berbondong-bondong mengikuti Yesus karena telah melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan-Nya terhadap orang-orang sakit. Melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, Ia berkata kepada Flilipus: “Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?” Dengan nada pesimis Filipus menjawab: “Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.” (Ay.5-7)
Di tengah-tengah mereka ada seorang anak kecil yang mempunyai lima buah roti dan dua ikan. Lima roti dan dua ikan itu pun lalu diserahkan kepada Yesus. Yesus kemudian mengucap syukur atas lima roti dan dua ikan itu dan lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semua pun makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa dua belas bakul penuh dari potongan-potongan roti setelah mereka selesai makan.
Mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengadakan mukjizat, orang banyak itu pun selalu berusaha mencari dan menemukan Yesus. Namun, Dia mengetahui gelagat orang banyak tersebut. Karena itu, saat mereka menemukan-Nya, Dia berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.” (Ay.26). Kemudian Ia melanjutkan dengan menunjukkan kepada mereka makanan seperti apa yang harus mereka usahakan: “Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.” (Ay.27).
Perkataan Yesus tersebut telah menggugah hati orang banyak. Karena itu, mereka berkata kepada-Nya: “Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?” Jawab Yesus kepada mereka: “Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.” (Ay. 28-29).
Yesus kemudian meyakinkan orang banyak bahwa Dia yang telah diutus Allah – yang tak lain adalah diri-Nya sendiri – adalah sungguh roti hidup yang telah turun dari surga. Ia berkata kepada mereka: “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.” (Yoh 6:35).
Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa Yesus tidak sepenuhnya menyalahkan orang banyak yang mencari-Nya karena telah merasa kenyang. Secara tidak langsung Yesus mau menunjukkan bahwa kepuasan lahiriah itu juga penting bagi manusia. Sikap dan pandangan Yesus ini juga sejalan dengan pemahaman tentang belalak seperti yang telah saya paparkan. Meski dalam artikel ini saya menekankan kepuasan rohaniah/batiniah sebagai tujuan tertinggi dari hidup manusia, tidak berarti kemudian kepuasan lahiriah itu jelek adanya.
Akan tetapi, sekali lagi, sebagaimana yang diingatkan oleh Yesus terhadap orang banyak, tidak cukup bagi manusia hanya sampai pada kepuasan lahiriah. Oleh karena itulah, Ia menunjukkan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Orang banyak dituntut untuk percaya karena Dia yang diutus oleh Allah itu merupakan Sang Roti Hidup yang akan membuat mereka tidak akan lapar dan haus lagi.
Konsili Vatikan II, dalam dokumen Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (Gaudium et Spes), ketika secara spesifik mengurai tentang martabat pribadi manusia menyatakan bahwa dengan tubuh jasmaniahnya yang sudah terluka oleh dosa, manusia tetap dipanggil untuk “melambungkan suaranya untuk dengan bebas memuliakan Sang Pencipta... Maka dari itu martabat manusia sendiri menuntut, supaya ia meluhurkan Allah dalam badannya, dan jangan membiarkan badan itu melayani kecondongan-kecondongan hatinya yang tidak baik.” ( GS. 14).
Dalam bahasa Paus Yohanes Paulus II, upaya manusia untuk selalu memuliakan dan meluhurkan Sang Pencipta dalam badannya dinamakan sebagai suatu pengalaman ‘melintas batas’: menemukan yang terdalam di balik yang dangkal, yang luar biasa di dalam ketertubuhan yang biasa, yang misteri di balik yang jasmani, atau yang ilahi di dalam yang menusiawi. Maka, bisa dikatakan bahwa perjalanan ‘melintas batas’ ini sebenarnya tidak lain merupakan pengalaman kembali kepada originalitas absolut eksistensi pribadi, sebagai insan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (T. Krispurwana Cahyadi, 2007, hlm. 44).
Belalak dan Kearifan Berladang Suku Dayak
Belalak, di satu sisi, mau menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang dialami seseorang belum sampai pada titik yang diharapkan. Namun di sisi lain, juga mau menunjukkan bahwa apa yang belum terpuaskan itu tidak lalu dipenuhi secara liar dan membabi buta. Akan tetapi, jika tidak dimaknai dan dihayati dengan benar, ada bahaya kalau belalak dapat sungguh mengubah manusia menjadi makhluk yang tak pernah puas. Menjadi makhluk yang serakah.
Masifnya kerusakan hutan barangkali bisa kita angkat sebagai contoh dari keserakahan manusia. Dikendalikan oleh keserakahannya, manusia tidak lagi melihat alam sebagai sesama ciptaan yang wajib untuk dilindungi, tapi hanya sebagai objek yang wajib untuk dieksploitasi. Hanya dilihat sebagai sarana pemuas kebutuhan.
Cara berladang dalam suku Dayak, menurut hemat saya, menghadirkan penghayatan yang benar dari makna belalak yang sesungguhnya. Saya katakan benar dalam artian bahwa di satu sisi, manusia sungguh menyadari dirinya adalah makhluk yang tak pernah puas, tapi di sisi lain, dia bisa mengontrol diri agar hidupnya tidak diperbudak oleh nafsu serakahnya. Bahwa berladang bukan didorong oleh motif ekonomi, melainkan semata-mata untuk meneruskan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur adalah bukti nyata bagaimana manusia memanfaatkan alam bukan hanya sebagai sarana pemuas kebutuhan.
Kemampuan para peladang untuk mengendalikan diri didasari oleh kesadaran bahwa alam itu memberikan kehidupan kepada mereka. Maka, mereka tidak boleh serakah dalam menggarapnya. Mereka harus bersikap baik dan sopan ketika memanfaatkan atau bersentuhan dengan alam. Alam itu memiliki "roh", "jiwa" tertentu yang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka dari itu harus dihormati. Rasa hormat diungkapkan dengan sikap dan tutur kata yang sopan dan santun, serta lewat upacara atau ritual adat.
Pelibatan tanda-tanda alam dalam berladang menjadi bukti lain bagaimana para peladang melihat alam sebagai sesama ciptaan yang wajib untuk dijaga dan dilindungi. Bagi para peladang, tanda-tanda alam merupakan sarana yang melaluinya Yang Ilahi menyampaikan pesan apakah lokasi tertentu boleh digarap atau tidak. Bagian-bagian tertentu dari hutan atau lahan tidak pernah bisa digarap, apabila dianggap tidak direstui oleh Yang Ilahi.
Terhadap kepercayaan suku Dayak bahwa alam itu memiliki kekuatan mistis, ruang untuk diskusi masih terbuka lebar. Manusia-manusia modern dengan segala kecerdasan intelektualnya dapat dengan leluasa mempelajari kearifan-kearifan lokal dalam komunitas-komunitas asli.
Namun satu hal yang harus mereka garis bawahi, kearifan lokal yang memiliki karakter lekat dengan locus (tempat), tidak sekadar mengatakan sudut pandang geografis. Sebuah tempat tinggal yang berupa dataran atau pegunungan atau pinggiran pantai, atau pinggiran hutan atau sawah, bukan hanya perkara geografis, melainkan mengurai suatu kebijaksanaan khas. Kebijaksanaan berupa produk relasionalitas manusia dengan alam tempat dia bertumbuh dan berkembang.
Apa yang mau ditekankan di sini ialah, meski dengan kekuatan akal budinya kaum intelektual mampu membongkar ketidaklogisan mitos, fenomena, legenda dan sejenisnya dalam sebuah komunitas adat, mereka juga harus memahami bahwa mitos bukanlah kisah khayalan atau hanya sebuah cerita untuk pengantar tidur. Mitos merupakan suatu "rasionalitas" dalam bentuk perdananya yang merupakan produk relasionalitas manusia dengan alam hidupnya (Armada Riyanto dkk (Eds.), 2015, 28-31).
Hal tersebut menjadi penting untuk mereka pahami agar komunitas lokal tidak dipandang sebagai manusia terbelakang, tak beradab, hanya karena meyakini Yang Ilahi itu hadir pada pohon-pohon besar, sungai, batu-batu besar dan tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan.
Dan, jangan sampai pula mereka secara gegabah malah mengusulkan agar hutan dibabat habis karena bisa mendatangkan penyakit bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang selalu membersihkan sebuah tempat atau lokasi yang bisa menjadi sumber dan mendatangkan penyakit. Namun dalam relasi manusia dengan alam, cara seperti itu tentulah tak selalu bisa diterapkan.
Alam memang bisa mendatangkan sakit penyakit pada manusia. Secara logika, bila hutan dibabat habis maka penduduk bisa jadi terbebas dari segala sakit penyakit. Akan tetapi, jika pembabatan hutan adalah solusinya, maka dijamin akan hadir bencana, penyakit dalam bentuk yang lebih ganas dan mematikan. Yakni, dalam rupa banjir, tanah longsor dan sebagainya.
Mahatma Gandhi suatu kali pernah mengatakan: “Bumi menyediakan cukup bahan untuk memuaskan setiap keperluan manusia, tetapi bukan untuk keserakahan manusia.”
***