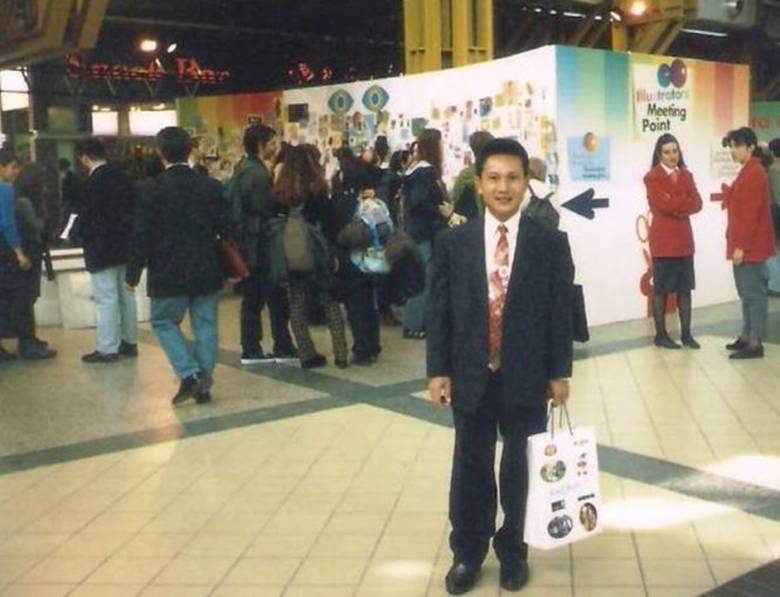Jalan Pulang [4] Adakah Mitos itu Benar Adanya?
![Jalan Pulang [4] Adakah Mitos itu Benar Adanya?](https://assets.ytprayeh.com/img/4r16185e4776261/b86a3-Untitled design(2).jpg)
Minggu pagi. Sehari setelah pulang dari rumah sakit, Ibu yang semalam masih tampak bahagia dan membaik saat makan malam bersama, hari ini tidak hendak beranjak dari tempat tidurnya. Sarapan dan teh manis pagi tak jua menggodanya untuk segera dicicipi. “Nanti,” begitu jawabnya singkat lalu kembali memejamkan mata. Gairah dan semangat yang sempat ditunjukkan menjelang pulang dari rumah sakit hari Sabtu kemarin, bukannya menguat, tapi justru seolah perlahan melemah.
Saya raba badannya, lalu keningnya, terasa menghangat. Thermometer tubuh pun saya selipkan di ketiaknya, untuk mendapatkan angka pasti. Benar, suhu tubuh pagi itu berada pada batas angka 37 derajat. Tidak terlalu mencurigakan menurut saya, bisa saja itu karena masih dalam kondisi baru bangun, apalagi status Ibu adalah pasien rawat jalan, bukan orang sehat bugar. Toh demikian, kami berganti-ganti merajuk dan membujuk Ibu agar bangun sebentar, mencicip sesuap-dua suap sarapan, agar obat-obatan yang dibawakan dari rumah sakit—ada sembilan macam—dapat segera diminum. Namun, segala rajuk dan rayu tak ada yang mempan, hanya disambut dengan gelengan kepala, mata yang dipejam-pejamkan, juga mulut yang ditutup rapat. Tidurnya pun diposisikan miring menghadap dinding. Entah itu posisi yang paling nyaman atau sekadar untuk menghindari kami semua.
“Kita coba sebentar lagi, barangkali Ibu masih capek setelah opname di rumah sakit,” begitu saya mencoba menenangkan seisi rumah. Ya, dalam hal ini keputusan apa pun ada di tangan saya. Di rumah itu hanya ada saya, anak saya, pramurukti, dan tetangga dekat yang bergantian datang bermaksud menengok Ibu.
Hari ini rencananya adik saya yang bertugas di Nabire, Papua akan datang. Saya memang sempat memintanya pulang karena sewaktu di rumah sakit, sekali-dua kali Ibu menanyakannya. “Kok belum datang?” begitu pernah tiba-tiba Ibu bertanya, tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud. Beberapa nama saya sodorkan, disambut gelengan kepala, lalu begitu nama adik saya sebut, Ibu mengangguk. Penerbangan Nabire – Jogja cukup panjang dan melelahkan, berdurasi 5-6 jam ditambah sekali transit di Makassar. Jadi, kira-kira selepas pukul 6 sore ia baru akan tiba di rumah. Tak jadi soal, asal kedatangannya hari ini bisa menjadi pelipur rindu dan pemulih kesehatan Ibu.
Hari mulai memasuki paruh keduanya. Tak ada yang bisa diceritakan selain Ibu yang tetap tergolek di tempat tidurnya. Air raksa dalam thermometer tubuh kini mulai menyentuh angka 38 derajat. Kompres penurun panas yang biasa saya tempelkan pada dahi Ibu bila ia panas, kali selalu disingkirkannya buru-buru. Sementara, sebutir obat pun tak berani kami masukkan mengingat perut Ibu yang masih kosong karena tak ada asupan apa pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Para tetangga yang datang hanya bisa sebatas memijat kaki dan bergantian membalurkan minyak kayu putih ke tubuh Ibu, sambil mencoba mengajak bicara, bercerita, atau sekadar mengobrol di antara mereka.
Inilah salah satu budaya bangsa yang membanggakan, harus dijaga, dan jangan sampai sirna dari bumi Nusantara. Dengan penuh kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, mereka datang membantu dan menguatkan tanpa memandang perbedaan. Pemandangan ini sungguh menyejukkan. Sebuah praktik toleransi yang membumi. Toleransi atau tolerantia dalam bahasa latin mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan, bukan hanya dalam hal beragama, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat. Dalam kearifan lokal Jawa pedoman sikap toleransi ini dinamakan dengan istilah tepa selira (dibaca tepo seliro), yakni sikap menjaga hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat latar belakang atau identitasnya untuk saling menghormati dan tolong-menolong.
Sebuah pemandangan yang lalu membangkitkan kenangan masa kecil saya ketika kami, anak-anak kampung sini, bermain dan bersenda gurau tanpa sekat-sekat perbedaan. Yang ada hanya senang dan bahagia bersama. Permainan demi permainan luar ruang (outdoor), kami lalui bersama, bermain kelereng, petak umpet, balap kereta jeruk bali, senapan pelepah daun pisang, hingga bermain hujan-hujanan di halaman rumah. Mereka, teman bermain saya, kini sudah tersebar ke berbagai pelosok negeri dengan pelbagai peran masing-masing, entah sebagai dokter, guru, dosen, ASN, pengusaha, bahkan terakhir saya mendapat kabar ada yang baru saja naik pangkat menjadi jenderal—meski di kutub yang berlawanan saya juga menjumpai teman masa kecil yang mengayuh hidup sebagai petugas kebersihan keliling, penambal ban, atau yang paling tragis adalah mengalami gangguan jiwa. Yah, begitulah hidup. C'est la vie menurut ekspresi idiomatik Prancis yang sangat tua dan sangat umum itu.
Lepas waktu magrib, adik saya akhirnya tiba juga, bersamaan waktunya dengan kehadiran seorang kakak sepupu saya. Sebagaimana sejak adanya Covid-19 kami selalu berkomitmen menjaga protokol kesehatan, mengingat Ibu memiliki sejumlah komorbid, maka ia saya minta membersihkan diri terlebih dulu sebelum menemui Ibu di kamar. Tak ada tanda-tanda kondisi membaik, segala tawaran ditampik, termasuk tawaran untuk memeriksakan diri ke dokter. Wajah-wajah tegang dan penuh khawatir terpancar dari mereka yang datang ke rumah.
Seusai mandi, dengan tetap menjaga jarak dan bermasker, adik saya pun menemui Ibu, menyapanya dengan suara nyaring. Kami berharap momen surprise ini bisa menggugah semangat Ibu. Nyatanya, asa kami tak bersambut. Ibu tetap bergeming, hanya mengangguk sedikit, lalu memilih memejamkan mata. Sambutannya sangat bertolak belakang dari biasanya bila kami anak-anaknya pulang. Sedikit tentang kami, saya dua bersaudara dengan dua panggilan hidup yang ibarat “langit dan bumi”. Ya, adik saya panggilannya ke “langit” karena ia memilih panggilan hidup sebagai seorang imam Katolik dan saat ini tugas pelayanannya ada di Nabire, Papua. Sementara, panggilan hidup saya ada di “bumi” menjalani tugas sehari-hari di sebuah perusahaan swasta di Jakarta guna menafkahi keluarga.
Melihat kondisi Ibu, kami memutuskan mengadakan doa khusus untuk orang sakit dan hanya diikuti oleh kami yang ada, dipimpin oleh adik saya. Suasana sangat haru dan mencekam, betapa tidak, karena umumnya doa ini dibawakan bagi mereka yang benar-benar dalam kondisi sudah sangat kritis. Dari ujung mata, saya bisa melirik para peserta doa yang mulai berkaca-kaca, dan berdoa dengan suara bergetar. Terlebih lagi ketika adik saya mengakhiri doa dengan mengatakan, “Yaah... kita tunggu saja...,” sontak, helaan napas dan suara jerit tercekat terdengar di antara mereka.
Kini semua mata memandang ke saya, menunggu komando. Dengan suara lirih, saya mengatakan, “Baik, sepertinya Ibu harus kita bawa kembali ke rumah sakit.” Kalimat lirih itu, disambut dengan sigap para ibu yang membantu menyiapkan ini-itu, termasuk mencari bantuan tetangga pria karena kali ini Ibu tidak mungkin berjalan sendiri. Ia harus digotong menuju mobil yang siap mengantar kembali ke rumah sakit. Pemandangan yang belum pernah terjadi selama ini.
Sesaat sembari bersiap berangkat, kakak sepupu berbisik lirih di telinga saya, “Percaya, tidak percaya, apakah ini ada hubungannya dengan kepulangan ibumu dari rumah sakit di hari Sabtu kemarin?”
Saya tidak bisa menjawab, mencoba sedikit menarik garis bibir, dan menatap wajahnya, “Saya tak mau berandai-andai, ... doakan Ibu ya, Mas....”
Percakapan teramat singkat itu, nyatanya menancap kuat dalam pikiran dan benak saya di sepanjang perjalanan kembali menuju rumah sakit. Adakah mitos itu benar adanya? Saya tak hendak memungkirinya, tapi tak juga lantas gegabah memercayainya. Satu yang saya yakini, bahwa sebagai sebuah produk kearifan lokal, mitos itu barangkali telah melalui tempaan perjalanan waktu yang teramat panjang lalu bersemayam damai di dalam selimut semesta. Ia tak lagi terjangkau, pun misterinya tetap terjaga hingga hari ini. (bersambung)