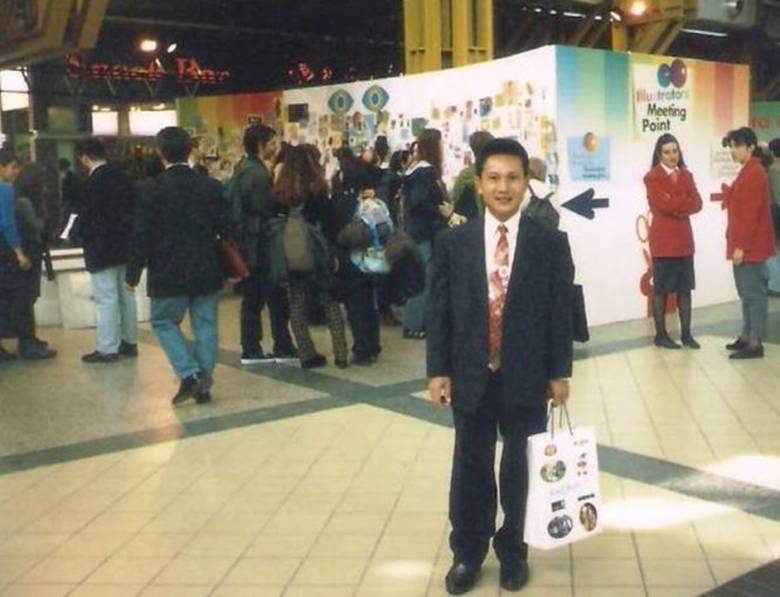Tilikan Eksistensialisme dan Fenomenologi atas “Melihat”-nya Megawati Soekarnoputri

"Saya ngeliatin ibu-ibu beli minyak itu, saya sampai ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu sama almarhum suami saya, emoh aku. Lebih baik saya masak di rumah, direbus kek, dikukus kek. Sampai saya kalau sekarang kita melihat, hebohnya minyak goreng ini. Saya sampai ngelus dada. Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng kok sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa nggak ada? Itu menu Indonesia juga lho. Lha kok sampai njelimet gitu." (Kompas.com, 18/03/2022)
Begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Ibu Megawati Soekarnoputri ketika melihat ibu-ibu yang rela mengantre untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Dari melihat antrean itu, Ibu Megawati pun sampai mengelus dada.
Tulisan ini mau mencoba meneropong “melihat”-nya sang ketua umum PDI Perjuangan dari persepktif eksistensialisme dan fenomenologi. Akan tetapi, sebelum sampai ke sana saya ingin mengawalinya dari film The Pianist. Mungkin dari antara kita sudah ada yang pernah menontonnya. Sebuah karya dari seorang sutradara dan aktor terkenal asal Polandia, Roman Polanski. Film ini berangkat dari kisah nyata dari kehidupan seorang pianis asal Polandia yang masih keturunan Yahudi, Władysław Szpilman (diperankan oleh Adrien Brody).
Degan latar belakang pendudukan Jerman atas Warsawa, film ini mengisahkan perjuangan seorang anak manusia untuk bertahan hidup. Sebagai seorang pianis, Szpilman tentulah dikenal banyak orang. Dia juga memiliki beberapa teman orang Polandia yang sangat baik kepadanya. Merekalah yang banyak membantunya dalam mencarikan tempat persembunyian dan mengantarkan makanan. Tindakan mereka tersebut adalah nyawa taruhannya. Sebab, siapa pun yang berusaha melindungi atau menyembunyikan orang-orang Yahudi akan turut dibantai oleh tentara Jerman.
Szpilman selalu lolos dari kejaran tentara Jerman. Namun, ketika situasi sudah semakin genting, teman-temannya tidak bisa lagi mengantar makanan untuknya seperti biasa. Peluang untuk bertahan hidup pun semakin menipis. Dalam situasi genting seperti itu, kepada seorang teman Polandia yang menemuinya di tempat persembunyiannya, dan menyampaikan bahwa mereka kesulitan mencari makanan untuknya, sambil melepas jam tangannya, lalu menyerakannya kepada temannya itu, ia berkata, “Ini. Jual ini. Makanan lebih penting daripada waktu”.
Apakah bagi Szpilman waktu itu sungguh tidak penting? Tentu saja sangat penting dan berharga. Dengan memiliki waktu (jam tangan), dia bisa merancang hidup dengan baik sekalipun berada dalam ketidakpastian akan keselamatan hidupnya sendiri. Namun, waktu tersebut (jam tangan) harus ia korbankan karena ada sesuatu yang lebih penting untuk ia dapatkan supaya bisa bertahan hidup, yakni makanan.
Hidup itu untuk Makan atau Makan itu untuk Hidup?
Kisah hidup Szpilman yang dikisahkan dalam film The Pianist, mengingatkan saya pada dua buah prinsip hidup yang terhadapnya setiap kita diminta untuk menentukan pilihan: hidup itu untuk makan atau makan itu untuk hidup.
Hidup dan makan itu ibarat dua sisi mata uang yang takbisa dipisahkan. Di mana ada kehidupan, pastilah di sana ada kebutuhan untuk makan. Dan di mana ada makanan, pastilah di sana ada kehidupan.
Soal prinsip hidup itu saya juga pernah ditanya oleh seorang rekan. Saat itu saya memilih kalau makan itu untuk hidup. Kala itu saya berpikir kalau makan, pertama-tama, memang untuk hidup. Dengan makan saya akan memperoleh energi untuk melakukan segala aktivitas serta tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya.
Mengapa saya tidak memilih yang pertama? Apa yang salah kalau memang hidup itu untuk makan? Saya tidak memilihnya, karena dalam benak saya hidup ini terkesan sangat dangkal kalau hanya untuk makan saja. Bisa-bisa saya akan dicap sebagai orang yang rakus kalau dalam benak saya yang ada hanya soal makan dan makan terus.
Akan tetapi dalam perjalanan waktu saya bertanya, sungguhkah mereka yang menjalani kehidupannya dengan menempatkan perkara makan di atas segalanya, mesti dicap sebagai orang yang rendah kualitas hidupnya? Sebagai orang yang hanya memikirkan perkara duniawi semata? Terhadap mereka ini, yang dari hari ke hari berkeringat dan berdarah-darah mencari sesuap nasi, saya pribadi tidak akan berani menilai bahwa kualitas hidup mereka sangatlah dangkal karena hanya memikirkan urusan perut.
Kisah hidup Szpilman bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya, pada titik tertentu, seakan menampilkan kalau hidup itu seolah menjadi medan perjuangan dalam mencari makanan. Meski yang terpenting baginya sekarang ialah bisa mendapatkan makanan agar bisa bertahan hidup, Szpilman tidak sedang mengajak untuk memilih prinsip mana yang lebih bagus dan penting: Apakah hidup itu untuk makan atau makan itu untuk hidup?
Sepertinya yang menjadi persoalan bukan perkara memilih prinsip mana yang lebih bagus. Pergulatan dan perjuangan anak manusia untuk bertahan hidup seakan hendak mengingatkan kita kalau kedua prinsip itu seringkali saling tumpang tindih.
Eksistensialisme dan Fenomenologi
Dalam realitas yang sering tumpang tindih itu, barangkali filsafat eksistensialisme dan fenomenologi bisa membantu kita dalam memahami manusia beserta pergulatan hidupnya. Mereka yang menjadi pengikut kedua paham ini tidak akan tergesa-gesa memberi penilaian. Ketimbang sibuk memberi penilaian, mereka akan dengan berani menceburkan diri dalam realitas kehidupan manusia yang seringkali berkeringat dan berdarah-darah dalam usaha untuk bertahan hidup.
Kedua paham ini berusaha memahami manusia dari fenomena atau realitas yang nampak di depan mata. Keduanya melakukan kontak langsung dengan realitas. Dogmatisme atau absolutisme, karena itu, akan ditolak karena dipandang menghalangi obyek kesadaran untuk menampakkan diri apa adanya.
Karena itu, seorang eksistensialis atau fenomenolog ketika berjumpa dengan Szpilman atau mereka yang siang malam tak kenal lelah mencari sesuap nasi, tidak akan berani berkata: “Saudaraku, cukuplah! Jangan diteruskan! Ingat, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan”. Di mata mereka, ungkapan semacam itu hanya sebuah retorika indah namun tanpa makna. Sebab, bagaimana mungkin berkata dengan begitu indah kepada mereka, sementara di hadapan mereka satu butir nasi pun tak ada?
Apakah kedua paham tersebut merupakan kritik terhadap kaum idealis? Boleh dikatakan demikian. Kalau begitu, apa yang keliru dari paham idealisme dalam memaknai realitas? Kritik Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis asal Denmark, terhadap Hegel bisa menjadi contohnya.
Di mata Kierkegaard, seperti ditulis oleh Thomas Hidya Tjaya dalam bukunya Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, filsafat Hegel yang hendak membangun sebuah sistem yang komprehensif, mampu memahami segala-galanya, merupakan sebuah proyek yang ambisius dan tak masuk akal. Menurut Kierkegaard, dengan pemikirannya itu, Hegel praktis menghilangkan daya sengat perasaan-perasaan eksistensial manusia, misalnya kecemasan, kemarahan, penderitaan dan keputusasaan. Ringkasnya, dengan sistem yang dibangun oleh Hegel, filsafat telah melupakan makna menjadi manusia.
Berfilsafat dengan cara Hegel, bagi Kierkegaard, bagaikan naik ke puncak gunung dan memandang ke bawah. Dari puncak gunung orang dapat melihat tatanan atau sistem pengaturan wilayah tersebut. Semuanya kelihatan indah, rapi dan teratur. Yang tidak kelihatan ialah apa yang terjadi di bawah atap rumah dan apa yang bergolak dalam hati penghuni rumah itu: anak-anak yang mengalami kekerasan, suami-istri yang sedang bertengkar, mereka yang berjuang untuk sembuh dari penyakit, para karyawan yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana harus menghidupi keluarganya, seorang pemuda/pemudi yang diputus oleh pacarnya, dan sebagainya.
Posisi “melihat”-nya Ibu Megawati, hemat saya, berada dalam bangunan filsafat yang dibangun oleh Hegel. Dalam hal ini bolehlah kita menempatkan beliau sebagai seorang Hegelian. Beliau memang melihat, tapi melihat dari “puncak gunung” kehidupan sebagai seorang yang memiliki status sosial yang sangat tinggi (seorang mantan presiden; ketua umum partai; ketua Dewan Pengarah BPIP; ketua BRIN).
Karena melihat dari posisi yang sangat tinggi, beliau tidak mampu melihat apa yang terjadi di tempat antrean dan apa yang bergejolak dalam hati ibu-ibu yang sedang ikut mengantre itu. Dalam bahasa Kierkegaard, Ibu Megawati mengabaikan perasaan-perasaan eksistensial para ibu itu, seperti kecemasan, kemarahan, penderitaan dan keputusasaan.
Andai saja Ibu Megawati memahami bahwa manusia itu adalah homo experiens (makhluk yang mengalami). Dengan homo experiens mau mengatakan kalau manusia mencari dan menemukan makna atas hidupnya dari pengalaman hidup sehari-hari. Setiap pengalaman itu memiliki maknanya masing-masing. Hanya saja untuk menemukan maknanya kadang memerlukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Bahkan mungkin tidak sedikit yang memutuskan berhenti di tengah jalan. Terlebih ketika berusaha mencari makna dari pengalaman yang pedih, menyakitkan, mengecewakan, dst.
Frasa “menemukan makna hidup dari realitas hidup sehari-hari” merupakan salah satu tema yang digumuli dalam hermeneutika Paul Ricoeur. Hermeneutika sendiri dipahami sebagai seni memahami sebuah teks. Adalah teks-teks kitab suci yang semula menjadi objek utama penafsiran. Namun, di kemudian hari realitas hidup manusia itu sendiri yang banyak digumuli.
Bagi Ricoeur, demikian ditulis Romo Armada Riyanto dalam bukunya Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen, memahami teks bukan hanya memahami makna yang terkandung di dalam teks itu, melainkan juga lewat teks itu merefleksikan makna hidup kita, karena teks mengacu kepada kehidupan, kepada dunia di luar teks itu. Dunia di luar teks itu dinamakan dengan konteks, yang menunjuk kepada ruang keseharian hidup manusia, pengalaman hidup sehari-hari.
Sebagai homo experiens, manusia diajak untuk menemukan makna hidup dari setiap pengalaman yang ia jumpai dalam keseharian hidupnya. Namun, makna tersebut baru akan ditemukan kalau manusia berani memasuki sebuah teks atau realitas yang kerap kali mengganggu rasa nyamannya.
Sebagai makhluk yang acap kali lebih memilih yang enak-enak saja, Ricoeur sepertinya hendak mengajak kita manusia untuk berani bergumul dalam realitas kekhawatiran, kecemasan, kegagalan, kesendirian, kemalangan, kelaparan, sakit, keputusasaan, dst, agar bisa semakin memahami diri dengan lebih baik. "Hidup yang tak pernah direfleksikan, tak layak untuk dihidupi”, demikian kata filosof Sokrates.
Realitas yang kerap kali mengganggu rasa nyaman itulah yang kiranya belum atau mungkin enggan dimasuki oleh Ibu Megawati. Sebab seandainya berada dan bergumul dalam realitas itu, beliau tidak akan tega mengeluarkan kata-kata yang melukai hati rakyat kecil.